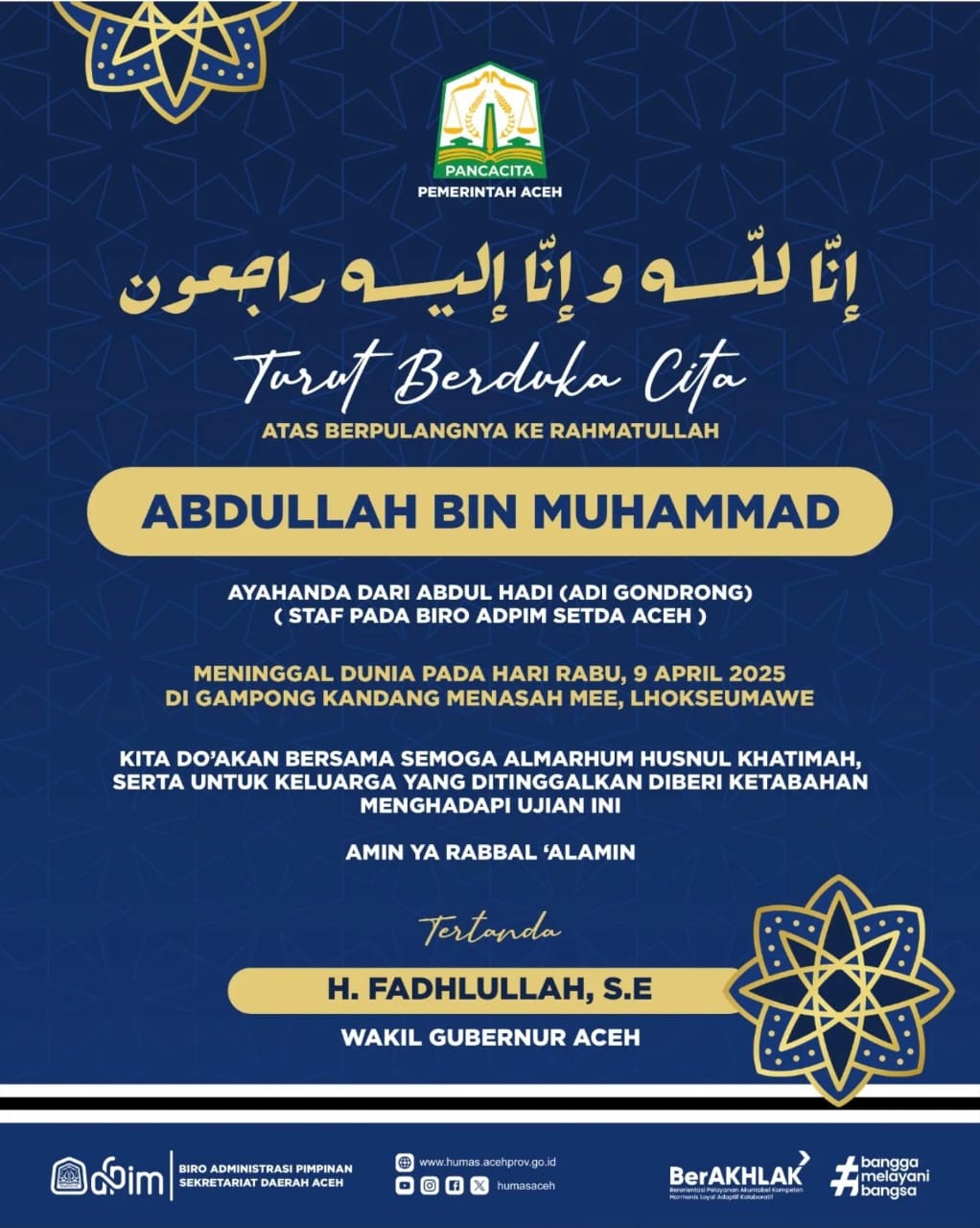Salah Satu Pilihan Kita Menangis?
Oleh Usamah El-Madny*)
“Sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum lahir”.
Edmund Burke, Politikus dan filsuf dari Inggris, 1729 – 1797.
Bagi masyarakat Aceh, bulan Maret merupakan salah satu paruh waktu yang memiliki nilai sejarah tersendiri.
Tapi nilai sejarah itu — seperti juga di paruh waktu lain —- menjadi tidak bernilai apapun ketika masyarakat sebagai pewaris dan pemilik sejarah itu sendiri tidak sadar lagi bahwa ruang dan waktu yang mereka lewati itu merupakan objek sejarah yang harus dinapaktilasi mereka dalam rangka menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang, untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik dan berkesinambungan.
Kenapa dengan bulan Maret?.
Pada bulan Maret, 148 tahun lalu, Aceh atau tepatnya Kesultanaan Aceh Darussalam masih berdiri tegak sebagai sebuah negara bangsa yang besar.
Bangunan kokoh Kesultanan Aceh Darussalam itu terancam rontok dan hancur lebur sehubungan dengan pernyataan perang dari Kerajaan Belanda.
Pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh
Pada Rabu, 26 Maret 1873, bertepatan dengan 26 Muharam 1290 Hijriah Kerajaan Belanda mengumumkan pernyataan perang kepada Kesultanan Aceh Darussalam.
Maklumat perang itu dibacakan dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh di antara Pulau Sabang dan daratan Aceh.
Pernyataan itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda, F. N. Nieuwenhuijzen. Sebulan kemudian Senin, 6 April 1973, Belanda mendaratkan pasukannya di Pante Ceureumen, Ulee Lheue di bawah pimpinan, Mayor Jenderal JHR Kohler.
Sejak itu perang demi perang terus berlangsung di Aceh.
Nyaris di semua medan pertempuran kekuatan armada Aceh jauh kalah dari serdadu Belanda. Secara pelan dan pasti, secara de facto Kesultanan Aceh Darussalam telah selesai.
Istana raja dikuasai. Sultan dan keluarganya lari ke hutan. Sedangkan secara de jure Kesultanan Aceh Darussalam masih ada karena Sultan Aceh sekalipun telah kalah perang tidak mengaku kalah dan tidak menyerahkan kedaulatan kepada Kerajaan Belanda.
Kesultanan Aceh Darussalam baru benar-benar lenyap secara secara de jure ketika rakyat Aceh yang diwakili elitnya menyatakan bergabung dan menjadi bagian dari NKRI.
Setelah Kesultanan Aceh lenyap secara de facto dan de jure —- sebagaimana halnya juga sejumlah kerajaan di wilayah lain —- bagaimana seharusnya sikap dan ekspresi kita?.
Kita bisa bersikap macam-macam.
Misalnya, tetap mengenang kejayaan masa lalu kita sebagai sebuah bangsa dan melawan lupa agar masa lalu kita dapat menjadi spirit masa depan. Karena, siapapun yang yang melupakan masa lalu akan kehilangan masa depannya. Banyak suku bangsa di dunia yang gagal merumuskan masa depan mereka karena terlanjur memutuskan masa lalu mereka. Contoh kongkrit adalah Suku Kurdi baik yang bertebaran di Turki atau Irak.
Atau, kita bersikap memutuskan atau melupakan saja masa lalu itu. Alasannya sederhana, karena hidup kita menuju masa depan. Bukan mundur ke belakang.
Kedua pilihan sikap di atas bebas jadi pilihan kita.
Sikap tidak melupakan masa lalu, misalnya, dengan mudah kita jumpai di Pulau Jawa. Di Jawa institusi kerajaan masih ada sekalipun kewenangan telah diamputasi.
Situs- situs mereka terawat baik. Bagi sebuah peradaban situs itu penting. Sebuah peradaban dianggap mitos ketika situs sebagai bukti peradaban tidak ada lagi.
Sebagai dampak kalah perang dan tidak mau berdamai dengan penjajah, di Aceh lembaga kesultanan tidak ada jejaknya lagi. Keturunan sultan hidupnya morat marit dan nyaris tidak terindu fiksasi lagi.
Situs yang menunjukkan bahwa kita pernah punya masa lalu dalam bentuk negara bangsa juga satu persatu hilang lenyap dengan berbagai cara dan sebab.
Kita pernah punya sultan dan sultanah. Tapi sebagian dari mereka tidak kita tahu di mana kuburannya. Kalaupun ada satu dua kuburan yang diketahui tapi kondisinya begitu meprihatinkan.
Dua puluh atau tiga puluh tahun kemudian bukan tidak mungkin ada di antara anak cucu kita yang berpendapat bahwa Kesultanan Aceh dan kejayaannya hanya mitos.
Mitos adalah keyakinan tanpa dukungan fakta. Sebenarnya bukan tidak ada fakta, tapi fakta yang ada terkait keberadaan masala lalu itu pelan pelan hilang ditelan zaman.
Peristiwa pada bulan Maret yang banyak kita tidak ingat lagi yang saya sebutkan di atas hanyalah fenomena gunung es semakin rentannya hubungan kita sebagai sebuah komunitas dengan masa lalu.
Dengan kata lain semakin banyak momentum sejarah masa lalu kita sebagai sebuah entitas suku bangsa yang terlupakan maka itu semua sekaligus konfirmasi bahwa sebagian besar kita telah memutuskan mata rantai peradaban kita dengan masa lalu.
Tentu dalam konteks ini tidak ada pihak yang perlu kita salahkan. Inilah konsekuen bangsa kalah perang dan kemudian ratusan tahun hidup tanpa pemimpin dan kepemimpinan yang efektif.
Peninggalan-peninggalan masa lalu itu kondisi hari ini sama sekali tidak menarik untuk kita jadikan objek destinasi dengan berbagai sebab. Hal ini diperparah lagi kondisi anak-anak muda kita yang tidak tertarik membaca sejarah Aceh.
Diperparah lagi di sekolah-sekola kita juga tidak maksimal diajarkan secara komperehensif konten pelajaran sejarah sejarah — paling kurang sebagai muatan lokal —- untuk merawat “chauvinisme” keacehan.
Pelan dan pasti kita kita harus ikhlas meleburkan diri secara totalitas dalam peradaban baru dalam bingkai NKRI. Padahal sesuai prinsip kebhinnekaan negara kita, loyalitas tunggal kepada NKRI bukan bermakna setiap suku bangsa yang ada di Indonesia harus mengisolasi diri mereka dengan peradaban masa lalu mereka.
Menghancurkan dan memusnahkan bukti-bukti peradaban. Peradaban masa lalu suka bangsa itulah —- termasuk bukti-bukti peradaban —- yang justru kemudian memperkaya khazanah peradaban Indonesia.
Bahkan dengan merawat bukti-bukti peradaban — misalnya dalam bentuk situs —- maka kita mendapatkan keuntungan ganda sekaligus: Bukti keperkasaan peradaban kita, sekaligus menjadi objek distinasi sejarah dan wisata yang produktif.
Last but not least , Edmund Burke, Politikus dan filsuf dari Inggris, 1729 – 1797, mengingatkan kita bahwa “sejarah adalah suatu perjanjian di antara orang yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, dan mereka yang belum lahir”.
Dengan kata lain sejarah adalah koneksitas antara tiga ruang waktu: masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.
Nah, ketika kita melupakan sejarah maka di saat itu juga kita telah melakukan tindakan diskoneksitas sejarah. Dampaknya tidak kecil.
Sebagai sebuah suku bangsa kita dinilai tidak memiliki sejarah. Di planet bumi ini kita menjadi pendatang baru, yang tidak punya masa lalu sekaligus tidak jelas masa depan.
Kehilangan masa lalu merupakan salah satu nasip bangsa kalah perang. Dan yang bisa dilakukan hanya menangis. Karena tidak berdaya di atas reruntuhan peradaban masa lalu yang kita telah lupakan itu telah dibangun fondasi peradaban baru
Di atas segala kenyataan yang ada, harapan itu masih ada. Sejumlah pihak di tengah- tengah kita masih setia merawatan ingatan sejarah Aceh dan terus berikhtiar melawan lupa.
Urat nadi sejarah dan peradaban kita masih berdetak, sekalipun pelan. Artinya harapan itu masih ada. []
*) Penulis adalah Kolumnis dan Redaktur Theacehpost.com