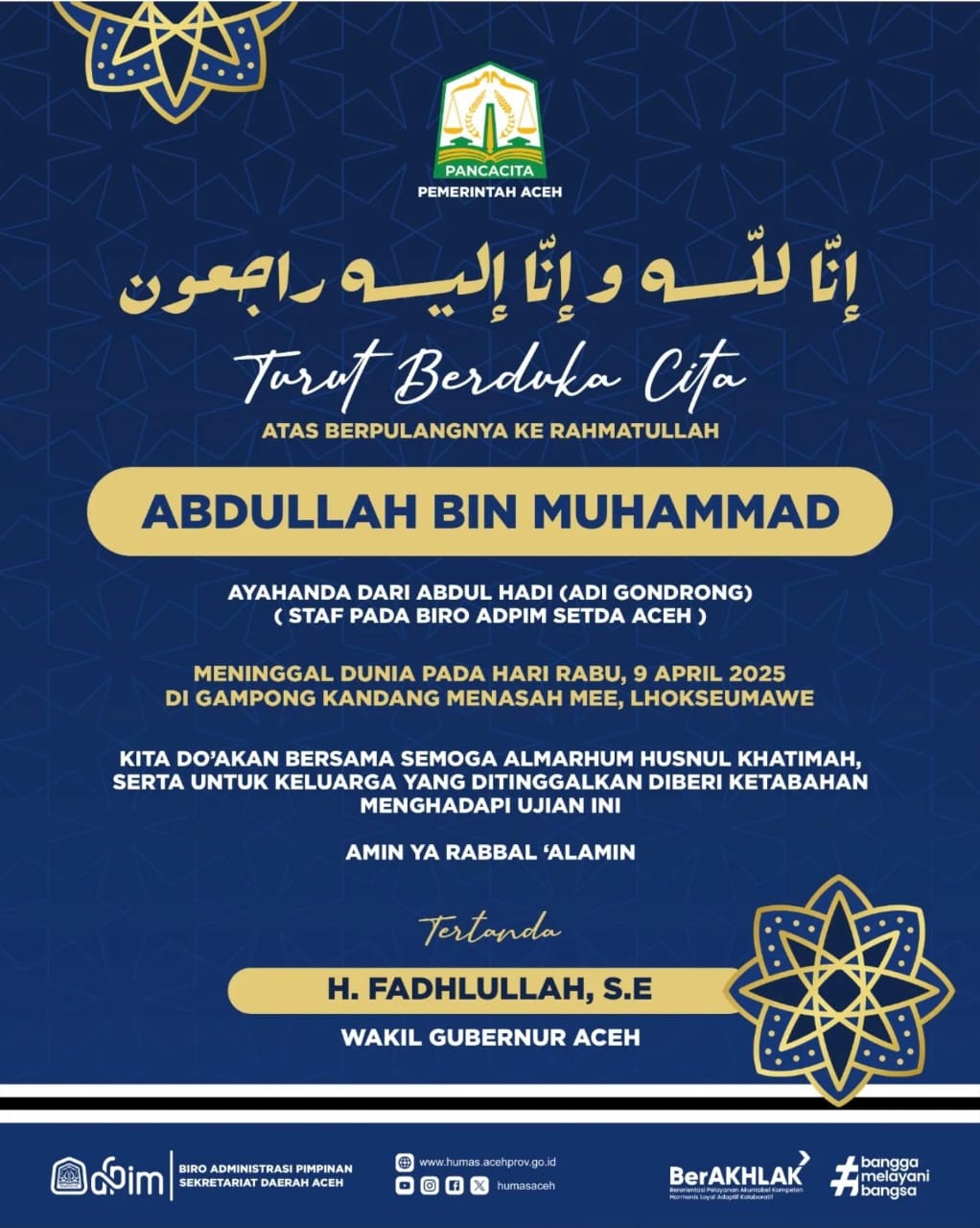Emping Terakhir untuk Ayah
Angin pagi di kampung selalu membawa aroma kenangan. Bagi Usman, aroma itu adalah campuran dari wangi tanah basah, asap kayu bakar, dan emping yang sedang dijemur. Setiap kali ia mencium wangi itu, hatinya terlempar ke masa lalu, ke masa di mana suara langkah kaki ayahnya, Abdurrahman, masih terdengar setiap subuh—berderap pelan menyusuri pematang sawah.
Abdurrahman adalah satu dari delapan bersaudara, tapi satu-satunya yang sangat terasingkan dri kelurga besarnya dan memilih tinggal di kampung, hidup sederhana di rumah kayu yang dibangunnya sendiri dengan tangan kasar penuh kapalan. Berbeda dengan saudara-saudaranya yang memiliki warisan dari sang ayah. Abdurrahman memilih jerih payah sendiri untuk keluarga kecilnya.
“Orang boleh kaya di mata dunia, tapi tak semua bisa kaya hati,” begitu ucapnya suatu malam sambil menaburkan garam ke atas tumisan daun pepaya. Usman, waktu itu masih bocah, hanya mengangguk—belum paham betul makna kalimat itu. Tapi kini, tahun berlalu setelah kepergian sang ayah, kalimat itu terus menggema dalam pikirannya.
Tahun 2002 adalah tahun yang takkan pernah Usman lupakan. Ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Tidak ada tanda-tanda. Hanya pagi itu, emping terakhir yang dijemur ayahnya belum sempat diangkat. Hari itu pula, Usman merasa rumah mereka berubah menjadi lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar terang.
Sejak kepergian ayah, cahaya dalam rumah itu meredup. Ibunya lebih banyak diam, kakak usman memlih berhenti sekolah dan merantau ke kota, adik-adiknya kehilangan semangat belajar, dan Usman—saat itu baru berusia 7 tahun—harus belajar menjadi dewasa terlalu cepat. Ia sering menggantikan ayah ke sawah setiap sekolah usai, mengambil upahan sebagai buruh tani, dan sesekali menjual emping buatan ibunya ke pasar untuk menambah penghasilan.
Tahun berlalu. Usman, kini sudah dapat berdamai dengan kehidupanya, walaupun masih menyimpan satu toples kecil berisi emping di atas lemari kayu tua milik ayah. Emping terakhir yang tak sempat digoreng hari itu. Sudah tak bisa dimakan, tentu saja. Tapi baginya, emping itu adalah warisan—pengingat tentang nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan cinta yang tulus dari seorang ayah.
Pagi ini, Usman membawa toples itu ke bawah pohon jati tempat ayah dulu biasa duduk seusai bekerja.
“Ayah,” gumamnya pelan, menatap langit yang biru jernih. “Emping ini sudah terlalu lama menunggu. Aku pikir, sudah waktunya menemanimu.”
Dengan hati-hati, ia membuka tutup toples, lalu menaburkan emping itu ke tanah. Angin berhembus lembut, membawa serpihannya menyatu dengan alam. Seolah menjawab, sehelai daun jati gugur dan jatuh tepat di pangkuan Usman.
Ia tersenyum.
Mungkin, itulah pelukan terakhir dari ayah.
****