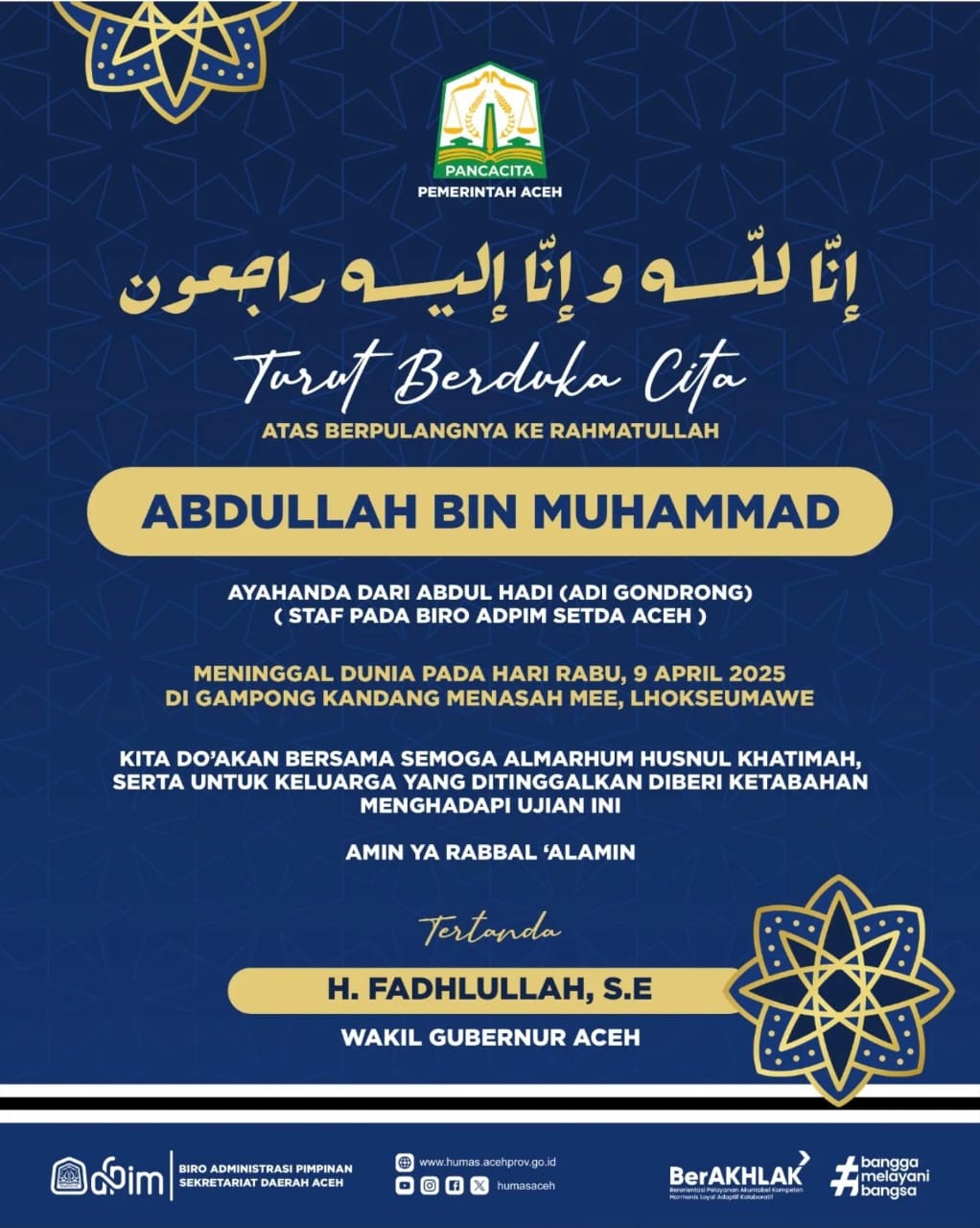Buku Orang Jawa di Suriname: Ruang dan Kesadaran Eksistensial Kaum Urban
Oleh Mahan Jamil Hudani*
Pertumbuhan penduduk yang luarbiasa cepat negeri kita, khususnya yang terjadi di kota besar ditambah dengan arus urbanisasi menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. salah satu imbasnya adalah, kaum urban tak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan banyak aktivitas. Secara umum mereka tinggal di rumah-rumah yang sempit dan padat penduduk. Rumah mereka tak memiliki halaman bahkan banyak pemukiman tak memiliki akses jalan yang cukup untuk dilewati satu kendaraan roda empat. Lebih parah lagi banyak ruang terbuka untuk publik telah hilang seperti lapangan bermain bola atau tanah lapang, taman bermain, atau ruang hijau dengan banyak pepohonan rindang.
Ruang-ruang yang hilang di masyarakat urban tersebut menjadi keresahan sekaligus kesadaran yang kemudian menjelma puisi-puisi dalam buku Orang Jawa di Suriname (OJS). Setidaknya ada 18 puisi dari 66 puisi yang benar-benar memakai kata ruang sebagai judul dan mencoba memaknai ruang-ruang tersebut, serta beberapa puisi lain pun menggunakan kata-kata ruang sebagai kesadaran utama yang ingin dibangun. Puisi-puisi lain – yang sebenarnya berbicara persoalan umum manusia, alam, dan masyarakat – juga pada akhirnya mau tak mau terasosiasi pada kesadaran utama yang menjadi perhatian sang penyarir. Ini sangat mungkin karena sang penyair memang sedang mengalami momentum puitik akan ruang yang ia renungkan dan kesadaran puncak karena hilangnya ruang-ruang tersebut.
Mungkin tema tentang ruang bukan suatu hal yang istimewa bagi masyarakat urban karena banyak mereka memang mengalami hal serupa, hilangnya ruang untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain dengan keluarga sambil berlari-lari di dalam rumah dan sekitarnya, atau bingung sekadar menaruh barang-barang atau kendaraan, lalu menjadi hal yang biasa karena konsekuensi hidup menjadi masyarakat urban. Menjadi istimewa karena kemudian Iman tak sekadar memaknai itu secara fungsional namun juga eksistensial dalam kerangka yang lebih luas sebagai seorang manusia yang hidup sebagai mahluk sosial. Bagaimanapun juga puisi bukanlah sekadar ekspresi namun bahasa komunikasi yang penuh pesan dan simbol yang kemudian bisa direinterpretasi oleh pembaca.
Awalnya kita bisa saja terkecoh dengan judul buku ini, itu wajar. Judul buku ini hanya diambil dari salah satu judul puisi di dalamnya. Setelah kita membaca lebih dalam dan teliti, sesungguhnya tema dan kesadaran utama buku ini tentang ruang-ruang tersebut. Ruang-ruang yang telah hilang dan diberangus oleh banyak faktor; sosial, ekonomi, politik, kemanusian, dan peradaban. Ruang yang kemudian menjadi sekat dan mengikis kesadaran kemanusiaan untuk membuka ruang nurani dan pikiran mereka akan banyak masalah kehidupan.
Tak ada lagi tanah lapang
Anak-anak rindu bermain layang-layang
Lalu kau kibarkan bendera lusuh
Di jantung kota yang rapuh
Angin tak henti mencangkul trotoar
Menghela peradaban mesin-mesin yang hingar
Orang-orang kalah dan gelandangan
Diperdaya gambar-gambar iklan
(penggalan puisi “Kota yang Rapuh, hal 1)
Puisi pertama membuka kesadaran deduktif tentang ruang terbuka yang hilang bagi masyarakat urban. Industri dan kapitalisasi atas nama peradaban yang ditandai dengan mesin-mesin menjadi faktor utama yang tak terelakkan. Gambar-gambar iklan telah menciptakan masyarakat marjinal, konsumtif, dan terpedaya. Orang-orang kalah di sini tentu saja bukan hanya mereka yang papa saja, namun sangat mungkin mereka adalah yang mampu secara ekonomi namun menjadi konsumtif dan terpedaya iklan-iklan yang sering kita tonton. Ini sesungguhnya masalah besar bagi bangsa besar dengan semua lapisan masyarakatnya, namun menjadi pasar empuk kaum atau negara industri dan kapitalis – bisa saja justru dari bangsa sendiri – yang menguasai negeri ini.
Kita bisa menyaksikan fenomena ini di pusat-pusat kota di negeri kita. Dominasi produk dan iklan telah menciptakan kaum kalah. Jantung kota yang kita anggap sebagai pusat peradaban justru telah menjadi rapuh dan tak kuat menahan gempuran kapitalisasi. Ruang-ruang telah menjadi barang yang sangat mahal. Kita bisa memasuki ruang-ruang di tengah kota, namun kita menjadi kalah dan konsumtif di sana, suatu harga yang tak mungkin bisa dijangkau oleh kaum bawah. Mall, pertokoan, kafe, restaurant, tanah lapang yang menjelma stadion yang hanya bisa dinikmati kalangan tertentu – dan tentu saja tak bisa untuk bermain layang-layang – adalah iklan yang mempedayakan.
Ruang, Modernisasi dan Peradaban
Makhluk, baik hidup atau tak hidup membutuhkan ruang. Sejauh mana ruang berfungsi dengan baik atau tidak, ternyata bukan persoalan sederhana yang dipikirkan banyak orang. Modernisasi dan peradaban manusia memberi pengaruh besar pada fungsi ruang tersebut. Pemikiran manusia yang berkembang pesat telah membuat ruang-ruang tersebut begitu fenomenal, fungsional, eksistensial, atau paradoksal yang mampu diidentifikasi dan membuat suatu diferensiasi antara satu kaum atau bangsa dengan bangsa yang lain dalam hal pemikiran, kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan serta tekhnologi.
Modernisasi sering dipandang secara sempit sebagai proses pembangunan fisik dan material suatu desa, kota, atau negara. Tentu saja bukan sekadar itu, karena pada faktanya, pembangunan semacam itu akan mengakibatkan bermacam masalah sosial seperti kesenjangan, penggusuran, pengangguran, atau ketiadaan ruang karena telah berganti fungsi dan peran, dan masih banyak lagi.
Kita nikmati detik-detik jam
Sebagai instrumentalia kehidupan
Tanpa keluhan dan kutukan
Di ruang depan
Tanda-tanda diterjemahkan
Memaknai peradaban zaman
(Bait terakhir puisi Ruang Depan, hal 11)
Bait di atas adalah suatu isyarat bahwa di ruang depan banyak tanda sedang diterjemahkan. Tanda-tanda tersebut adalah bagian dari apa yang kita sebut peradaban. Kebudayaan luar yang datang dan sedang gencar melakukan penetrasi nilai dan gaya hidup dengan segala superioritasnya, kapitalisasi dan industrialisasi produk dan jasa dengan iklan gemerlapnya yang menenggelamkan jati diri kita hingga menjadi orang kalah dan konsumtif, ruang-ruang yang dialihfungsikan dan menciptakan orang-orang marjinal. Kita melihat semua itu sedang terjadi di ruang depan dan pemaknaan kita terhadap laju peradaban tersebut sesungguhnya telah bisa kita ketahui dari isyarat-isyarat sebelumnya.
Fenomena-fenomena yang terjadi di ruang depan terjadi dengan begitu pesat. Pada akhirnya arus modernisasi akan menggerus ruang depan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mungkin tak mampu kita elakkan. Kita mungkin masih bisa menikmati hidup dan waktu kita, detik-detik jam, dan atau romantisme tanpa mengeluh dan mengetuk karena semua tersebut adalah instrumentalia kehidupan. Namun kembali lagi, jika kita melihat apa yang terjadi di ruang depan, kita harus siap terhadap konsekuensinya, suatu harga mahal yang harus kita bayar.
Kamu tidak hanya satu. Jumlahnya lebih
Dari seribu. Subuh dan pagi masih jauh
Orang-orang kecil yang diremehkan
Suaramu menggedor-gedor tembok angkuh
Kota metropolitan. Angin berkesiur ke kali bau bacin
Yang airnya hitam, mengalir lamban lantaran
Tersendat-sendat oleh sampah-sampah peradaban
(penggalan puisi Suara dari Seberang Jalan, hal 47)
Dari ruang depan, kita telah menyaksikan peristiwa dan fenomena yang terjadi. Dari situ juga kita bisa mendengar “Suara dari Seberang Jalan”. Suatu fenomena yang cukup mengerikan sebagai suatu konsekuensi dari peradaban, sampah. Bau bacin kali yang airnya hitam dan lamban mengalir, orang-orang kecil yang diremehkan dalam jumlah ribuan, tembok-tembok angkuh yang kemudian sesungguhnya sedang mengikis nilai dan rasa kemanusiaan kita. Konsekuensi ini sesungguhnya telah membuat implikasi yang jauh lebih mengerikan secara psikologis dan sosiologis, juga ideologis. Teks tak sekadar persoalan interpretasi tapi memang membuka lapisan-lapisan lain yang jauh lebih banyak untuk dieksplorasi.
Orang-orang memasuki ruang tunggu
Yang lain. Kipas angin berputar gemetaran
Kita tiba-tiba merasa akan keasingan
Pikiran kita membimbang, kali kesekian hati meragu
Setiap saat kita terjebak kesibukan kota
Menerawang gelisah pada kaca-kaca
Mata kita saling bertatapan
Tapi tak menemu pelabuhan
(penggalan puisi Ruang Tunggu yang Lain, hal 28)
Modernisasi dan peradaban berdampak tak hanya pada mereka orang-orang yang kalah dan marjinal, tapi berpengaruh juga pada psikologis masyarakat secara umum dan keseluruhan di wilayah-wilayah urban. Kita bisa menyaksikan fenomena tersebut di ruang tunggu. “Ruang Tunggu yang Lain” hanya semacam afirmasi bahwa di ruang tunggu, di tempat yang berbeda menyajikan kondisi psikologis yang sama; keasingan, pikiran yang membimbang, dan hati yang meragu. Potret ini begitu realistis bagi masyarakat urban, kesenjangan yang begitu kentara. Suasana ruang tunggu yang lain tersebut semakin terasa asing dan bimbang dengan ilustrasi kipas angin yang berputar gemetaran. Tentu kita bisa memaknai ini sebagai suatu kondisi di mana ruang tersebut begitu panas hingga pendingin udara tak mampu berfungsi dengan baik. Ini adalah simbol personal yang sangat mungkin ditafsirkan dengan beragam cara.
Ruang tunggu tersebut juga mengilustrasikan kaum urban yang begitu sibuk setiap saat. Ini semakin mengukuhkan bagaimana kaum urban menghadapi hidup yang begitu sarat. Kondisi batin yang gelisah meski sesungguhnya satu sama lain saling bertatapan. Interaksi kaum urban adalah interaksi sosial yang begitu pasif meski setiap saat mereka saling berjumpa di ruang tunggu dalam kesibukan mereka. Repetisi kehidupan yang sungguh begitu monoton dan tentu saja menciptakan kegelisahan. Selalu seperti itu tanpa ada pelabuhan.
Halusinasi dan Kesadaran Eksistensial
Kompleksitas hidup masyarakat urban pada titik tertentu mengusik pikiran kita melakukan halusinasi. Beban batin dan pikiran yang begitu berat memang perlu segera dilepaskan. Persoalan ekonomi, kesenjangan, kebutuhan hiburan yang mahal, ketiadaan ruang, raungan mesin yang bising, keterasingan, adalah hal-hal yang butuh disalurkan agar tak menjadi patologi masyarakat.
Aku selalu merindu kibaran udara
Tanpa polusi. Telah kucatatkan mimpiku
Yang dihanguskan asap knalpot. Tetapi
Sebaris senyum dan tawamu menjelma
Bunga-bunga dan pohon rindang menadahi
Airmataku yang meratapi nasib hutan-hutan
Yang dibakar. Aku ingin bicara kepada daun-daun
(penggalan puisi Halusinasi Ruang Hijau, hal 15)
Sangat tepat jika katakan bahwa bait di atas adalah halusinasi. Kibaran udara tanpa polusi telah mengilustrasikan wajah kota yang sebaliknya. Kita melihat ruang terbuka luas, yaitu lingkungan udara di kota saja telah menjadi suatu persoalan. Ketika banyak ruang telah tergerus dan beralih fungsi, kita masih mendapat masalah lain, yaitu polusi pada ruang terbuka. Asap knalpot yang menghanguskan mimpi hanya salah satu pengaruh dan masalah bagi polusi ruang terbuka. Faktanya kita masih disajikan dengan begitu banyak asap yang muncul dari mesin-mesin pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah kaum urban yang tak lagi memiliki tempat untuk membuang sampah. Kurangnya pepohonan dan taman yang mampu membuat sirkulasi udara berjalan dengan baik menambah masalah bagi kaum urban.
Halusinasi tersebut sungguh hal wajar, sebagai satu hiburan. Jauh dari masyarakat urban sana, di hutan-hutan juga telah terjadi masalah besar, pembakaran. Pada akhirnya kita memang hanya bisa menciptakan halusinasi tentang bunga-bunga dan pohon rindang yang menjelma dari sebaris senyum dan tawa. Saat ruang-ruang tertutup dan terbuka semakin menjadi permasalahan yang tak terselesaikan dan halusinasi juga hanya hiburan semu, maka hal yang paling mungkin adalah kita penciptaan suasana yang penuh kedamaian, senyum dan tawa. Suasana batin yang penuh keterasingan, kegelisahan, kebimbangan, harus kita gerus demi menjaga rasa humanisme kita.
Sebuah jam tak bosan bernyanyi
Membangunkan kita setiap pagi
Sebelum cahaya matahari masuk
Ke kamar kita. Kamar yang kecil –
Namun penuh cita-cita, mimpi dan biografi
(penggalan puisi Ruang Keluarga, hal 43)
Kesadaran eksistensial akhirnya perlu kita bangun. Kita tentu saja tak bisa hidup dengan halusinasi. Pemaknaan terhadap ruang-ruang tersebut akan menjadi lebih penting daripada kita mengutuknya dan menjadikan itu semua masalah-masalah yang makin membuat kita hidup dalam suatu keterasingan, kegelisahan, dan kebimbangan. Rasa kemanusiaan kita sesungguhnya adalah ruang hidup yang berperan besar untuk menghidupkan kehidupan yang lebih luas.
Ruang yang paling mungkin berikutnya adalah “Ruang Keluarga”. Keluarga atau rumah adalah tempat bermula. Kamar yang kecil di dalam rumah kita bisa dimaknai eksistensial, bahwa dari situ mampu dibangun hal-hal besar. Kamar kecil penuh cita-cita, mimpi, dan biografi telah mampu memaknai suatu kehidupan yang lebih berarti. Ya, dari sini setiap kita bisa memulai. Ruang-ruang di luar sana akan menjadi hidup juga saat ruang batin, kamar, dan ruang keluarga memancarkan aura optimisme dengan cita-cita dan mimpi.
Di sebuah jalan lain, pada waktu yang lain
Malam adalah ingatan-ingatan kusam atas
Gugusan musim. Aku menatap lampu-lampu
Ketika bulan, pelan-pelan, menidurkanmu
Malam telah tua dan musim berganti warna
Aku menatap guguran-guguran hujan
Di halaman. Esok pagi, kau hirup segar udara
Dan hari-harimu kembali berbunga-bunga
(penggalan puisi Perjalananan Dua Musim, hal 66)
Puncaknya, setiap kita memang harus memiliki keyakinan, bahwa manusia mampu menjaga dan membangun eksistensinya. Kesadaran, pikiran, dan rasa kemanusiaan yang hidup akan memberi jalan manusia untuk mengatasi semua persoalannya. Sesungguhnya meski memang berat, persoalan kaum urban tak semengerikan yang kita bayangkan. Kita bisa berdamai dengan segala warna kehidupan tersebut sambil tetap berusaha dan yakin bahwa esok pagi kita bisa menghirup udara segar dan hari kita kembali berbunga-bunga. Ini tentu bukan semata suatu halusinasi, namun tak ada seorangpun yang ingin menghancurkan hidupnya sendiri dalam kebinasaan, keterasingan, dan kebimbangan. Masih ada ruang yang hidup, ruang bernama nurani juga ruang pikiran, bahkan ruang itu tak terbatas. Ruang nurani itulah yang akan memaknai ruang-ruang besar lain yang ada, ruang yang kemudian kita sebut ruang eksistensial. Berdirilah di ruang mana saja, saat nurani kita masih hidup, kita akan melihat damai dan kebaikan. Segala yang asing akan menjadi indah dan begitu bermakna.
*Mahan Jamil Hudani adalah nama pena dari Mahrus Prihany lahir di Peninjauan, Lampung Utara, pada 17 April 1977. Meluluskan studi di Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO). Saat ini bergiat di komunitas Sarang Matahari Penggiat Sastra (SMPS). Juga aktif di Komunitas Sastra Indonesia (KSI). Kini juga sebagai kepala sekretariat Lembaga Literasi Indonesia (LLI) yang didirikan sastrawan Ahmadun Yosi Herfanda, serta sebagai Redpel di portal sastra Litera.co.id.