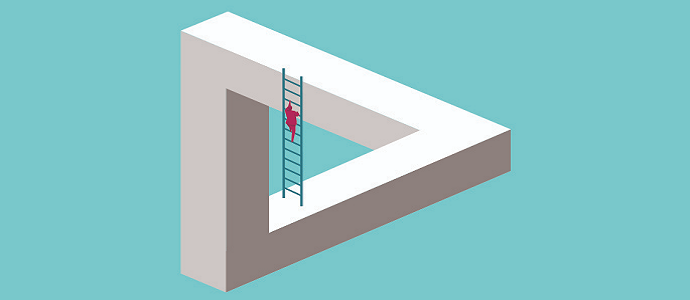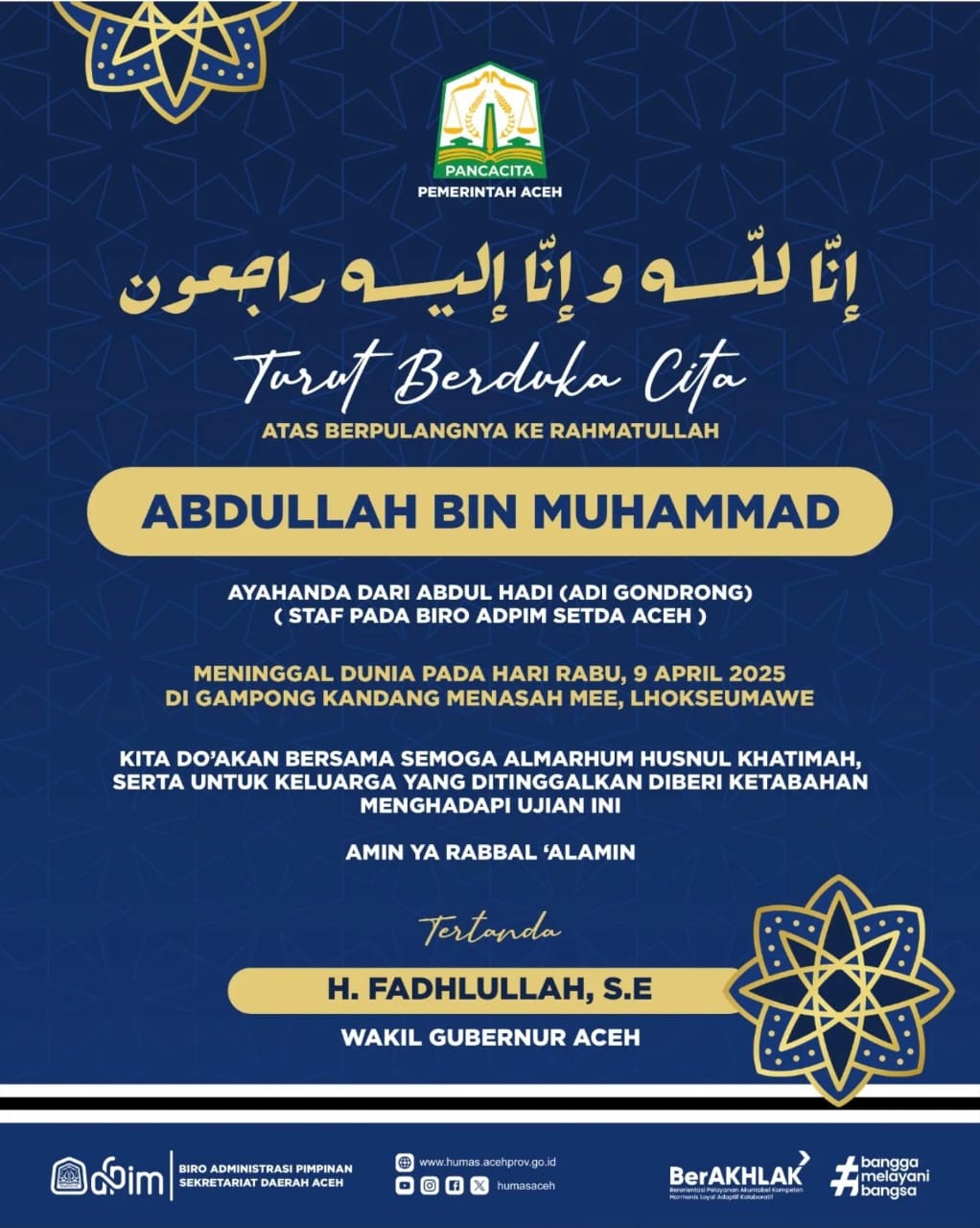(Bermain dengan) Paradoks dan Momentum yang Hilang Serta Totalitas Ekspresif
Oleh Mahan Jamil Hudani*
Paradoks dan Implikasi Puitik
Jika kita membaca puisi-puisi Budhi Setyawan dalam buku ini yang berjumlah 72 puisi, kita seperti disuguhi dengan sebuah paradoks1. Hal pertama adalah pemilihan judul puisi Sajak Sajak Sunyi (S3) yang kemudian tentu saja menghadirkan puisi-puisi dengan nada seragam. Kita tentu bisa memperdebatkan sekarang bahwa kesunyian bukan semata milik sajak dan penyairnya. Puisi tak lagi berada di jalan sunyi, ini juga sebuah kredo yang paradoks sama seperti paradoksnya seorang penyair pasti berada di ruang sunyi. Bagaimanapun faktanya adalah banyak penyair berada di ruang penuh gemuruh. Inspirasi juga bisa lahir di manapun bahkan saat kita sedang makan di resto atau cafe lalu menulis peristiwa itu sebagai puisi. Mungkin paradoks ini bagi pembaca sesungguhnya memang bukan suatu hal yang signifikan dan menarik untuk dibahas tetapi bagaimana kita memasuki dan memahami kesunyian dan kompleksitasnya pada puisi-puisi dalam S3 ini maka melakukan ekplorasi paradoks dalam perspektif sastra2 akan menjadi sangat diperlukan karena ini adalah semacam titik sentralnya.
Memang bisa jadi sunyi dalam buku puisi ini adalah sebuah dialektika. Sunyi adalah ruang atau waktu di mana kontemplasi dan imaji bermain dengan bebasnya padahal bisa jadi puisi itu seperti sebuah kesadaran diri yang terkadang muncul begitu mendadak dan tajam serta menyentak relung terdalam batin kita. Puisi adalah nurani yang terkadang mungusik atas suatu desakan dari sebuah realita tanpa dibatasi dimensi ruang. Ya, puisi bisa saja merupakan benturan antara kognisi dan realitas yang kemudian mengendap. Endapan itu kemudian bisa saja segera meluap atau justru tersimpan lama dan hidup dalam memori yang tetap mengusik hingga suatu ketika harus diledakkan. Ini adalah suatu dialektika yang sesungguhnya makin membuat sebuah puisi mampu berbicara secara jujur tanpa terkesan artifisial dan jauh dari sekadar permainan ilusif. Tapi tentu saja apa dan bagaimana sebuah puisi lahir adalah perkara atau otonomi sang penyair.
Bisa jadi puisi ini mencapai kulminasinya sebagai suatu kesunyian yang benar-benar telah mengendap yang kemudian dieksplorasi. Buku ini sendiri dibagi dalam dua bagian, 42 puisi bagian pertama berbicara ruang sunyi, sementara bagian kedua berisi 30 puisi berbicara waktu sunyi. Nada dan suasana yang terlukis dalam puisi-puisi ini sungguh diselimuti dan memang menekankan kesunyian.
Ini suatu hal yang menarik. Keseragaman dalam mengangkat subyek dalam 72 puisi bukanlah perkara yang mudah terlebih puisi-puisi ini lahir dalam fase yang cukup singkat, hanya dua tahun. 70 puisi ditulis dalam rentang tahun 2014-2016, hanya 2 puisi yang ditulis di tahun 2017. Suatu usaha yang tentu membutuhkan konsentrasi besar.
Kita tak akan mendapatkan puisi-puisi yang berbicara tentang kritik sosial atau hiruk pikuk dunia dan semacamnya, tapi kita akan dibawa pada suatu pendalaman dan pengahayatan batiniah atau spiritual dalam lingkup yang lebih sempit. Jika puisi-puisi spiritual bisa berbicara hal-hal yang bersifat horisontal dan ritual, puisi-puisi dalam S3 ini lebih menitikberatkan perenungan dan dialog batin pada sang pencipta seolah kita sedang berdoa dan berdzikir. Ada satu titik yang dituju, pemahaman akan sang pencipta dengan cara yang sangat kontemplatif dengan mengerahkan dan bertumpu pada totalitas ruang dan waktu yang sunyi. Di situ hanya ada kita dan Tuhan. Dengan kenyataan tersebut, puisi ini hendak betul mengingatkan kita bahwa kita harus benar-benar menyisihkan waktu dan mencari ruang untuk melakukan meditasi dan menghindari segala hal hiruk pikuk dunia. Kita adalah mahluk yang belum mampu mengingat sang pencipta di mana saja dan kapan saja. Ruang dan waktu masih memanjakan kita dengan segala kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa pada sang pencipta.
di sepanjang pantai usia
tuhan
terlupa dalam suka
tersebut dalam duka
(Iman, hal 62)
Pada saat itulah, saat kita berada dalam duka, kita akan mengingat tuhan dengan menyebut namanya. Pada kondisi normal atau bahkan suka, kita lupa akan tuhan bahkan di sepanjang usia. Puisi ini semakin mengingatkan kita bahwa ternyata sunyi adalah ruang dan waktu yang bisa membangkitkan kesadaran akan siapa diri kita. Kita yang harus memberi kesempatan batin kita dengan sengaja untuk bermunajat dalam sunyi. Proses dan praktik ini bukan dicapai dengan semata melakukan ritual yang telah atau biasa kita lakukan sehari-hari, tapi kesadaran diri yang benar-benar dipaksa dan dibawa ke dalam sunyi.
maka kubenamkan sujudku, kutenggelamkan diri pada
lubuk diam paling sunyi. inikah akhir dari pengembaraan
angan menurutkan jalan ingin. sementara angin makin
mendekati sarangnya, sebagai pintu membebaskan doa
dari tindihan harap dan bayang kenikmatan. juga
melepaskan rasa dari dekap rencana rencana. karena
sebagai penempuh takdir sampai batas akhir, tak
semestinya berderap meminta, tetapi cuma bisa tekun
menerima. pada segala yang tiba, kerlip tunaskan daya.
lalu keheningan tajam memintas kalbu, terbit gigil
terbayang tebasan waktu.
(Seperti Sujud Terakhir, hal 71)
Di sinilah kita bisa melihat paradoks bermain. Kita melupakan segala hiruk pikuk dan kenikmatan duniawi. Kita adalah mahluk yang sesungguhnya jarang menyadari bahwa kehidupan kita telah begitu panjang dan penuh dengan lumpur. Segala keramaian dan pesta dunia itu semata sebuah kepalsuan. Yang kita lihat hanya berupa kekosongan. Orang-orang yang lalu lalang dengan membawa segala cerita mereka hanyalah pejalan sementara yang masing-masing seolah sedang menuju pada kesia-siaan. Kita harus bertapa dengan khusuk sejenak walau nanti akan kembali lagi, tapi pada saat itu bisa jadi kita akan melihat sesuatu yang berbeda atau bisa jadi kita berjalan dan tiba-tiba telah berada pada suatu kehidupan yang lebih bermakna.
Fakta tentang kesunyian ini akan mengukuhkan jika sesungguhnya puisi juga memiliki otoritasnya sendiri untuk menyampaikan kepada publik atau pembaca. Kemudian kita akan melihat sejauh mana otoritas itu direspon oleh pembaca. Keragaman respon pembacaan ini secara umum mungkin bukan sebagai justifikasi atau legitimasi terhadap teks tetapi lebih pada suatu upaya pembacaan dan pembelajaran atau reaksi pada sebuah otoritas.
Paradoks oleh Cleanth Brook juga disebut kontradiksi3. Tentu penggunaan paradoks dalam sastra akan menghasilkan makna yang lebih dalam karena kita tak bisa berhenti begitu saja membuat suatu makna kata berhenti dan dipahami sebagai suatu yang diam. Kita bisa memancing pembaca untuk terlibat aktif memahami paradoks tersebut. Misal seperti ini, S3 telah membuat generalisasi yang paradoksal bahwa untuk bisa sampai kepada Tuhan hanya bisa melalui jalan sunyi. Puisi-puisi dalam S3 seolah telah menyampaikan kredo bahwa di luar kesunyiannya manusia hanya mahluk yang lupa pada Tuhan. Tak ada nilai ilahiah kecuali dalam waktu dan ruang sunyi. Tentu S3 sesungguhnya telah menyuguhkan paradoks yang membuat kita berpikir secara tekstual dan kontekstual. Kita bisa saja membuat generalisasi juga bahwa S3 telah menegasikan eksistensi dan hakikat kemanusiaan. Lebih jauh bahkan menggiring pada pengkerdilan kemanusiaan. Nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya sebagai basis dan sumber prilaku yang kemudian teraplikasi pada kehidupan hanya diukur ketika manusia melakukan meditasi pada tuhan di ruang dan waktu sunyinya.
Tentu paradoks yang dibangun S3 ini sesungguhnya tak sesederhana itu. Konsep yang dibangun dalam S3 pada akhirnya akan mempertemukan beberapa titik perbedaan kehidupan manusia dan beragam kompleksitas yang kemudian ditarik pada satu kata kunci yaitu ‘sunyi.’ Sunyi dalam puisi ini bukan semata persoalan diksi tapi juga titik awal dan titik akhir yang memberikan ilustrasi bahwa sesungguhnya untuk memahami jalan kemanusiaan harus terlebih dulu memahami diri sendiri dengan cara melarutkan diri dalam kesunyian. Diksi dalam S3 dengan penekanan kata ‘sunyi’ sesungguhnya adalah konvergensi karena memang pada kenyataannya sunyi bukan berarti diam, tapi sunyi adalah akumulasi gejolak dan proses panjang sebuah perjalanan kemanusiaan.
Sederhananya seperti ini, sunyi dalam S3 ini tidak lahir begitu saja. S3 lahir dan bisa kita baca sebagai suatu pergulatan batin, pikiran, dan benturan yang tentu saja telah melalui filterisasi. Proses filterisasi secara tekstual yang kemudian bisa kita baca dalam S3 ini tentu mengingatkan kita pada satu kaidah bahkan ajaran dasar Roman Jakobson tentang ‘axis of selection into axis of combination’4, puisi adalah seleksi dan kombinasi kata-kata yang memiliki kelas kata dan harus diolah untuk mencapai bahasa yang puitik yang tentu saja berbeda dengan bahasa biasa. Seleksi dan kombinasi kata dengan menggunakan paradoks telah memberi daya dorong yang kuat pada S3 bahkan lebih dari itu, ini bisa menjadi karakteristik tersendiri pada puisi-puisi ini. Sunyi bisa tampil dengan cara dan nada yang beragam tanpa keluar dari koridor utamanya. Coba kita baca bait terakhir puisi ini:
akumulasi renung membuahkan percik embun yang
melumasi ingatan, o, siapa yang memainkan rahasia rasa,
merasuk ke pucuk senyap. pertanyaan memantulkan
gaung, seperti tamparan yang menempelkan pesan:
apakah pemburu mesti mebawa hasil buruan di hutan?
wirid putih melangkah sendiri membawa diri, bergantian
ke ruang silam dekapan jauh dan ke usapan dekat begitu
teduh.
(Antologi Sepi, hal 42)
Tanpa keluar dari koridor dan paradoksnya, puisi itu telah mengalami suatu proses filterisasi yang memberi implikasi puitik. Bait puisi tersebut tidak diam di tempat. Ia melakukan perjalanan dengan begitu teratur sesuai koridornya untuk kemudian sampai pada yang ditujunya. Coba perhatikan baris pertama pada kata ‘akumulasi renung’, kata ini sesungguhnya berangkat dari sebuah kerja pikiran ‘renung’ dengan berangkat dari sebuah kesadaran karena digabung dengan kata ‘akumulasi’. Seorang yang sedang melakukan ‘renung’ sesungguhnya otaknya sedang bekerja, terlebih jika renungnya adalah suatu akumulasi. Ada banyak hal yang sedang dikerjakan oleh pikirannya. Kerja ‘akumulasi renung’ itu tentu bukan hal yang sia-sia. Ia ‘membuahkan percik embun yang melumasi ingatan’, tentu saja segala kerja yang kita lakukan juga mengalami sebuah proses yang terkadang pelan dan prosedural bahwa ingatan kita kemudian dilumasi oleh ‘percik embun’ sebagai buah dari kerja otak sebelumnya. ‘Percik embun’ bisa kita maknai beragam baik sebagai alegori atau bukan. Apa yang terjadi kemudian adalah rasio yang dihadirkan dengan kata ‘renung’ dan ‘ingatan’ bergerak ke arah ‘rasa’, dan kita sadar bahwa ‘rasa’ yang bersifat ‘rahasia’ ada yang mempermainkan. Proses ini masih berjalan karena memang kita sesungguhnya tahu bahwa begitu banyak yang telah mempermainkan ‘rasa’ kita tapi itu terasa ‘rahasia’. Kenyataannya manusia sering mengalami sesuatu hal yang mereka rasakan tanpa mengetahui mengapa itu terjadi. Pada puisi di atas, satu cara yang bisa mengantar adalah saat kita ‘merasuk ke pucuk senyap’. Saat renung/rasio dan rasa terasuk pucuk senyap (sebuah perjalanan menuju waktu dan ruang) kita akan tahu bahwa pertanyaan kita memantulkan gaung ‘seperti tamparan yang menempelkan pesan’. Kita tahu bahwa pesan yang ditempelkan itu lebih kuat tersimpan, maka bait tersebut tidak menggunakan kata ‘menyampaikan pesan’. Komposisi ini menjadi paralel karena kata yang muncul sebelumnya adalah ‘seperti tamparan’. Begitulah seterusnya bait puisi ini bergerak hingga akhirnya kita mencapai pada puncaknya dengan merasakan ‘teduh’.
Mencari dan Menciptakan Momentum yang Hilang
S3 telah menggariskan dunianya dalam kesunyian. Sepi, senyap, kesendirian barangkali adalah momentum yang paling tepat untuk kita sampai atau setidaknya mengenal Tuhan. S3 memang benar menggunakan sunyi sebagai konvergensi dari segala masalah, ragam, dan pernak-pernik kehidupan ini untuk kemudian menuju padaNya.
Jika membaca lebih dalam dan teliti pada puisi-puisi dalam buku ini, kita akan bisa mengetahui jika pernak-pernik yang ada di belakang sunyi adalah segala hal yang profan, sekuler, kesia-siaan, syahwat atau nafsu, dan segala perbuatan buruk lainnya. Itulah kenapa kesunyian akhirnya menjadi momentum untuk mengurangi atau membersihkan semua kotoran itu.
Ya, S3 telah menciptakan momentum puitiknya sendiri. Hanya saja momentum ini dipaksakan bukan sebagai sesuatu yang natural. Ada generalisasi dan penyeragaman bahwa tak ada momentum yang bisa membawa manusia kepada kebaikan dan kebenaran di luar kesunyian. Tapi di sisi lain S3 dengan cukup cerdik telah membuka ruang tafsir tentang kesunyian dengan lebih luas karena S3 menampilkan sunyi bukan sebagai sebuah citraan yang pasif. Sunyi sekalipun benar dikerangkeng dalam ruang dan waktu dan dengan sengaja pula telah menciptakan momentum tersendiri, tetaplah sebuah keaktifan rasa dan rasio yang kemudian mengukuhkan eksistensi diri.
Sunyi adalah ibadah, sunyi adalah tahajud, sunyi adalah dzikir, sunyi adalah wirid, sunyi adalah munajat, sunyi adalah akumulasi renung, sunyi adalah pengembaraan dan pencarian. Sunyi juga gugusan air mata kemanusiaan yang telah mencapai klimaks dari suatu fase kehidupan. Betapa sunyi tampil dan menciptakan begitu banyak momentum puitiknya, artinya sunyi telah ditempatkan dan dimaknai puitik secara momen dalam begitu banyak cara. Sunyi bukan sebagai sebuah kebosanan, lamunan, kesia-siaan, dan rasa keputusasaan.
Banyak sesungguhnya momentum yang hilang, tetapi S3 mampu menciptakan momentumnya sendiri. Momentum puitik sesungguhnya bisa lahir di manapun namun imaginasi dalam S3 yang menegasikan dan menafikan segala hal di luar kesunyian mencoba mencari, menyeret dan merangkum momentum-momentum yang hilang tersebut untuk kemudian diciptakan dengan karakteristiknya sendiri.
kubaiatkan napasku padamu
dan tak kuhiraukan lagi tentang makna sampai
karena hijab hijab antara aku denganmu
terus berlepasan setiap kusebut
kebesaranmu dalam hitungan ganjil
hingga terus kutakzimkan detak nadi
mengalirkan haru ke muara sunyi
(Syahid Rindu, hal 35)
Bait di atas adalah momentum puitik yang diciptakan (untuk tidak mengatakan dipaksakan), mungkin tidak begitu natural, tapi kita melihat ada jejak yang membawa kita bahwa bait terakhir puisi ‘Syahid Rindu’ tersebut menyeret kita pada suatu tempat yaitu ke muara sunyi. Secara struktur baris-baris tersebut adalah anti klimaks. Jika pada puisi-puisi lainnya sunyi adalah titik berangkat untuk sampai kepada tujuan yang bisa kita sebut sebagai ‘zat tuhan’ yang dalam puisi ini bisa dilihat dari kata ‘kebesaran’ dan ‘hitungan ganjil’, tapi pada baris ini sunyi ditulis pada baris terakhir. Terlepas dari itu, kita bisa merasakan suatu proses atau perjalanan yang menyeret momentum-momentum lain terlebih jika kita membaca puisi tersebut secara utuh, begitu juga saat membaca puisi-puisi lainnya.
Totalitas Ekspresif
Pada akhirnya kita melihat totalitas kerja seorang penyair dalam buku S3 ini. Suatu upaya yang serius untuk memaknai sunyi, sunyi yang bekerja untuk mencari dan menemukan titik tujuan. Sunyi bukan semata suasana yang melankolik dan dramatik yang berbicara tentang keduniawian tapi sebuah proses spiritual meski masih parsial karena memang masih bersifat ekspresif.
Sifat ekpresif itu bisa terlihat karena sunyi dalam S3 adalah eskapisme atau pelarian dari hal yang sekuler dan profan. Eksistensi manusia sesungguhnya makin kukuh jika mampu menghadapi segalah kompleksitas kehidupan tanpa harus menghindar dari kenyataan. Kehidupan adalah ragam persoalan baik individual, sosial, kultural, dan dimensi lainnya yang bahkan akan mampu menunjukkan sejatinya manusia. Manusia bagaimanapun juga memiliki intelektualitas dan keluhuran tanpa kehilangan jati dirinya sebagai mahluk sosial.
Spiritual yang dibangun dalam S3 juga masih bersifat parsial, berbicara hanya hubungan vertikal. Diksi sunyi yang dihadirkan dengan ibadah, munajat, dzikir, doa, wirid dan term-term religi lain ditambah dengan nuansa eskapistis tentu membuat S3 masih dalam sebuah perjalanan dan pencariannya.
Totalitas ekspresif S3 bagiamanapun juga telah memiliki jejak-jejak horisontal dalam suatu dimensi sosial meski masih begitu samar. Ia berangkat dari sunyi, ia menuju sunyi, ia menyatu dengan sunyi, dan sunyi adalah antara aku denganmu. Ada satu kredo bahwa saat aku bersama denganmu, maka segala yang tak terlihat, segala yang terlupa, segala yang kotor akan menjadi jejak yang kuat untuk akhirnya menyadari bahwa manusia adalah bukan mahluk kesunyian. Kesunyian lalu akan makin membuat kita begitu bergairah untuk menghadapi segala kompleksitas, keriuhan, dan segala hingar bingar dunia.
Totalitas ekspresif dalam S3 adalah upaya luar biasa untuk memberi makna pada sunyi sebelum akhirnya menjadi totalitas dari sebuah proses spiritual. Mereka yang telah tiba pada totalitas spiritual akan mampu membuat sunyi sebagai sebuah ledakan dahsyat bahkan menciptakan momentum puitik serupa revolusi sosial. Sunyi akan menjelma kekuatan yang mampu mengubah apapun. Sunyi adalah katalisator.
aku belum sepenuhnya mengenalmu, saat lautan
seperti kian meluas, mewadahi ombak yang terus
melafalkan zikir pengagungan. pun senja kian masak,
dengan matahari yang lindap ke ceruk persembunyian.
ada semacam sutra bisikan untuk kembali mencipta
repetisi penelusuran, lebih hening dan dalam, sebelum
yang terang benar benar tenggelam
(Aku Belum Mengenalmu, hal 52)
Totalitas ekspresif S3 masih digambarkan dalam bait puisi di atas. Sesungguhnya memang tak akan ada yang pernah sampai, tapi setidaknya jika kita percaya bahwa manusia adalah mahluk sempurna maka tak ada alasan untuk tidak berbuat secara total. Pencapaian diukur dari seberapa jauh usaha dan kerja yang dilakukan. Nanti kita akan juga melihat upaya yang dilakukan S3 dengan segala pencapaiannya. Kita akan merasa ‘ada semacam sutra bisikan untuk kembali mencipta’. Sutra adalah kelembutan, kehalusan, juga kemewahan. Sutra adalah jejak lain dari simbol dunia yang memberi tafsir betapa kesunyian juga memberi bisikan, inspirasi, dan ilham bagi manusia untuk mencipta, meski sesungguhnya kita belum begitu sepenuhnya mengenalnya. Ada repetisi penelusuran.
S3 dengan totalitas ekspresifnya telah memberi nada optimis meski ia berangkat dari rasa pesimisme dan eskapisme. Tapi bagaimanapun juga, pesimisme yang berangkat menuju vertikal adalah pesimisme yang akhirnya memberi terang, ya kita akan dapatkan itu ‘sebelum yang terang benar benar tenggelam.***
Catatan akhir
1. Wikipedia: “Kata paradoks seringkali digunakan dengan kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi tidak dapat benar, banyak paradoks memiliki sebuah jawaban, meskipun banyak yang tak terpecahkan, atau hanya terpecahkan dengan perdebatan.
2. James H. Pickering dan Jeffrey D. Hoeper dalam bukunya menjelaskan: “Paradox is a statement that is true in some sense, even though at first it appears self-contradictory and absurd.” (Concise Companion to Literature, hal 129-131).
“Like allegory and metaphor, a paradox requires the reader to participate intelectually in the creation of literary meaning. (Ibid)
Sementara Wlilliam Whitla menulis dalam bukunya: “Paradox is a rethorical device that involves a surface contradiction in tension with an element of truth………(The English Handbook: A Guide to Literary Studies, hal 257).
Beberapa teoritisi dan kritikus sastra juga memiliki pandangan tentang paradoks tetapi sesungguhnya hampir seragam.
3. Richard Harland mengutip Cleanth Brook bahwa paradoks hampir sama dengan kontradiksi, semakin besar paradoks dan kontradiksi dalam puisi, akan makin besar pula puisi tersebut. Bagi Brook, paradoks atau kontradiksi akan memancing konflik yang akan memperkuat suatu karya sastra. (Literary Theory from Plato to barthes: An introductory History, hal 189).
Sekadar diketahui Cleanth Brook adalah seorang kritikus yang dikaitkan dalam suatu gerakan sastra yang disebut ‘New Criticm’ yang menekankan pembacaan karya sastra dengan cara tertutup atau close reading. Sesungguhnya saya juga sedang berusaha melakukan pembacaan puisi pada S3 ini dengan pembacaan tertutup, pembacaan yang hanya didasarkan pada teks.
4. Hans Bertens mengutip pandangan Roman Jakobson: “Every time we use language what we say or write is a combination of words selected from a large number of classes and categories. (Literary Theory: The Basics, hal 47-48). Menurut Jakobson, awalnya seleksi yang bekerja menuju kombinasi tersebut hanya pada pemilihan kata atau diksi, selanjutnya ia akan bergerak pada lapangan makna yang banyak digunakan dalam bahasa puisi yang kemudian dikenal sebagai ‘Poetic Function’. Sangat mungkin makna-makna dalam suatu kata menjadi berbeda atau kita yang membuatnya berbeda dalam suatu puisi.
Daftar Pustaka
1. Pickering, James H., Hoeper, Jeffrey D. (Concise Companion to Literature, Macmillan Publishing, 1981).
2. Selden, Raman., Widdowson, Peter., Brooker Peter. (A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, Prentice Hall/Harvester Wheat Sheaf, fourth edition, 1997).
3. Harland, Richard. (Literary Theory from Plato to Barthes: An Introductory History, St. Martin Press, New York, 1999)
4. Zima, Peter V. (The Philosophy of Modern Literary Theory, The Athlone Press, London, 19990.
5. Bertens, Hans. (Literary Theory, The Basics, Roudledge, New York, 2001)
6. Scholes, Robert. (Paradoxy of Modernism, Yale University Press, 2006)
7. Whitla, William. (The English Handbook: A Guide to Literary St
Mahan Jamil Hudani*
Mahan Jamil Hudani adalah nama pena dari Mahrus Prihany lahir di Peninjauan, Lampung Utara, pada 17 April 1977. Meluluskan studi di Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO). Saat ini bergiat di komunitas Sarang Matahari Penggiat Sastra (SMPS). Juga aktif di Komunitas Sastra Indonesia (KSI). Kini juga sebagai kepala sekretariat Lembaga Literasi Indonesia (LLI) yang didirikan sastrawan Ahmadun Yosi Herfanda, serta sebagai Redpel di portal sastra Litera.co.id. Karyanya tersiar di sejumlah media seperti Batam Pos, Riau Pos, Sumut Pos, Lampung Pos, Bangka Pos, Solopos, Pontianak Pos, Tanjungpinang Pos, Medan Pos, SKH Amanah, Bhirawa Surabaya, Haluan Padang, Rakyat Sumbar, Magelang Ekspress, Palembang Ekspress, Padang Ekspress, Radar Mojokerto, Radar Bromo, Analisa Medan, Kabar Priangan, dan Rakyat Sultra. Sejumlah lain termuat dalam beberapa antologi bersama. Karyanya termuat juga di sejumlah media massa. Puisinya terkumpul dalam sejumlah antologi puisi bersama seperti Mengalir di Oase (DKTS, 2010), Seratus Puisi Qurani (Parmusi, 2016), Kemurnian dan Cinta (DKTS, 2016), 1550 mdpl (antologi puisi kopi bersama, 2016), Buitenzorg: Bogor dalam Puisi Penyair Nusantara (DKKKB, 2017), Situ, Kota, dan Paradoks (FLT, 2017), Seutas Tali dan Segelas Anggur (antologi puisi dan cerpen bersama, 2017), PPN X: Puisi untuk Perdamaian Dunia (2017), Jejak Cinta di Bumi Raflesia (Festival Sastra Bengkulu, 2018), Perjumpaan (FSB-BWF, 2019), Jazirah Tiga (FSIGB 2019), dan Banjarbaru Rainy Day Festival (2019). Kumpulan cerpen tunggalnya yang telah terbit adalah Raliatri (2016), dan Seseorang yang Menunggu di Simpang Bunglai (2019).