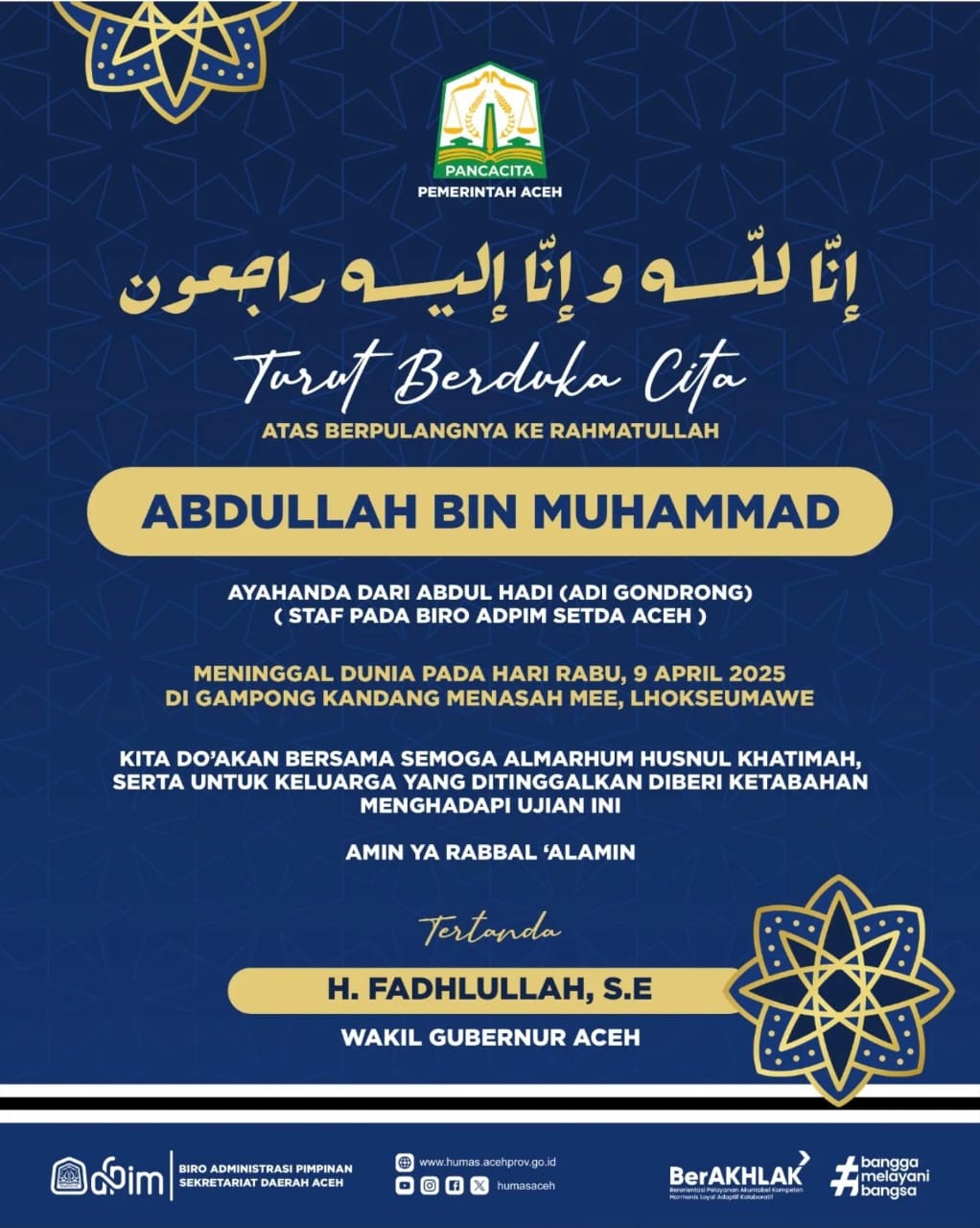Uang Kopi di Negeri Para Raja
Dahulu kala, di sebuah tanah subur yang dijuluki Serambi Mekkah, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Darul Hidayah. Kerajaan itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Faruqi, seorang pemimpin bijak nan saleh, yang ilmunya mendalam dalam agama dan hatinya bersih dari kerak dunia. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dalam kedamaian. Hukum ditegakkan dengan adil, dan setiap proyek pembangunan, dari irigasi sawah hingga pembangunan madrasah, dikerjakan dengan niat ibadah.
Rakyat mencintai Sultan Mahmud karena ia tidak hanya memerintah dari singgasana, tapi juga sering turun langsung ke pasar dan mushala-mushala kecil, mendengar keluh-kesah rakyatnya. Setiap dirham yang dikeluarkan dari perbendaharaan negara selalu disertai musyawarah, dan selalu tercatat rapi dalam lembaran kas negara.
Namun, seperti hukum alam yang tak pernah ingkar, masa berlalu dan Sultan Mahmud pun wafat dalam usia senja. Takhta kemudian diwariskan kepada putranya, Sultan Malik Jamaluddin. Awalnya, rakyat menyambutnya dengan harapan. Tapi harapan itu tak bertahan lama.
Sultan Malik, meski berpenampilan alim, lebih senang berada dalam lingkaran pujian dan pesta. Ia jarang keluar dari istananya, dan lebih percaya pada para penasihat muda yang bergelimang minyak wangi dan baju sutra. Di balik layar, muncullah wajah-wajah baru: para “konsultan”, “penghubung proyek”, dan “penyusun anggaran”—semua istilah baru yang tak dikenal di zaman ayahandanya.
Dari sinilah bermula kisah tentang “uang kopi”.
***
Uang kopi, di negeri para raja, bukanlah uang untuk membeli kopi. Ia adalah istilah halus untuk pelicin, pemulus, dan pelengkap kata “bisa diatur”.
Pada awalnya, hanya satu dua proyek yang melibatkan uang kopi. Tapi seperti air bah, kebiasaan itu cepat meluas. Setiap pembangunan jembatan, perbaikan jalan, bahkan pengadaan kitab untuk pesantren, semua ada “fee tak tertulis”. Jika ingin proposal diterima, maka perlu membawa lebih dari sekadar ide brilian: harus ada amplop, atau lebih baik lagi, kain songket berisi dinar emas.
Ada seorang muda bernama Imran, putra seorang ulama tua di kampung Pedir. Ia menyaksikan perubahan ini dengan mata terbuka dan hati yang resah. Imran baru saja kembali dari menuntut ilmu di negeri Haramain. Ia datang membawa cita-cita untuk membangun madrasah di daerah pedalaman yang kekurangan guru dan fasilitas. Ia membawa proposal, lengkap dengan rencana anggaran dan nama-nama guru yang bersedia mengajar.
Tapi saat ia menghadap ke Dewan Perencana, seorang pejabat berkata sambil tersenyum tipis, “Adinda Imran, ini proposal yang bagus… Tapi kamu tahu sendiri, di sini kopi mahal.”
Imran bingung. “Maksud Tuan, saya harus menyediakan…”
“Sedikit saja. Tak banyak. Cuma untuk pelumas mesin birokrasi. Tanpa itu, sayang sekali, ide cemerlangmu hanya akan mengendap di rak berdebu.”
Imran pulang dengan dada panas. Ia merasa seperti kembali ke masa jahiliyah yang pernah ia baca dalam kitab sejarah. Tapi tak semua bersedia melawan arus. Banyak kawannya sesama pemuda memilih untuk ikut arus, menjadi “penghubung proyek”, yang kerjanya cuma menyodorkan proposal dan mengantarkan uang kopi ke tangan-tangan yang lapar.
***
Suatu hari, Imran bertemu dengan Teungku Karim, sahabat almarhum ayahnya yang juga seorang alim. Mereka berbincang di bawah pohon ketapang di halaman surau kecil.
“Imran, kita tidak bisa menebang pohon kotor itu dengan kapak kayu. Tapi kita bisa menanam pohon yang lebih besar, agar ia kalah teduhnya.”
“Maksud Teungku?”
“Bangunlah madrasahmu tanpa uang mereka. Cari jalan dari rakyat. Kadang, amal kecil dari orang ikhlas lebih kuat dari dana besar yang penuh noda.”
Kata-kata itu membakar semangat Imran. Ia mulai berkeliling kampung, mengetuk pintu demi pintu. Ia menjelaskan niatnya, menunjukkan rencana, mengajak warga untuk bergotong royong. Satu per satu warga mulai membantu. Ada yang menyumbang semen, ada yang menawarkan lahan, ada yang siap menjadi tukang meski tak dibayar.
Berita itu menyebar. Seorang janda kaya, yang pernah menjadi murid ayah Imran, menyumbang emas perhiasannya. Seorang pedagang kain dari Kutaraja mengirimkan tikar dan sajadah. Bahkan seorang mantan pejabat yang pensiun dalam sepi datang dan menawarkan bekas kantor kecil miliknya sebagai ruang kelas pertama.
***
Tiga tahun berlalu. Madrasah itu berdiri megah di tengah ladang hijau. Namanya: Madrasah Al-Faruqi, sebagai penghormatan kepada Sultan Mahmud.
Anak-anak dari berbagai pelosok datang belajar. Mereka diajarkan ilmu, akhlak, dan sejarah negeri mereka yang agung. Mereka diajarkan bahwa pembangunan sejati dimulai dari kejujuran dan niat yang bersih.
Di sisi lain, proyek-proyek istana makin megah namun rapuh. Jalan yang dibangun cepat rusak. Bangunan ambruk sebelum usia. Rakyat mulai bertanya. Suara-suara lirih berubah menjadi gumaman ramai. Di masjid, di warung kopi, di bawah pohon-pohon rindang, orang mulai membandingkan hasil dari uang kopi dan hasil dari tangan rakyat.
Sultan Malik merasa terganggu. Ia memanggil penasihatnya. “Siapa anak muda itu? Kenapa ia bisa membangun tanpa uang kita?”
“Namanya Imran, Tuanku. Putra almarhum Teungku Yahya.”
“Panggil dia.”
Imran datang ke istana. Ia mengenakan gamis putih sederhana. Tanpa cincin, tanpa pengiring.
“Wahai Imran,” kata Sultan, “kenapa kamu tak datang sejak awal dan meminta bantuanku?”
“Ampun, Tuanku. Hamba datang, tapi kopi hamba tak cukup harum.”
Sultan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu.
Imran melanjutkan, “Hamba hanya ingin rakyat belajar bahwa membangun tak harus dengan syarat yang mencederai nurani.”
Diam-diam, Sultan Malik menatap pemuda itu lama. Dalam hatinya, ia tahu: Imran tidak hanya membangun madrasah. Ia sedang membangun kembali kepercayaan rakyat pada kebaikan.
***
Dan sejak hari itu, kata “uang kopi” perlahan mulai memudar di Negeri Para Raja. Tidak sepenuhnya hilang, tapi rakyat tahu kini ada jalan lain: jalan yang dibangun dengan iman, bukan amplop.
Sebab jika kopi hanya menghangatkan perut, maka kejujuran menghangatkan negeri.
Bersambung…