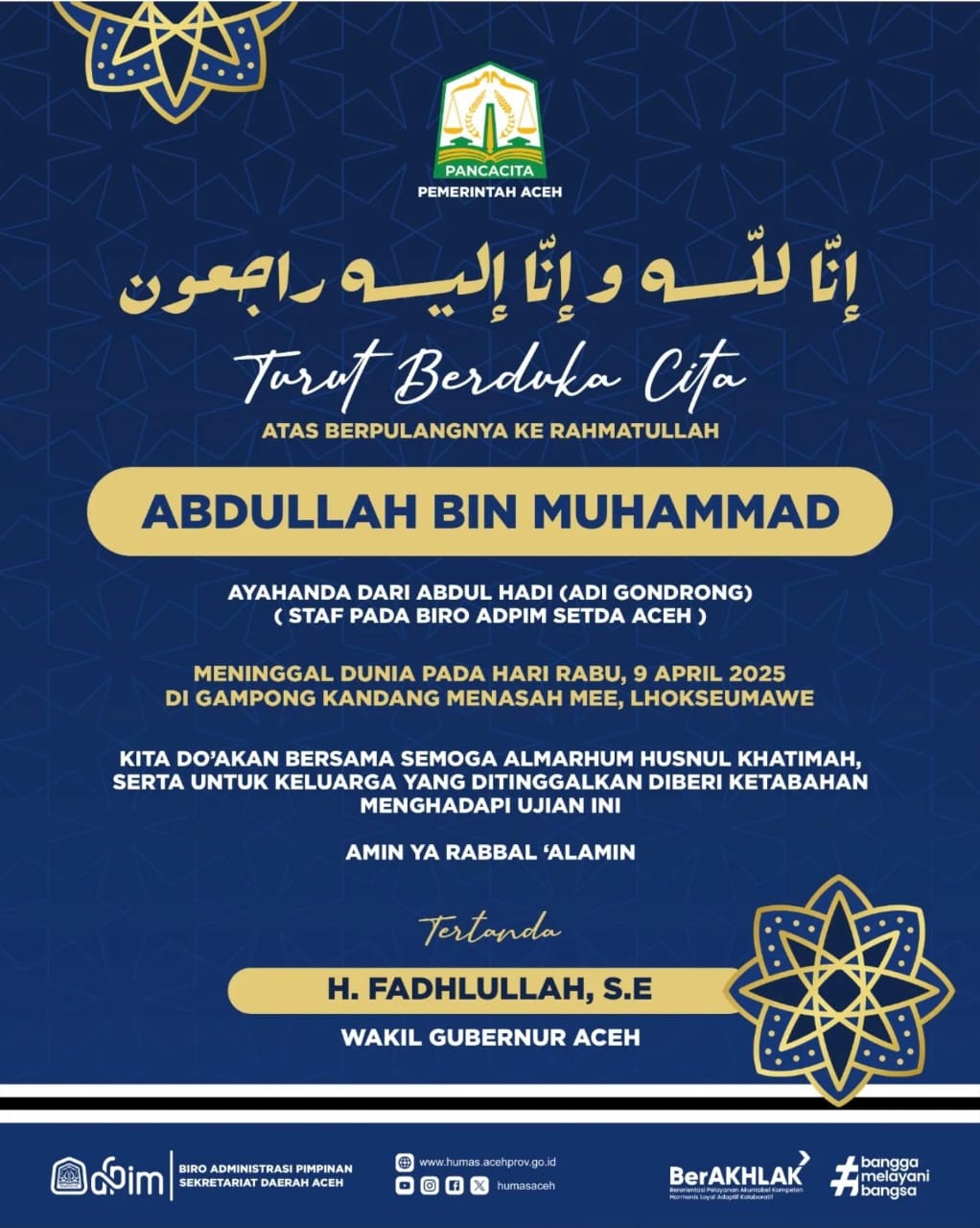Turki mungkin telah merebut kembali kepemimpinan Islam Sunni dari Arab Saudi
Ditulis oleh Omar Ahmed
Masjid Agung Hagia Sofia dibuka untuk ibadah umum Jumat lalu untuk pertama kalinya dalam 86 tahun menyusul putusan pengadilan tinggi bahwa bangunan bersejarah itu, awalnya sebuah gereja, telah diubah menjadi museum secara ilegal oleh pendiri negara sekuler Turki modern. Saya harapkan hasil yang baik sebelum keputusan penting diumumkan secara resmi awal bulan ini dan memutuskan untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu terungkap.
Terakhir kali saya mengunjungi Hagia Sophia sekitar 10 tahun yang lalu ketika itu adalah sebuah museum. Kali ini, sekitar 350.000 orang bergabung dengan saya, sebagian besar di sekitar masjid, sementara sekitar 1.000 salat di dalam. Jemaat termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang disambut dengan tepuk tangan meriah saat dia terlihat memasuki masjid di layar luar ruangan yang besar. Saya berhasil memasuki masjid sendiri beberapa hari kemudian, karena masjid itu terbuka untuk pengunjung, baik Muslim maupun non-Muslim.
Meski pemakaian masker wajah diwajibkan karena pandemi virus corona, jarak sosial pada acara penting Jumat lalu praktis tidak ada; ini tidak mengherankan mengingat banyaknya orang di sana, termasuk banyak orang asing seperti saya. Dapat dikatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang panjang, Masjid Biru Istanbul yang ikonik dibayangi oleh bangunan di sekitarnya, di mana semua masjid era Ottoman dimodelkan.
Pengembalian Hagia Sophia ke masjid, peran yang telah dipenuhi selama hampir lima ratus tahun, adalah perkembangan terbaru saat Erdogan menegaskan kembali status Turki sebagai kekuatan regional. Beberapa percaya itu adalah upaya untuk mendirikan kekaisaran neo-Ottoman, sambil berpaling dari Barat dan warisan Mustafa Kemal Ataturk yang mendirikan Republik Turki sekuler setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1923. Pada 24 Juli tahun itu, Perjanjian Lausanne menghasilkan kekuatan Barat dan sekutu mereka mengakui perbatasan Turki modern. Pembukaan kembali Masjid Agung Hagia Sophia adalah peringatan 97 tahun penandatanganan perjanjian tersebut.
Tidak diragukan lagi, simbolisme yang disengaja juga meresap dalam khutbah Jumat lalu . Kepala otoritas agama tertinggi Turki, Diyanet , Ali Erbas membawa pedang Ottoman saat dia naik ke mimbar alih-alih tongkat kayu yang lebih umum digunakan. Imam Erbas kemudian menjelaskan penggunaan pedang kepada wartawan: “Ini adalah tradisi di masjid yang merupakan simbol penaklukan. Selama 481 tahun tanpa henti, [para imam] pergi dengan pedang [ke mimbar]. Insya Allah, kami akan melanjutkan tradisi ini mulai sekarang. ”
Dalam persiapan untuk khutbah, Alquran dibacakan, seperti salam kepada Nabi Muhammad (saw), keluarga dan sahabatnya, mengingatkan pada nasyid populer dari awal tahun 2000-an oleh Sami Yusuf. Ketika mereka menggema dengan merdu baik di dalam maupun di luar masjid, saya tersadar bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi di Arab Saudi, di mana interpretasi puritan terhadap Islam Sunni, yang sering disebut sebagai Wahhabisme, adalah agama dan praktik negara yang dianggap sebagai “inovasi”.
Saudi berperang melawan Ottoman dan telah bersaing untuk kepemimpinan dunia Islam Sunni sejak pembentukan Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Penafsiran Ottoman tentang Islam berada di ujung lain spektrum agama, dengan tasawuf memainkan peran besar peran dalam masyarakat Ottoman, meskipun pendirian agama konservatif.
Selama beberapa hari ini di Turki saya mendapat kesan bahwa perjuangan 300 tahun untuk kepemimpinan Islam Sunni tampaknya kembali menguntungkan Turki, dengan langkah Hagia Sophia menjadi proyeksi terbaru dari kekuatan lunak Ankara. Seolah-olah khotbah Jumat lalu mengumumkan Turki sebagai pesaing kepemimpinan yang serius, sekeras apa pun Islam Sunni. Sementara perang lima tahun yang menghancurkan Riyadh di Yaman telah menodai citranya di kalangan Muslim, intervensi militer Ankara di Suriah dan Libya tampaknya mendapat dukungan dari banyak kalangan Muslim non-Turki.
Tentu saja retorika neo-Utsmaniyah dilebih-lebihkan dan merupakan bentuk propaganda melawan Turki. Arab News milik Saudi menerbitkan serangkaian artikel baru-baru ini tentang Turki yang ” mengulangi ” kejahatan Ottoman terhadap orang-orang Arab, memperdebatkan klaim sejarah pra-Ottoman dan menuduh Turki mencoba mendapatkan dukungan dari Muslim dari berbagai negara saat berusaha memulihkan kekuatannya dan wewenang.
Ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang terlihat pertama kali. Sebuah majalah berita pro-pemerintah di Turki, Gercek Hayat, membagi opini setelah langkah Hagia Sophia dengan sampul depan yang kontroversial yang menggambarkan bendera Ottoman merah dan menyarankan bahwa sudah waktunya untuk kembalinya kekhalifahan.
Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Washington Post tahun lalu, mayoritas warga Turki yang menanggapi mendukung penghapusan Kekaisaran Ottoman dan menentang pembentukannya kembali.
Namun, gagasan pan-Islamis tentang kebangkitan kekhalifahan melampaui batas, dan memang benar untuk mengatakan bahwa beberapa pendukung terbesar untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Utsmaniyah sama sekali bukan orang Turki, tetapi tinggal di beberapa bagian Asia dengan beberapa yang terbesar. Populasi Muslim. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena beberapa seruan paling awal untuk mempertahankan kekhalifahan datang dari anak benua India, dengan munculnya gerakan Khilafat (1919-1924).
Kritikus kredensial Turki untuk kepemimpinan dunia Islam Sunni mungkin bergantung pada argumen politik dan agama, seperti keanggotaan Turki di NATO dan hubungan diplomatik dan perdagangannya dengan Israel, terlepas dari retorika anti-Zionisnya. Ada juga pendapat umum bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy Mekah , dan bahwa Ottoman bukanlah khalifah yang sah karena mereka bahkan bukan orang Arab apalagi Quraisy. Bisa dibilang kekhalifahan terakhir adalah Abbasiyah yang berakhir pada 1258 M, dengan penyerangan Mongol di Baghdad, saat itu mereka hanya boneka tanpa kekuatan nyata.
Keberadaan Kerajaan Safawi Iran, yang pada waktu yang berbeda-beda bentrok dan hidup berdampingan dengan Utsmaniyah, juga menggambarkan fakta bahwa otoritas politik Utsmaniyah tidak menjangkau semua umat Islam. Iran saat ini memiliki ambisi regionalnya sendiri dan memandang dirinya sebagai pemimpin dunia Syiah, yang, seperti Islam Sunni, tidak monolitik.
Saya diingatkan tentang perbedaan ini selama saya tinggal di Istanbul ketika saya mengunjungi lingkungan Syiah dengan komunitas Azeri yang besar dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat tentang Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Mereka tidak terlalu terkesan dan malah menyebut situs religi di Karbala dan Najaf sebagai tempat yang lebih layak untuk dikunjungi.
Kembali ke pertanyaan tentang kepemimpinan dunia Sunni, jelas bahwa penggunaan kekuatan lunak dan keras oleh Turki telah membantu memposisikan kembali dirinya dalam peran sebelumnya, meskipun dengan cara yang tidak persis sama. Ironisnya, saat Turki membangun kembali hubungan dengan masa lalu Ottoman, Arab Saudi telah menghapus sebagian besar warisannya, termasuk dari era Ottoman, dan semakin sulit untuk membenarkan perannya sendiri untuk menjadi pemimpin yang meyakinkan dari populasi mayoritas Sunni di dunia dalam masalah agama dan politik.
Tulisan diterjemahkan dari www.middleeastmonitor.com. Omar memiliki gelar MSc Keamanan Internasional dan Tata Kelola Global dari Birkbeck, Universitas London. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh Timur Tengah, termasuk belajar bahasa Arab di Mesir sebagai bagian dari gelar sarjananya. Minatnya meliputi politik, sejarah, dan agama di wilayah MENA.