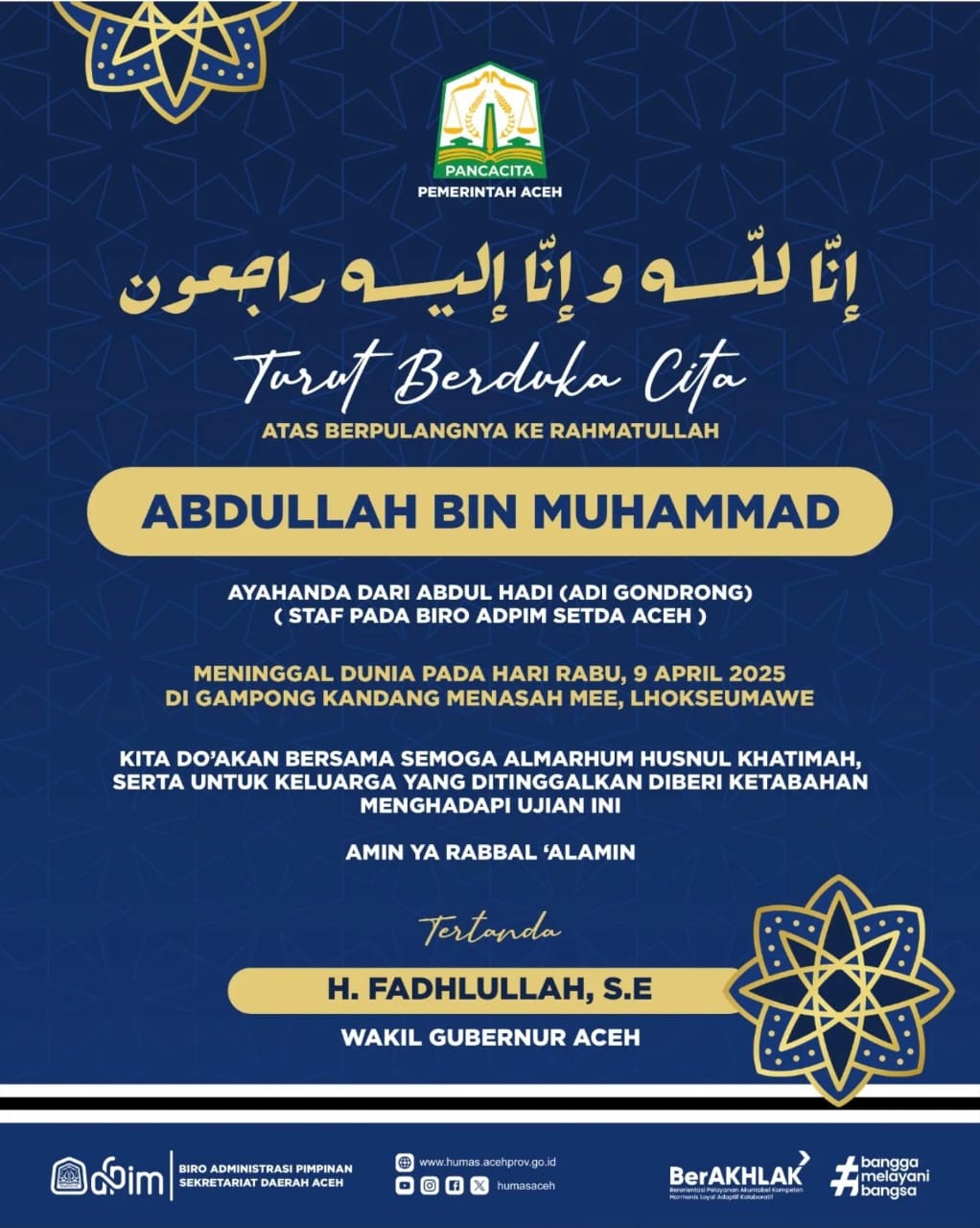Transaksi, Suasana, dan Politik di Balik Meja Dagang
Di sebuah kios kecil di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta, seorang ibu penjual tempe menggeleng pelan ketika ditanya soal harga. “Naik, Mas. Dari kemarin. Tapi ini bukan karena dolar. Ini suasana,” ujarnya sambil merapikan dagangannya.
Kata “suasana” dalam perdagangan sering terasa abstrak. Tapi justru di situlah kekuatannya. Ia merembes ke dalam benak konsumen dan pedagang, kadang tanpa sadar. Dalam ilmu ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Namun di lapangan, harga sering kali ditentukan oleh suasana: suasana hati, suasana pasar, dan, tak jarang, suasana politik.
Menjelang pemilihan umum, suasana semacam itu jadi makin nyata. Pedagang-pedagang di Tanah Abang, misalnya, biasanya lebih berhati-hati dalam menstok barang saat suhu politik memanas. “Jangan sampai salah beli. Kalau terjadi gejolak, barang nggak laku, bisa rugi besar,” kata Arifin, pemilik toko garmen.
Gejolak politik mengganggu prediktabilitas pasar. Pembeli menahan belanja, khawatir terjadi lonjakan harga atau kekacauan distribusi. Penjual juga mengencangkan ikat pinggang. Bahkan pelaku usaha besar seperti pengembang properti atau distributor elektronik menahan ekspansi, menunggu arah angin.
“Situasi politik menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah musuh utama investasi,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam masa kampanye, janji-janji populis bisa mendongkrak daya beli sementara. Tapi begitu selesai, pasar sering dihadapkan pada realitas fiskal yang berbeda. Inilah kenapa suasana politik tak hanya dirasakan di gedung DPR, tapi juga di pasar-pasar kecil dan toko daring.
Lebih jauh, suasana politik juga mempengaruhi trust —modal sosial penting dalam jual-beli. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah atau sistem hukum, maka transaksi menjadi lebih mahal. Orang menuntut uang muka lebih besar, memperketat kontrak, atau beralih ke transaksi tunai.
Sebaliknya, dalam suasana politik yang stabil dan transparan, ekonomi tumbuh bukan semata karena angka-angka makro, tapi karena rasa aman dalam bertransaksi.
Dalam konteks UMKM, suasana ini bahkan lebih menentukan. Bagi pelaku usaha kecil yang tak punya banyak cadangan kas atau asuransi, satu rumor politik bisa memicu penarikan tabungan, penundaan pembelian, hingga pembatalan pesanan. Mereka berjualan bukan hanya berdasarkan harga bahan baku atau margin laba, tapi berdasarkan “rasa” pasar.
Ini bisa kita lihat dalam momen-momen menjelang Pilpres, ketika narasi-narasi besar—soal ekonomi kerakyatan, subsidi, hingga nasionalisme dagang—berkeliaran di media sosial. Sebagian pelaku usaha terbawa euforia, sebagian lain menunggu dan menakar. Di ruang-ruang digital, suasana jual-beli dipengaruhi oleh isu politik yang kadang samar-samar.
Marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, yang tampak netral dan otomatis, sejatinya juga memproduksi suasana politik tertentu. Melalui algoritma promosi, dukungan terhadap seller lokal, atau kampanye nasionalisme konsumen, mereka juga membentuk mood kolektif yang mempengaruhi arah transaksi.
Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang mengatur suasana itu? Jika suasana adalah arena tak kasat mata tempat ekonomi dan politik bersilangan, maka kendali atas suasana menjadi kekuasaan tersendiri.
Suasana bukan cuma soal pencahayaan toko atau kata-kata manis di etalase. Ia bisa dimanipulasi oleh iklan politik, dikondisikan lewat pemberitaan, atau direkayasa lewat strategi komunikasi pemerintah.
Dalam teori ekonomi politik, pasar tak pernah netral. Ia selalu berdiri di antara kekuatan-kekuatan ideologis, institusional, dan psikologis. Dan dalam praktik sehari-hari, kekuatan itu menjelma menjadi “suasana”—kata yang tak tercantum dalam laporan laba rugi, tapi punya daya yang besar.
Kembali ke pasar Sleman, si ibu penjual tempe tersenyum sambil menyodorkan kembalian. Ia tak pernah baca jurnal ekonomi, apalagi pidato menteri. Tapi ia tahu, ketika suasana politik memburuk, dagangannya bisa tak laku. Dan ketika suasana membaik, pasar kembali ramai.
Transaksi, pada akhirnya, bukan sekadar urusan uang. Ia adalah refleksi dari suasana yang dibentuk oleh banyak hal—ekonomi, budaya, dan, ya, politik.
Oleh: Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta