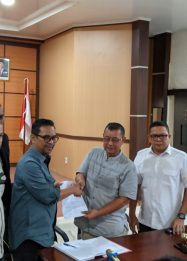Stempel Tak Bahagia setelah ‘Tamparan’ Miskin
Penulis: Darmansyah
GEREGET itu datang lagi menampar wajah Aceh. Masih dari badan pusat statistik. Be-pe-es.
Badan yang sama, ketika mentaklimatkan tentang Aceh miskin. Kini tamparan itu datang lagi. Lebih telak. Di penanggaalan awal, pekan pertama, bulan Januari, di pergantian tahun
Tamparan itu sebuah rilis. Bertajuk indek kebahagiaan. Surveinya dihimpun sepanjang tahun lalu.
Lantas?
Dari data indek kebahagiaan itu Aceh terjengkang lagi. Peringkatnya bereda di posisi 26 dari 34 provinsi yang ada.
Angkanya, setelah diakumulasi dengan berbagai cabang perhitungan mentok di 71,24. Masih di bawah indek paling corot. Hanya satu tingkat di atas Jakarta.
Angka yang dirilis itupun turun dibanding empat tahun silam. Angka indek tahun 2017.
Untuk menghiburkan diri saya berdamai dengan hati untuk memberi jawaban yang menghibur. “Nggak turun amat.”
Angka bulatannya tetap tujuh puluh satu. Tapi angka per-nya turun sebesar 72.
Namun begitu, yang celakanya, dari indek kebahagiaan Aceh hasil rilis be-pe-es itu, sepertinya stagnan. Padahal survei ini sudah berlangsung tiga kali, sejak tahun lalu.
Indek ini kalau mau dirinci lagi masih berada di bawah indek kebahagiaan secara nasional.
Menurut be-pe-es sendiri kesepakatan indek kebahagiaan negara ini saat ini rata-rata berada di angka 71,49.
Saya tak tahu, apakah rilis be-pe-es kali ini ada komplain pejabat di Aceh untuk menggugat validitasnya.
“Mungkin saja ada,” kata teman saya, seorang guru besar sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Guru besar hebat dengan parodi manajemen di Tri Sakti.
Ia tidak mengatakan “ada” secara utuh. Masih diefumiskan dengan dua kata, ”mungkin saja.” Sebenarnya saya tahu isi kepalanya ingin mengatakan “ada.” Namun begitu, ketika kata itu menjalar hingga ke mulutnya, sang guru besar memutar bandul untuk mengucapkan ”mungkin saja.”
Ya, sudahlah. Itu nggak terlalu penting.
Dan, kalau pun ada bantahan dari penujum di Aceh, be-pe-es, seperti yang saya pantau, tak akan bergeming. Artinya, tak mau berdamai telaah yang metodenya berstandar indeks global.
Bahkan, kepala be-pe-es, Margo Yuwono yang mengatakan, tingkat kebahagiaan penduduk yang mereka survei tahun lalu itu diukur secara serentak di seluruh kabupaten dan kota
Pun yang disurvei untuk kemudian dianalisis adalah rumah tangga yang dipilih secara acak atau random.
Metode surveinya juga sudah sangat maju, sampling two stage one phase sampling. Total sampel rumah tangga yang diperlukan untuk keperluan estimasi tingkat kebahagiaan hingga level provinsi sebesar 75.000 rumah tangga
“Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara oleh petugas dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan alat bantu,” kata Margo.
Pertanyaan baru pun muncul. Begitu tidak bahagianya kah orang Aceh?
Jawabannya, entahlah…
Entahlah… usai ditampar oleh rilis negeri paling miskin dari badan yang sama kini Aceh distempel lagi dengan provinsi tidak bahagia.
Sakitnya sebagai negeri paling miskin di Sumatra, jangan dulu bicara untuk ukuran Nusantara, teramat menyakitkan ketika saya mendatangi sebuah diskusi kecil dengan dua orang doktor ekonomi dan seorang profesor anak Aceh “meugampong” di kampus Tri Sakti.
Diskusi kami di pertengahan pekan ini bukan membentangkan karpet reaktif terhadap nasib Aceh yang miskin dan tak bahagia itu. Diskusi kami pro-aktif. Jauh dari provokatif.
“Kita hanya duek pakat,” kata sang profesor ringkas untuk pengantar. Sang prof kepada saya minta untuk tak menuliskan namanya kalau pembicaraan berpindah ke sebuah media.
Saya menjawab dengan guyon. “Nggaklah. Itu bisa melanggar kode etik. Bisa-bisa jadi delik.”
Dalam duek pakat itu banyak keluar kalimat yang saya sendiri tak tahu apa terjemahannya. Maklum saja. Saya kan bukan intelektual. Hanya berbasis strata satu. Itu pun bukan ekonom. Hukum, dengan latar jurnalistik.
Dalam perbincangan itu terselip juga canda kaki lima. Canda dengan kalimat, Udah miskin tambah tak bahagia. Dan masih bisa ditambah dengan tidak aman, tidak ….. dan entah apalagi.
Saya tak mampu menuliskannya. Dan Andalah yang paling tahu dan bisa mengukurnya lewat “meunyo hana beu ….. yang penting “bek nanggroe tapeugala”
Selain duek pakat khas aneuk nanggroe, kami juga sempat membahas pernyataan dari rektor unsyiah… ee..ee USK. Saya kok selalu salah sebut akronim untuk kampus tekad bulat itu. Maklumlah, sejak ia ditabalkan hingga saya menjadi bagiannya hanya unsyiah yang selalu saya komat-kamitkan.
Tentu muncul pertanyaan. Apa yang dibahas tentang pernyataan sang rektor, Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng, IPU Asean. Eng itu?
Sebenarnya kami sumir saja membawa pernyataan sang rektor ke topik diskusi. “Kok mendadak Pak Rektor bicara lantang tentang kondisi Aceh ya?” ujar teman berbincang yang starata tiganya dari university kebangsaan itu.
Saya hanya mendehem dan nyahut seadanya dalam kalimat canda, ”baguslah kalau mendadaknya macam injakan rem.”
Sang rektor, yang saya nggak tahu berapa besar share-nya dalam men-”develop” pembangunan Aceh memang pantas cemas dengan predikat miskinnya Aceh.
Ia memang pantas untuk bicara setelah kampus tekad bulatnya berhasil meraih posisi sebagai perguruan tinggi terbaik kedua di Sumatera atau ke-26 se-Indonesia. Kampus yang mengalahkan USU di Medan.
Dalam hati saya mungkin karena faktor ini yang membuat nyalinya kepincut. Kalau kepincutnya karena popularitas ini yah payah. Dan kalau itu yang menjadi penyebabnya saya jadi ketawa.
Ketawa karena kesejarahan. Bukankah tiga rektor terdahulu bisa jadi……karena kapasitas kerektorannya. Anda tahulah kemana arah yang saya tuju. Anda tahulah siapa Prof Madjid Ibrahim, Prof. Ibrahim Hasan, dan Prof Syamsuddin Mahmud.
Udahlah.
Kembali saja ke materi yang menjadi otokritik Prof Samsul tentang Aceh miskin. Aceh yang mengendapkan dana sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan. Silpa. Silpa yang menjadikan Presiden Jokowi marah. Mendagri Tito Karnavian marah.
Dan Prof Samsul juga marah. Dan marahnya Samsul lebih spesifik. Langsung tunjuk hidung. Dan yang ditunjuk itu adalah dr. Taqwalah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). TAPA yang bukan Tuan Tapa orang keramat di negeri saya. Tapaktuan.
Samsul mengaku heran dengan kinerja aparatur Pemerintah Aceh, khususnya sekretaris daerah Taqwallah yang “Tapa” itu. Tapi tidak keramat
“Coba lihat, dari tahun ke tahun, dana Silpa terus bertambah. Ini membuktikan ada yang tidak beres dari kinerja dan tata kelola pemerintahan, khususnya keuangan,” kritik Samsul
Kritiknya masih berlanjut tentang pembangunan Aceh yang sangat tergantung pada transfer dana dari pusat. Dana alokasi umum maupun dana otonomi khusus
“Mana ada industri skala menengah dan besar yang tumbuh dan berjalan di Aceh. Akibatnya, berpengaruh pada pendapatan asli daerah.”
Sebagai pemegang tongkat keintelektualan sang rektor menyebut kemiskinan dan pengangguran masih menjadi momok yang sangat memalukan untuk Aceh.
Lebih tragis lagi, Aceh tak hanya mengalami darurat kemiskinan tetapi juga darurat pengangguran, darurat stanting, darurat narkoba, darurat bencana, darurat judi online, darurat korupsi serta darurat kekerasan seksual.
Ironisnya, dana dalam jumlah besar itu pun tak mampu dikelola dengan baik atau menjadi stimulus serta lokomotif bagi tumbuhnya perekonomian rakyat.
Padahal, berbagai dana dari pusat tersebut, harusnya dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta perekonomian rakyat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukan dikembalikan ke Pusat
Ia menyebut case ini sebagai bencana. Birokrasi tak mampu bekerja dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya.
Sebagai intelektual rupanya Samsul pandai juga menyelip canda. “Yang terjadi di Aceh ibarat orang menyapu. Setelah bersih di depan, lalu kotor kembali di bagian belakang.”
Begitulah terus berulang-ulang sejak lima tahun terakhir. Lalu, jika ada yang kurang beres, lakukan gonta-ganti pejabat. Ini yang saya sebut manajemen menyapu.
Kondisi ini memang kontras dengan apa yang digaungkan selama ini. Rapat-rapat sampai larut malam, tetapi hasilnya Silpa sangat besar.
Terlepas dari kebenaran otokritik itu, Samsul mungkin alpa membentang kemana uang anggaran yang hitungannya bisa membeli gajah. Bukan gajah mati. Tapi gajah pembangunan.
Otokritik itu hanya bisa kami dehemkan dari kawasan Grogol itu. Dehem senyum. Dehem pertanyaan ada maksud apa. []