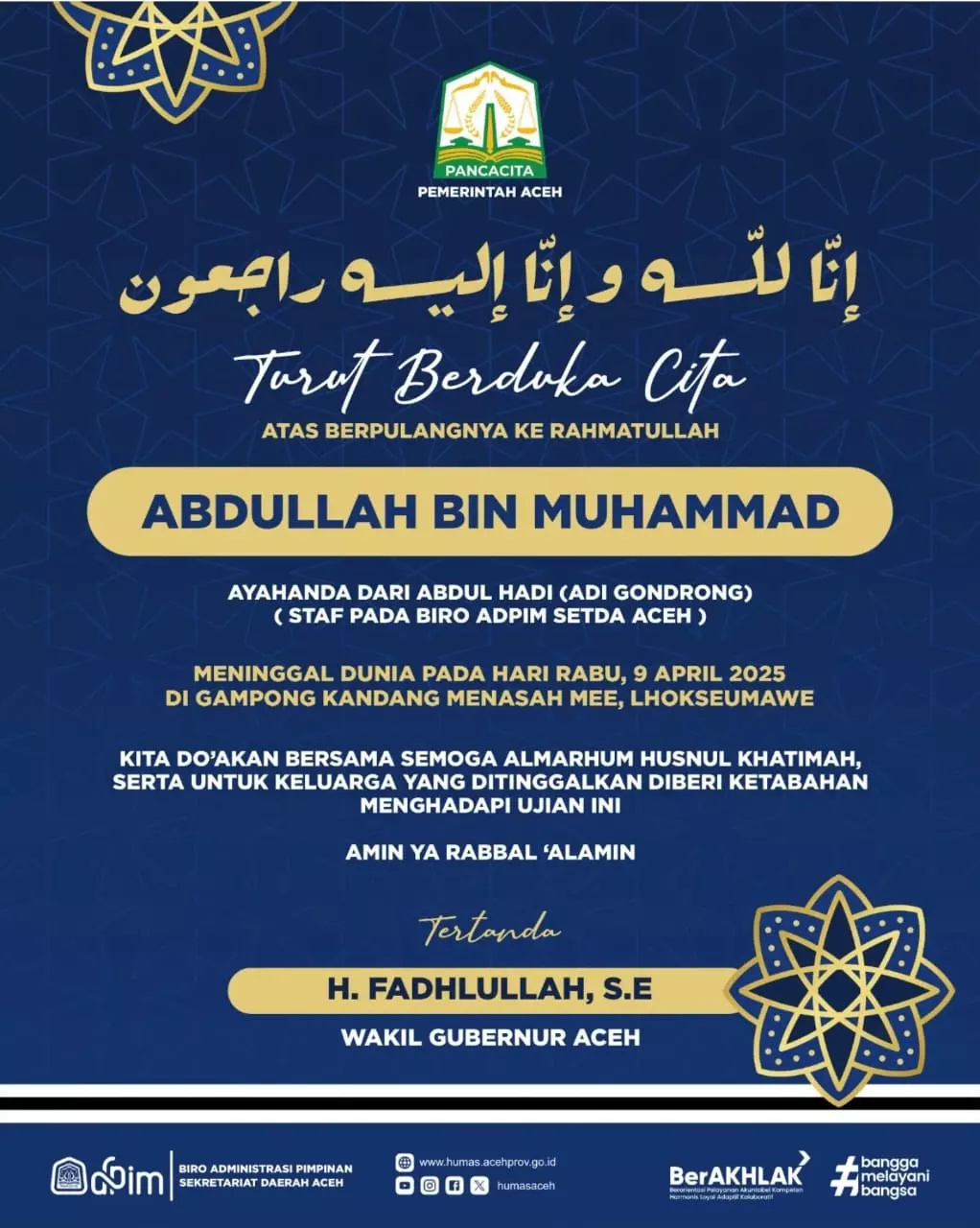Ruang Publik di Banda Aceh, Sudahkan Responsif, Demokratis, dan Bermakna?
Oleh: RM Teguh Prawira Atmaja, S.Pd, M.Si *)
DALAM hal pemenuhan hak-hak publik, tentu banyak yang harus kita pertanyakan. Pertanyaan paling mendasar adalah sudahkah ruang publik responsif, demokratis, dan bermakna?
Studi kasus untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat saja fakta-fakta di Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang publik bisa berupa Ruang Terbuka Hijau Publik atau Ruang Terbuka Non Hijau Publik. Karena rujukannya adalah undang-undang, maka negara (pemerintah) harus bisa menjamin ketersediaan lahan dan peruntukannya.
Kembali ditegaskan bahwa ruang publik harus memenuhi tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna.
Responsif diartikan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis bermakna dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Sedangkan bermakna, memiliki arti harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.
Istilah ruang publik (public space) pernah dilontarkan Lynch dengan menyebutkan bahwa ruang publik adalah nodes dan landmark yang menjadi alat navigasi di dalam kota (Lynch, 1960).
Ruang publik dapat berupa jalan (termasuk pedestrian), tanah perkerasan (pavement), public squares, dan taman (park).
Hal ini berarti ruang terbuka hijau (open space) publik seperti jalan dan taman serta ruang terbuka non-hijau publik seperti tanah perkerasan (plaza) dan public squares dapat difungsikan sebagai ruang publik.
Sejauh pengamatan penulis, Pemko Banda Aceh terkesan abai dengan pemanfaatan ruang publik, misalnya ruang terbuka, sentra kuliner. Setelah dibangun kemudian terbengkalai. Entah apa penyebabnya, entah kurang niat atau kurang rencana.
Padahal kalau niat, tempat-tempat wisata yang sudah ada bisa sangat menarik. Tidak perlu sibuk dengan proyek baru yang terkesan wah, kemudian terbengkalai lagi.
Contoh kasus yang di tepi kali Peunayong, sentra kuliner yang baru setahun dibangun, lihat saja kondisinya sekarang, sangat memprihatinkan. Setelah bertanya ke beberapa sumber, ada yang mengatakan sewa terlalu tinggi sehingga pedagang juga keberatan. Dampaknya, ya terbengkalai.
Sekarang malah mau dibangun lagi yang di Penayong (bekas pasar). Itu berarti pembangunan sentra kuliner itu tidak menarik untuk pedagang, bisa karena harga sewa, bisa juga karena lokasinya nggak pas menurut mereka. Seharusnya, setelah proses pembangunan harus dikawal pemanfaatannya, termasuk, tentu saja tidak terlalu mengedepankan sisi bisnis.
Contoh lain, Taman Sari juga sepi, padahal lokasi tersebut sudah direnovasi pada 2019–membangun pendestrian jalan dan pentas seni yang menghabiskan miliaran rupiah. Yang terlihat kemudian lebih ‘rimbun’ beton ketimbang pepohonan. []
*) Penulis Adalah Akademisi dan Aktivis Pengurangan Risiko Bencana