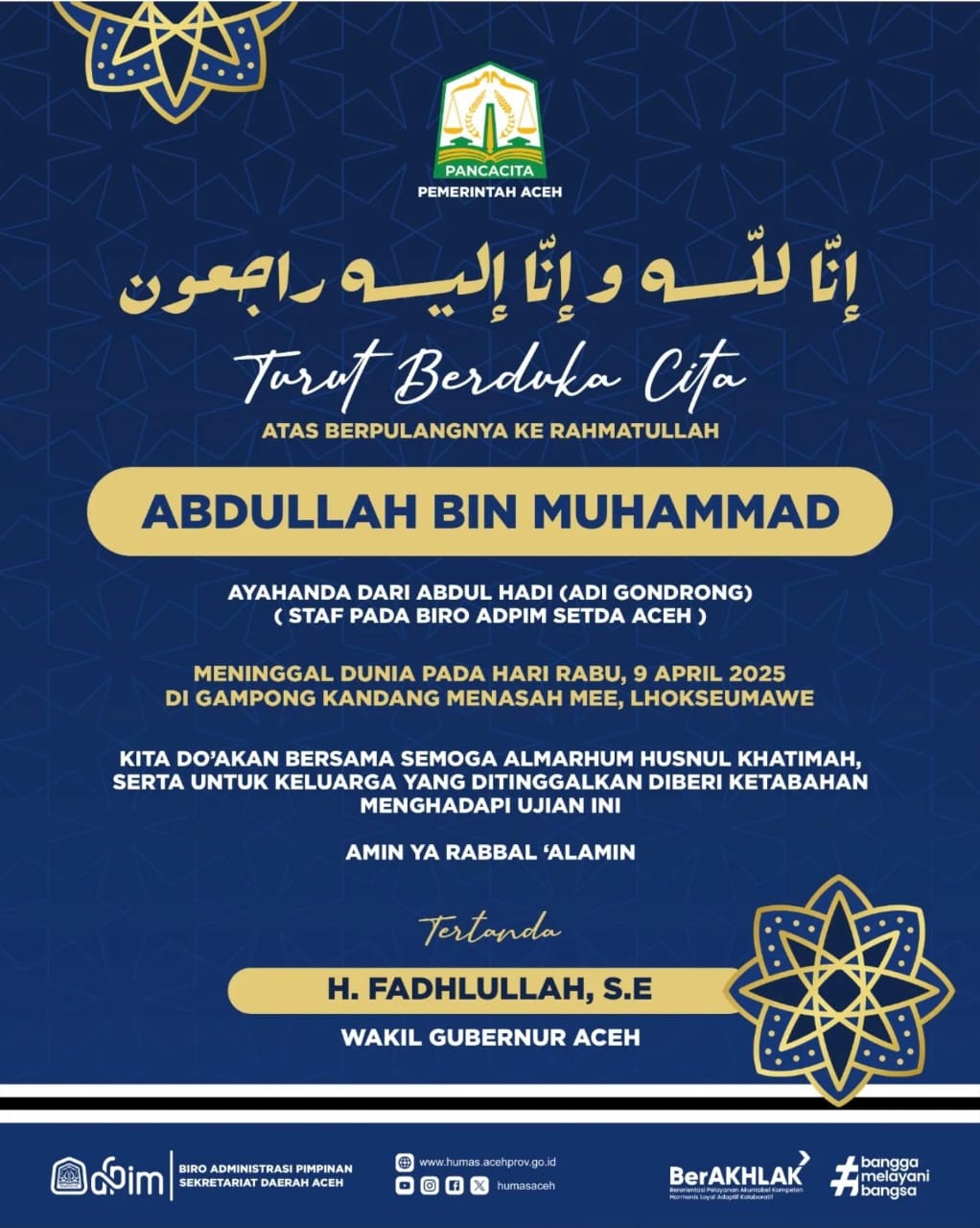Politik Meja Makan: Ketika Kuasa Diwariskan, Rakyat Cuma Menonton
Di Banda Aceh, politik kerap kali menyerupai sebuah kenduri. Siapa yang punya kuasa, dialah yang membagi piring. Yang tak punya kuasa? Cukup menepuk tangan di pinggir halaman, atau kalau beruntung, mendapat tulang ikan di akhir acara. Bedanya, jika kenduri biasa selesai makan bisa pulang, dalam politik Aceh, rakyat diminta terus menonton orang yang itu-itu saja duduk di kursi empuk. Bahkan, kendurinya bisa berlangsung bertahun-tahun, dengan kursi yang diwariskan dari kakek, anak, cucu, hingga menantu. Rakyat? Tetap menjadi penonton.
Yang lebih menyakitkan, di tengah riuh politik meja makan, Banda Aceh justru dihantui kabar duka yang berulang. Beberapa waktu terakhir, ada saja berita tentang anak muda yang ditemukan meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Ada yang di kamar kos, ada yang di rumah kontrakan. Ini bukan semata soal moral, melainkan soal sistem sosial yang gagal menyediakan ruang aman untuk berbagi cerita. Kita lebih suka menasihati daripada mendengarkan. Tentang betapa anak muda, khususnya perempuan, sering memikul beban ekspektasi tanpa pernah ditanya: “Apakah kamu baik-baik saja?”
Ini bukan hanya soal lemahnya iman, seperti yang kerap dibisikkan dari mulut ke mulut di warung kopi. Ini adalah cermin tentang keterasingan, tekanan sosial, dan kesunyian yang tak memiliki ruang untuk didengar di tengah hiruk-pikuk kota kecil ini. Di sinilah seharusnya kita bertanya, bukan menghakimi. Tentang relasi sosial yang retak, tekanan yang tak terlihat, dan kesehatan mental yang masih dianggap tabu. Sebab di balik setiap tragedi, selalu ada cerita panjang yang kita abaikan sampai akhirnya hanya bisa kita kenang.
Akhir-akhir ini, obrolan tentang politik keluarga kian ramai di warung kopi, dari Simpang Lima, Ulee Kareng, hingga Lampriet. Dari abang-abang warung, mahasiswa yang pura-pura mengerjakan skripsi, hingga bapak-bapak pensiunan pegawai yang rutin nongkrong pagi, siang, malam semua membahas politik warisan.
Konon, ada seorang mantan kepala daerah perempuan yang sempat jadi harapan baru, disebut-sebut sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi politik laki-laki di Banda Aceh. Awalnya dielu-elukan sebagai angin segar di tengah politisi tua yang gemar peusijuk proyek. Namun, lambat laun, ia pun turut larut. Kini keluarganya kembali aktif di politik. Tak hanya dirinya, tapi juga suami, anak, dan kerabatnya mulai masuk gelanggang.
“Hinoe, menyoe keun Aneuk jih si nyan, ya lakoe si jeh, masyarakat biasa ya lage haba nyan. Lage tajak jaga meunasah,” celetuk seorang kawan aktivis saat kami ngopi di Lamdingin.
Warga menyebutnya “politik meja makan.” Urusan jabatan, proyek, dan calon legislatif diputuskan bukan di ruang dewan atau forum rakyat, melainkan di ruang makan rumah elite politik. Di sanalah segala persekutuan, bagi-bagi jabatan, dan aliran proyek dirancang. Rakyat? Cukup diberi ceramah syariat, disuguhi peusijuk, dan dibagikan kaus partai saat kampanye. Setelah itu, selesai. Protes? Siap-siap dicap “anti syariat” atau “tidak hormat pada ulama.”
Yang lebih ironis, praktik ini sering dibungkus rapi dengan narasi agama. Seolah selama rajin ikut pengajian, mengenakan kerudung syar’i, dan menyebut syariat dalam pidato, maka politik warisan menjadi halal. Padahal, seperti kata seorang teungku tua di kampung saya, “Syariat nyan keu pegangan hate, bukon keu pelindoeng proyek.” Sayangnya, suara para teungku kampung kini kalah nyaring dibanding mikrofon para calon legislatif.
Proyek infrastruktur, beasiswa, hingga izin usaha kerap kali hanya beredar di lingkaran keluarga elite. Maka tak heran, jika drainase macet tiap hujan, ruang publik makin sempit, dan program pemuda jalan di tempat. Sementara yang lebih sering diurus adalah razia spanduk, perempuan bercelana jins, atau panjang jilbab ASN. Bukan soal banjir atau harga ikan yang tiap minggu naik di pasar Peunayong.
Kadang saya geli sendiri. Banda Aceh ini seperti kota yang pemimpinnya lebih suka jadi figuran film aksi ketimbang pengelola kota. Daripada fokus memperbaiki birokrasi atau mencabut izin hotel yang melanggar aturan, mereka sibuk turun ke lapangan untuk razia. Bukannya cukup keluarkan surat keputusan, tapi tampaknya seragam Satpol PP lebih fotogenik untuk pencitraan. Keliling kota, sorot kamera, tegur pedagang kecil, lalu unggah selfie sambil bagi masker. Urusan jalan rusak dan izin usaha ilegal? Nanti saja, tunggu musim kampanye.
Padahal rakyat butuh pemimpin, bukan aktor sinetron penertiban. Tapi begitulah, politik meja makan membuat jabatan wali kota lebih sibuk merias kota ketimbang memikirkan perut warganya.
Fenomena ini tentu bukan hal baru. Di banyak daerah, politik dinasti memang bukan barang asing. Namun di Aceh, ia lebih licin karena dibungkus dengan syariat. Politik jadi urusan keluarga elite, sementara rakyat hanya diundang ketika pemilu. Setelah itu? Tinggal menunggu undangan tahlilan saat pejabat wafat, atau syukuran saat anak pejabat menikah.
Kini, meunasah yang dulu menjadi ruang diskusi warga, lebih sering digunakan untuk pengajian dan tadarus. Topik-topik kritis seperti harga beras, kondisi kampung, atau kepala desa yang rakus, mulai hilang. Ceramah di meunasah pun kini hanya soal kiamat, aurat, atau wanita surga. Masalah pengangguran pemuda? Disuruh rajin salat. Masalah ekonomi? Dibilang cukup dengan sedekah.
Masyarakat sipil juga makin jinak. Banyak LSM dan aktivis yang dulu galak, kini sibuk urus proposal seminar, atau malah jadi tim sukses caleg. Saya pernah bertanya kepada seorang kawan aktivis yang dulu membakar ban di depan kantor gubernur, kini justru masuk tim kampanye. Ia hanya tersenyum, “Bang, lelah kalau terus melawan. Anak istri tak cukup makan dengan idealisme.” Ya begitulah, politik Aceh memang licin. Yang galak bisa dijinakkan, yang kritis bisa dibungkam, asal meja makannya cukup panjang.
Ironisnya, semua ini terjadi di kota yang mengaku paling syariat di Indonesia. Banda Aceh bangga sebagai kota syariat, tapi praktik politiknya mirip pasar malam bising, semrawut, dan penuh dagangan politik keluarga. Setiap musim pilkada, wajah lama kembali. Jika dulu ayahnya, kini anaknya. Dulu suaminya, kini istrinya. Kadang ditambah menantu atau keponakan. Rakyat? Cukup diberi nasi kotak dan stiker kampanye.
Saya yakin, jika anak muda Banda Aceh terus diam, politik meja makan ini akan bertahan sampai anak cucu kita. Kita butuh keberanian untuk berkata: cukup. Demokrasi bukan warisan, melainkan ruang bagi siapa pun yang punya integritas dan visi. Namun, selama sistem masih begini, jangan harap muncul pemimpin baru. Yang muncul, ya orang yang sama, atau keluarganya.
Aceh sudah terlalu lama disandera politik keluarga. Syariat seharusnya bukan hanya untuk menutup kepala, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran dari kerak ketamakan. Jika terus dibiarkan, rakyat Aceh hanya akan menjadi penonton setia di pesta demokrasi keluarga elite. Rakyat cuma jadi tamu kenduri, sementara dapurnya tetap dikuasai mereka yang itu-itu saja.
Akhirnya, bukan syariat yang jadi panutan, tapi syarat-syarat politik meja makan: asal anaknya, asal keluarganya, asal satu meja makan. Jadi kalau besok abang-abang warung kopi bertanya, “Kenapa Aceh begini-begini saja?” Mungkin jawabannya: karena meja makannya tidak pernah berubah. Kursinya pun masih sama. Dan kita hanya sibuk menepuk tangan di pinggir halaman.
Disclaimer:
Tulisan ini adalah opini pribadi penulis, berdasarkan pengamatan sosial, diskusi warga, dan suasana warung kopi di Banda Aceh. Tidak ditujukan untuk menyerang pribadi atau kelompok mana pun, melainkan sebagai refleksi atas fenomena politik lokal yang terjadi di masyarakat.
Oleh: Rahmatal Riza (Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry)