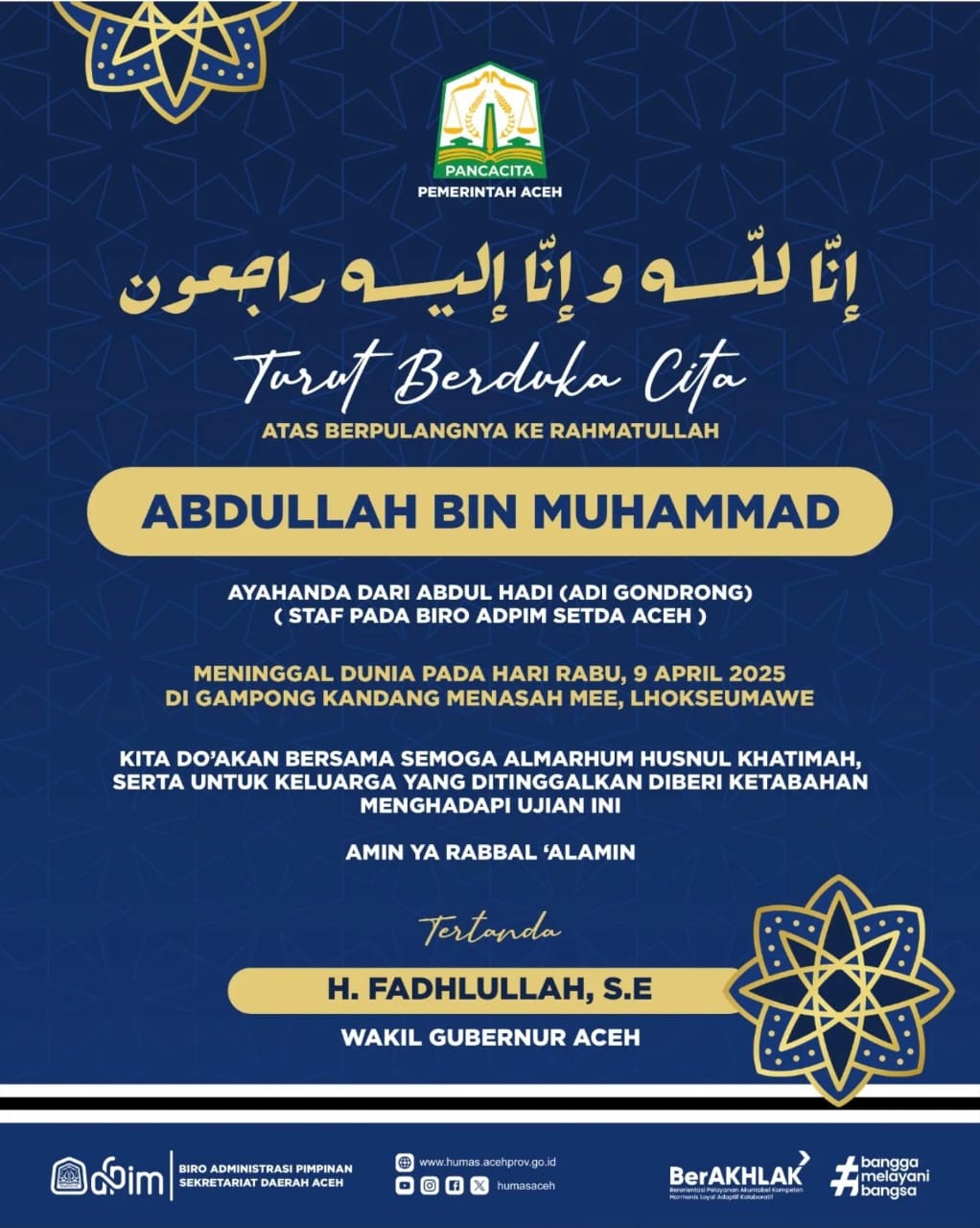Perang Jen
Para tetua di kampung bercerita.
Pada sekitaran tahun 60-an ke bawah di berbagai pelosok Aceh berjangkit penyakit Puree. Dalam Bahasa Indonesia disebut puru, frambusia atau petek.
Penyakit ini akibat infeksi tropis pada kulit, tulang dan sendi yang disebabkan oleh bakteri Spiroket Treponema Pallidum Pertenue.
Penyakit ini berawal dengan pembengkakan keras dan bundar pada kulit, dengan diameter 2 sampai 5 cm.
Luka kulit awal ini biasanya sembuh sendiri setelah tiga sampai enam bulan.
Setelah beberapa minggu sampai beberapa tahun, sendi dan tulang dapat terasa sakit, kelelahan dapat berkembang, dan luka kulit baru mungkin muncul. Kulit telapak tangan dan telapak kaki dapat menjadi tebal dan membuka. Tulang dapat berubah bentuk. Setelah lima tahun atau lebih daerah yang luas dari kulit bisa mati, meninggalkan bekas luka.
Puree menyebar melalui kontak langsung dengan cairan dari luka orang yang terinfeksi. Kontak biasanya bersifat non-seksual. Penyakit ini paling umum pada anak-anak, yang penyebarannya terjadi ketika bermain bersama-sama.
Yang menarik, di kalangan orang Aceh kala itu, puree tidak dianggap penyakit serius. Hanya gejala biologis biasa dan akan sembuh pada waktunya.
Puree justru dianggap ukuran kedewasaan seorang anak.
Bagi anak perempuan yang sudah mengalami puree, maka penyakitnya itu dianggap pertanda dewasa dan segera dinikahkan bila ada yang melamar.
Begitu juga pada anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang telah mengalami puree, maka anak laki-laki itu dianggap sudah cukup umur dan sudah dapat berkumpul dalam komunitas dewasa.
Dalam acara-acara di meunasah sering anak kecil dibentak dan diminta minggir oleh para senior dengan kalimat, “Aneuk mit yang golom meu puree bek sahoe ngen ureung syik”. Artinya anak laki-laki yang belum berpuru dianggap belum akil baligh.
Dengan persepsi yang demikian terhadap puree, maka ketika itu penyakit ini bukan sesuaatu yang ditakuti masyarakat. Tetapi sesuatu yang ditunggu sebagai konfirmasi seseorang telah dewasa.
Pada tahun 70 – 80-an Pemerintah Orde Baru menyadari Indonesia terancam sejumlah penyakit. Termasuk Aceh. Maka dilakukanlah imunisasi.
Misalnya, pada 1973 dilakukan imunisasi BCG untuk tuberculosis. Imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil dilakukan 1974. Lalu imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) pada bayi dilaksanakan 1976.
Saya teringat pada tahun-tahun tersebut di atas sejumlah tokoh, termasuk agamawan, menolak kegiatan imunisasi yang dilakukan pemerintah.
Di tengah masyarakat terjadi persepsi yang berbeda dengan pemerintah.
Melalui imunisasi pemerintah bermaksud agar tubercolosis, tetanus, pertusis tidak menjadi pandemi di Indonesia. Termasuk di Aceh.
Tapi ketika itu pihak yang menolak imunisasi menyampaikan argumentasi yang “mematikan” : Jangan mau diimunisasi. Yang disuntik itu adalah air Nasrani. Siapapun yang disuntik dengan vaksin tersebut akan jadi Nasrani.
Lalu penolakan masif pun terjadi di tengah-tengah maasyarakat.
Namun setelah ikhtiar keras, panjang dan melelahkan, akhirnya masyarakat sadar bahwa imunisasi itu penting. Masyarakat tidak percaya lagi bahwa vaksin yang disuntik itu air Nasrani.
Hasilnya pun luar biasa. Beberapa tahun setelah suksesnya imunisasi itu, TBC, kematian ibu melahirkan, kematian karena difetri, tetanus serta kematian bayi turun drastis.
Pada tahun 80-an juga dilakukan sejumlah imunisasi. Penolakan masyarakat terhadap imunisasi pada era ini relatif tidak ada lagi. Misalnya imunisasi polio 1981, campak 1982 dan hepatitis B 1997.
Jauh sebelum peristiwa di atas, pada sekitar 1873 Aceh dilanda wabah kolera. Yang dalam beberapa sumber disebut Peunyaket Taeun.
Penyaket Taeun yang melanda Aceh itu diceritakan Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjehers.
Dalam cerita Snouck itu, ketika penyaket taeun melanda Aceh, orang Aceh tidak tahu dan tidak percaya bawa penyakit itu disebabkan oleh virus tertentu.
Sebaliknya orang Aceh ketika itu justru percaya bahwa penyakit taeun itu karena terjadi perang jen (jin). Jin kafir menyerang jin muslim dengan panah. Mereka berlindung di antara manusia tanpa membedakan muslim atau bukan.
Akibatnya, banyak manusia terkena panah itu yang menyebabkan penyakit kolera atau taeun. Penyelesaian terhadap penyakit ini pun kemudian secara penuh ditangani secara spritual. Sampai kemudian Belanda melakukan intervensi medis.
Konon jumlah korban taeun ketika itu sangat banyak.
Saking banyaknya kain untuk mengkafani jenazah yang meninggal tidak cukup lagi. Sampai-sampai harus dikafani dengan ijab rok. Sehingga kemudian hari pandemi kolera di Aceh itu dari generasi ke generasi diceritakan sebagai Taeun Ija Brok. Dalam sejumlah catatan disebutkan kuburan massal korban taeun nija brok itu terletak di kawasan Alue Naga sekarang.
Ternyata di berbagai belahan dunia, selalu ada perspektif dan pendapat berbeda dalam menghadapi sebuah penyakit. Ada pro kontrta. Bahkan ketika pandemi sekalipun.
Terakhir di Aceh negeri teuleubeh ateuh rueng donya.
Ketika sejumlah korban Covid-19 berjatuhan di Aceh, dan kemudian berbagai pihak mencoba menanggulanginya, ternyata ada pihak yang tidak percaya bahwa Corona adalah fakta yang nyata adanya.
Bahkan ada yang mengedepankan alasan-alasan agama dan spritualitas untuk menguatkan argumentasi mereka bahwa Corona itu tidak ada. Hanya rekayasa untuk kepentingan pihak tertentu.
Justru ketika kebenaran fakta Corona itu diungkapkan oleh seorang ulama besar, yang masyarakat Aceh mangakui integritasnya, dan ulama bersangkutan mengalaminya secara langsung, masih ada masyarakat — yang selama ini mengklaim dirinya pengikut ulama — tidak percaya fakta Corona yang disampaikan sang ulama.
Alih-alih percaya, mereka justru bertindak zalim. Menuduh sang ulama mulia itu telah dibayar agar bersedia menyampaikan fakta Corona. Ada juga yang menyangka sang ulama yang dihormati itu dipaksa menyampaikan kenyataan Covid-19 yang dialaminya. Sesuatu dugaan yang a-historis dan un-logis.
Menyaksikan fenomena yang demikian, akhirnya kita teringat kata-kata orang arif.
Kepada orang bebal tidak perlu menyampaikan seribu satu penjelasan dan alasan terkait suatu perkara, karena yang bersangkutan otak dan hatinya telah digelapkan oleh kebebalan mereka.
Hidup mereka telah dipenuhi kebencian, kemarahan yang membara serta kecurigaan. Hatta kepada seorang ulama yang berintegritas sekalipun.
Di Bumi Aceh ini, ketika kata-kata ulama tidak dipercaya lagi, lalu siapa yang harus kita percaya ?.
Apakah Anda sehat?.[]