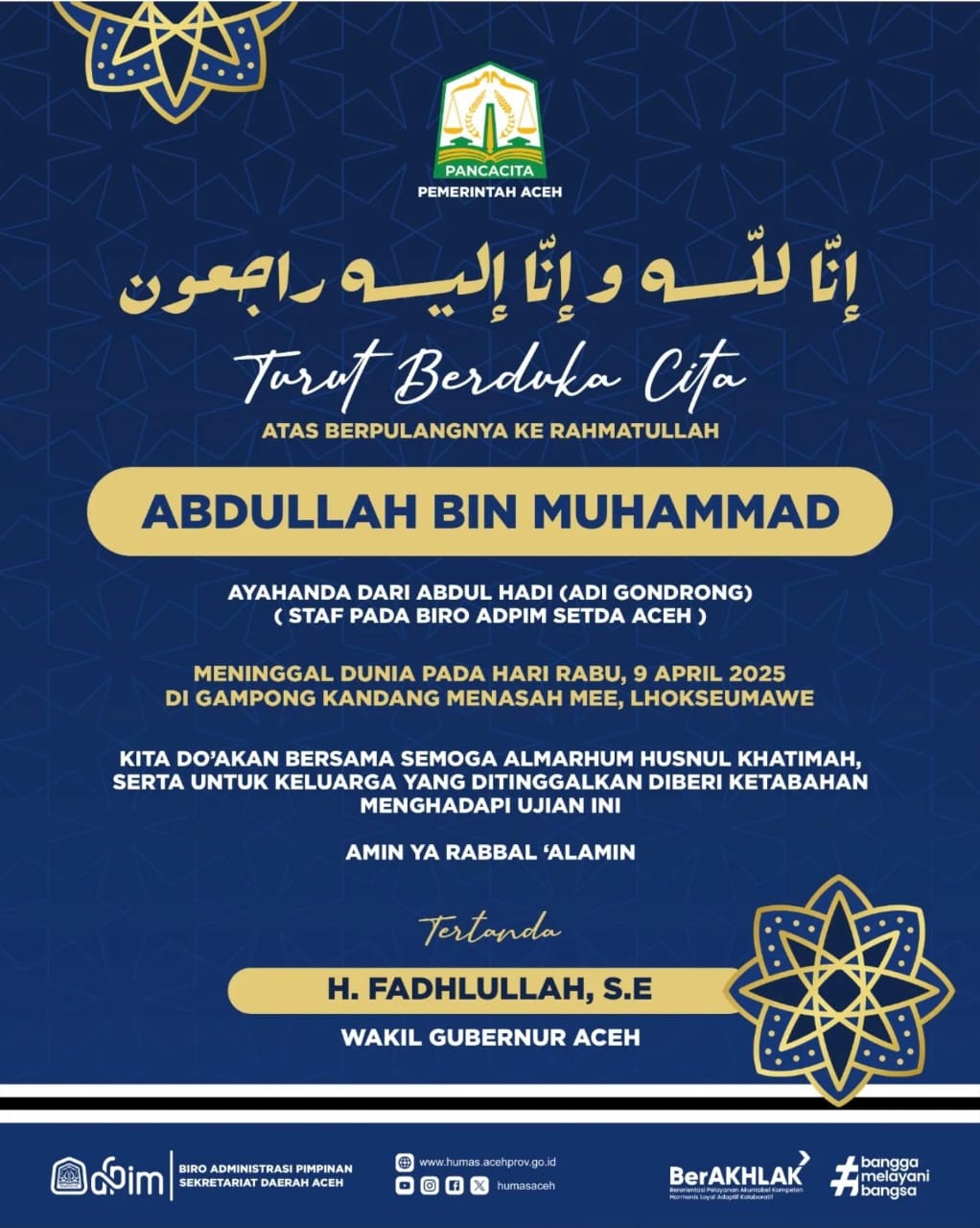Lari dari Syariat: Aceh Run 2025 dan Kegagalan Sensitivitas Kultural
Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus dalam pelaksanaan Syariat Islam, mestinya menjadi teladan dalam penegakan norma dan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kegiatan publik. Namun, pemandangan yang terjadi dalam acara “FKIJK Aceh Run 2025” justru memperlihatkan kemunduran komitmen terhadap nilai-nilai yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat Aceh.
Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh, sebagai representasi institusi keuangan yang semestinya menjunjung tinggi integritas dan sensitivitas sosial-budaya, justru mempersembahkan tontonan yang mencederai marwah Syariat. Penampilan para peserta yang mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam – yakni berlari dengan celana pendek yang mempertontonkan aurat – mencerminkan kelalaian serius dalam memahami konteks lokal Aceh yang bersyariat.
Fenomena ini menunjukkan adanya “lari bersama” dari komitmen terhadap Syariat, alih-alih sekadar lari untuk kesehatan. FKIJK, tampaknya, terlalu sibuk mengatur urusan ekonomi hingga lupa bahwa di Aceh, ekonomi dan agama bukan dua kutub yang saling menegasikan, melainkan harus saling menguatkan dalam kerangka maslahat.
Lebih ironis lagi, acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh – seorang pejabat publik yang semestinya menjadi simbol pelindung Syariat Islam. Alih-alih menyerukan adab berpakaian yang sesuai, beliau berdiri di panggung pembukaan tanpa sedikit pun menegur atau sekadar mengimbau para peserta agar menutup aurat, misalnya dengan memakai manset kaki. Diamnya pejabat di hadapan pelanggaran nilai syar’i bukan hanya pasif, tetapi bisa dibaca sebagai bentuk pembiaran yang tak bisa dianggap remeh.
Apakah ini bentuk modernisasi? Ataukah justru westernisasi yang dibungkus jargon kebugaran? Ironisnya, di tanah yang hukum cambuk diberlakukan untuk pelanggaran aurat, justru aurat dipertontonkan dalam euforia lari massal yang diluncurkan secara resmi oleh lembaga resmi. Di mana fungsi pengawasan internal, dan lebih jauh lagi, di mana suara-suara Stakheholders yang selama ini aktif mengawal ruang publik Aceh?
Kita tentu tak menolak olahraga. Islam pun mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan. Tapi apakah harus dengan menanggalkan kehormatan Syariat? Apakah tidak bisa diselenggarakan dengan pakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan fikih?
Aceh bukan Jogja, bukan Bandung, bukan Bali. Aceh adalah Serambi Mekkah – bukan hanya nama, tetapi amanah. Maka, setiap kegiatan publik di Aceh mestinya tunduk pada ruh dan nilai-nilai Syariat, bukan tunduk pada tren global yang mengabaikan etika lokal.
Jika pelanggaran seperti ini terus didiamkan, maka jangan salahkan rakyat Aceh jika mulai mempertanyakan ketulusan lembaga-lembaga publik dalam menghormati qanun yang berlaku. Jangan sampai masyarakat melihat ada wajah ganda: satu wajah religius di atas mimbar dan satu wajah permisif dalam arena.
FKIJK Aceh, dalam hal ini, harus bertanggung jawab secara moral dan kultural. Dan kepada para pejabat publik, hendaknya tidak cukup menjadi penonton dari hilangnya kehormatan Syariat dalam ruang publik Aceh. Sudah saatnya kita berhenti berlari dari jati diri.
Oleh: Tgk. Alwy Akbar Al Khalidi, SH, MH (Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Alumni Dayah Aceh, Mahasiswa Doktoral Islamic Studies Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Pengajar Sosiologi Hukum dan Pemikiran Hukum Islam)