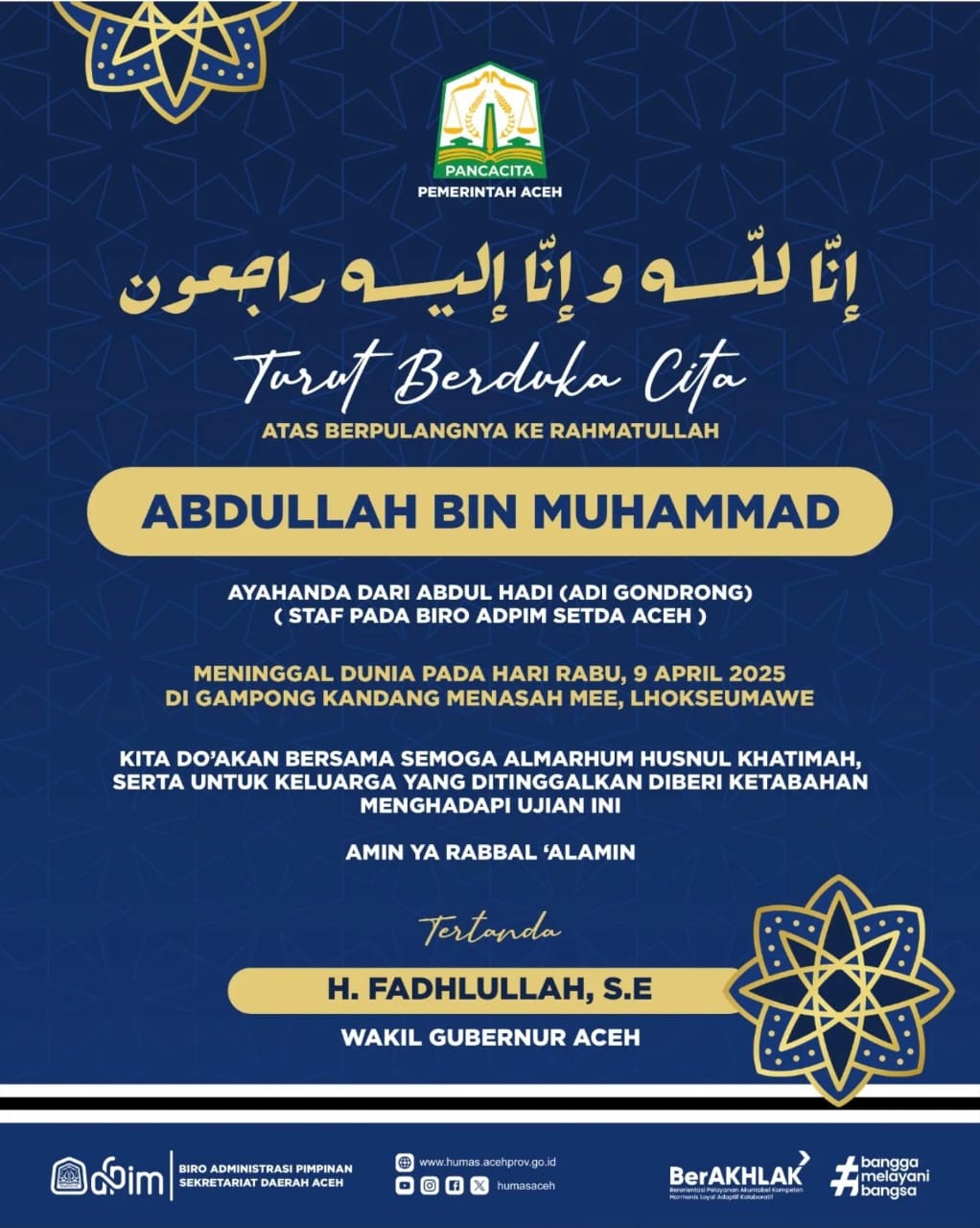Insan Kamil, Siapakah?
Oleh : Syah Reza
Siapapun pasti pernah menonton film Superman. Film yang diproduksi sejak tahun 1930an menggambarkan kehebatan seorang manusia yang memiliki kemampuan fisik luar biasa, bisa terbang, mengangkat beban berat, mata mengeluarkan sinar, tubuh kebal dari berbagai macam benturan benda, dan kehebatan fisik lainnya.
Film yang diangkat dari komik, karya Joe Shuster itu adalah fiktif. Namun karakter superman (manusia super) tampaknya punya kaitan erat dengan konsep manusia sempurna dalam tradisi filsafat Barat.
Dalam literatur Barat, teori manusia sempurna (Übermensch) secara detail ditemukan dalam filsafat eksistensialisme Friedrich Nietzsche. Salah satu pemikir Barat Atheis, yang dikenal dengan gelarnya “Sang pembunuh Tuhan”.
Ia menganut paham rasionalis-humanis yang menganggap superioritas manusia di atas segala realitas. Potensi yang dimiliki manusia menurutnya mampu mencapai titik tertinggi dalam proses kesadaran.
Terutama ketika berhadapan dengan perang, sesuatu yang bahaya atau berupa rintangan besar, dia cenderungan mengeluarkan potensi terbesar dari dirinya. Dalam kondisi tertekan demikian, proses berfikir dan kekuatan fisik akan bekerja secara maksimal melampaui kehidupan biasanya.
Baginya, manusia menentukan segala sesuatu, bukan lainnya. Pada kulminasi tertentu, manusia sempurna akan menaungi manusia lainnya. Pada konsep tersebut kental sekali penafian peran tuhan atau agama dalam diri manusia.
Penafian itu berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan ajaran Kristen. Idenya cenderung fatalistik, dan tampak bangunan logikanya tidak utuh ketika memahami konsep manusia sempurna karena bertumpu pada perpektif Rasionalisme-Empiris dengan mengandalkan supremasi akal, yang sebetulnya sangat terbatas. Padahal ada sisi lain yang bersifat metafisis-ontologis melampaui akal yang hanya mampu dijelaskan melaui agama.
Hakikat Insan Kamil
Jauh sebelum lahirnya konsep manusia super versi kaum rasionalisme barat, Islam sejak awal turunnya wahyu telah menyampaikan isyarat tentang manusia sempurna. Isyarat Al-Quran untuk manusia sempurna ada pada kata Ahsan al-Taqwim (QS 95: 4) adalah sebaik baik bentuk (jasad dan ruh).
Artinya, Allah menciptakan manusia sebagai kesempurnaan dari seluruh ciptaan, baik alam maupun malaikat. Ini adalah makna universal ditujukan pada semua manusia berada dalam lingkup kesempurnaan. Hal itu merupakan perbuatan Allah (Af’al) melalui sifat Ar-Rahman.
Tetapi secara khusus, makna kesempurnaan manusia akan berbeda derajat. Derajat dasar ketika menjadi Islam (Alyauma akmaltu lakum dinakum..). Selanjutnya orang beriman, orang shalih, ulama, waliullah, dan derajat tertinggi yaitu Nabi.
Terkhusus lagi di antara derajat tertinggi itu yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang disebut oleh para ulama sebagai Insan Kamil baik secara zahir maupun bathin. Manusia Paripurna diatas manusia lainnya.
Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Insan Kamil yang secara spesifik membahas konsep manusia sempurna mengatakan bahwa, Nur Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk pertama yang diciptakan Allah dari kesempurnaan-Nya (al-Kamil) yang mendahului makhluk lainnya sebelum Allah jadikan alam zahir ini (kharijiyah).
Artinya, Insan Kamil itu penisbahan pada diri Nabi Muhammad SAW, baik sebagai cahaya awal penciptaan.
Kriteria Insan Kamil
Diri Nabi Muhammad SAW yang Ma’sum (terbebas dari dosa) dengan segala sisi yang melekat pada diri beliau, adalah representasi manusia agung yang dicintai Allah. Karena itu, Allah mengatakan bahwa Nabi sebagai suri tauladan karena kesempurnaan dari semua sikap yang terbaik dialam ini ada pada dirinya (QS. Al-Ahzab:21).
Seorang muslim ketika mampu mengikuti ketauladan Nabi melalui risalahnya, akan berada pada derajat Insan Kamil. Artinya, siapapun mampu mencapai tingkatan itu atas izin Allah.
Secara sederhana, Imam al-Ghazali telah memberikan salah satu patron secara integratif sikap manusia sempurna. Dalam Misykatul Anwar, ia mengatakan bahwa Insan kamil itu yaitu mereka yang cahaya ilmunya (zahir) tidak memadamkan cahaya wara’-nya (batin).
Maksudnya, sikap adil yang tidak terlalu condong pada zahir sehingga menolak sisi batin seperti kaum Hasyawiyah (kaum dari ahlul hadist dari golongan ahlussunnah) yang mengatakan tuhan memiliki bentuk dan sifat seperti yang ada pada makhluk (bertangan, bertubuh, berkaki, naik, duduk, dan sebagainya).
Mereka memahami ayat Al-Quran dan dalil secara zahir dengan mengabaikan makna batin. Bukan juga mereka yg terlalu condong pada bathin seperti kaum bathiniyyah (seperti Syiah Ismailiyah dan sejenisnya) dan Psedo Sufi (Aceh: salèk buta) yang meninggalkan hukum hukum syariat secara lahiriyah, seperti perbuatan meninggalkan kewajiban shalat, dengan alasan ia terus menerus melakukan shalat secara bathin. Dan alasan bahwa Allah tidak butuh pada amalan manusia. Ini pandangan menyimpang.
Sejatinya seorang muslim yang adil, ia yang mampu menundukkan nafsunya (atas bimbingan Allah) ketika menjalankan perintah Agama. Tunduk pada syariat dan hakikat secara totalitas (kaffah).
Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika Allah memerintahkan menanggalkan kedua sandalnya. Beliau melakukannya secara zahir yaitu melepaskan kedua sandal, dan secara batin meninggalkan dua alam, dunia dan akhirat untuk bisa melihat Allah.
Sikap adil itu secara khusus melekat pada orang orang khusus di antara kaum muslim, baik Nabi, ulama dan orang shalih. Kemampuan menangkap dan menyikapi setiap realitas yang hadir dengan petunjuk Allah.
Insan Kamilterwarisi pada umat Nabi Muhammad yang secara khusus disebutkan dalam hadistnya yaitu para Ulama (Al-‘Ulama’ Warasatul Anbiya’). Ulama yang mana dan bagaimana? salah satunya yang melekat padanya sikap Adil dalam diri, disertai iman yang tinggi.
Kapan ia meletakkan dan menyikapi sesuatu dari sudut pandang zahir dan bathin berdasarkan ilmu dan iman, bukan orientasi lainnya. Implikasi dari sikapnya tersebut mampu terwujudnya kemaslahatan bagi umat Islam secara khusus, dan alam secara umum. Adakah Insan Kamil di tengah kita saat ini? Wallahualam.
*Penulis adalah peneliti di Islamic Institute of Aceh