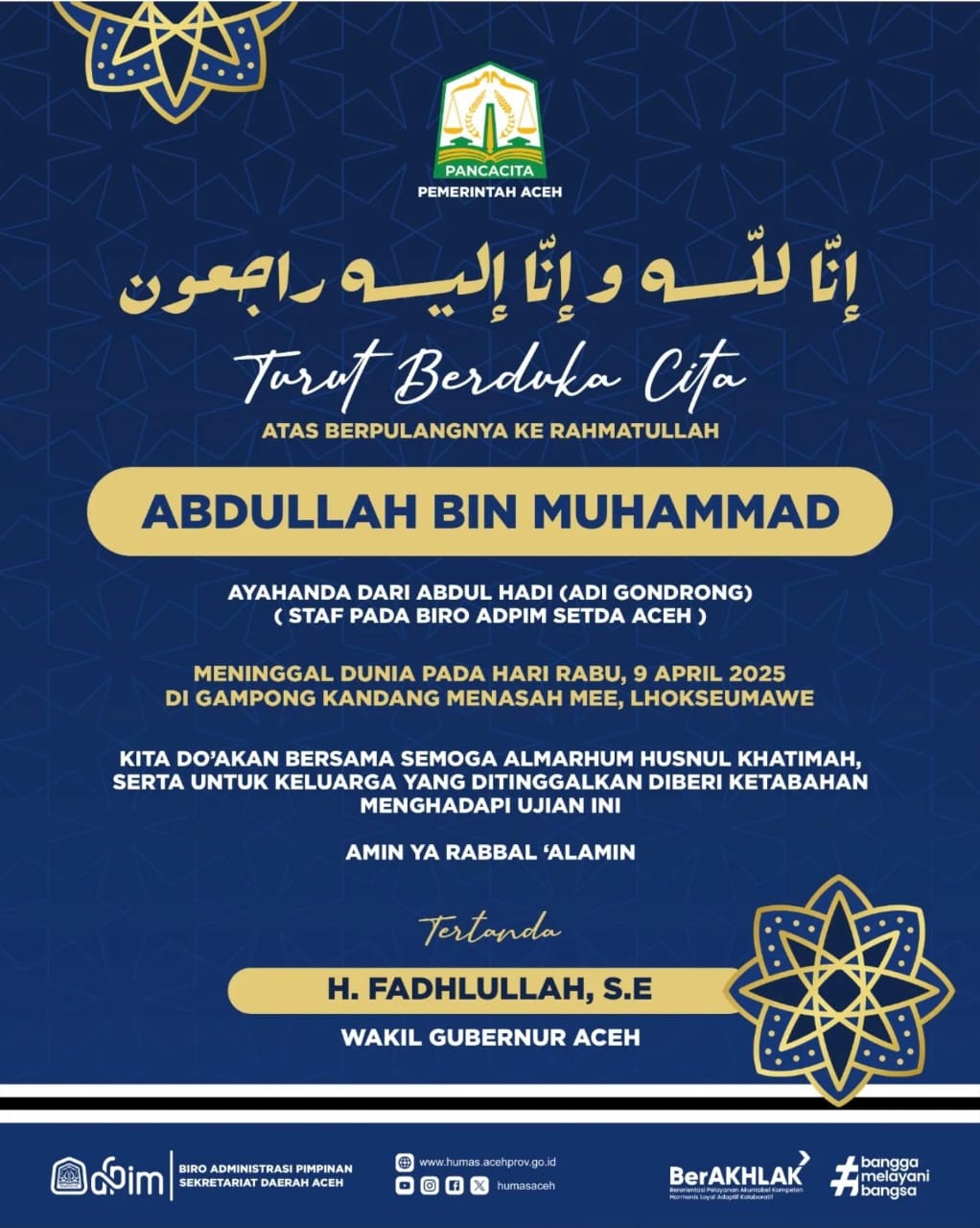Demokrasi itu Lonjong
Oleh Usamah Elmadny*)
BERBAGAI peristiwa demokrasi yang terjadi di berbagai belahan bumi ini seakan mengajarkan kita: Jangan terlalu percaya demokrasi. Jangan terlalu memuja demokrasi. Apalagi menjadikannya sebagai berhala.
Pengalaman empiris mengajarkan kita bahwa demokrasi itu lonjong. Tidak bulat.
Di banyak tempat dan kejadian, demokrasi itu hanyalah sebuah etalase prosedural. Hanya pemenuhan indikator demokrasi—oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat—tanpa menyentuh tuntas tujuan asasi sebuah mekanisme demokrasi dihadirkan. Demokrasi hanya sebatas cara “peralihan” kekuasaan secara santun dan modern yang berbeda dengan cara-cara tradisional yang kasar, keras, dan gaduh.
Demokrasi kadang menjadi cara elite politik dan pemilik modal membajak mandat rakyat, kemudian melakukan berbagai kebijakan subjektif—destruktif atas nama rakyat.
Ketika rakyat disebut telah berpartisipasi secara dominan/ mayoritas dalam sebuah pesta demokrasi, maka momentum itu segera menjadi semacam otorisasi oleh penguasa yang dihasilkan oleh proses demokrasi itu untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat. Sekalipun rakyat berkali-kali melakukan protes terhadap kebijakan mandatarisnya itu.
Kita kadang-kadang terlalu memuji pola demokrasi tertentu. Dan pada kesempatan yang sama mencaci bahkan membenci pola demokrasi versi lainnya.
Sebagai negara pengusung demokrasi kita sering menilai demokrasi yang kita praktikkan belum berkualitas.
Dalam praktik berdemokrasi kita merasa inferior dibanding prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan Amerika Serikat yang kita anggap sebagai kampiun demokrasi dunia.
Seakan demokrasi Amerika Serikat sangat sempurna. Padahal pasca Pilpres, kemarin, ketika pendukung petahana Trump yang kalah itu menyerang gedung parlemen AS segera mengkonfirmasi kepada kita bahwa kualitas demokrasi Amerika Serikat pun masih kelas Taman Kanak- Kanak.
Peristiwa elite politik AS dan sebagian warganya yang tidak menghargai proses dan hasil pilpres yang demokratis menjelaskan kepada kita bahwa demokrasi itu tidak selamanya bulat. Sesuai dinamika sebuah wilayah, demokrasi itu sering lonjong.
Sampai saat ini saya kira belum ada negara yang layak mendeklarasikan dirinya sebagai komunitas pelaku demokrasi terbaik.
Sebagai bangsa kita juga pernah ragu dengan cara berdemokrasi kita. Ragu dan tidak suka dengan cara demokrasi yang selama ini telah kita terapkan, lalu kita beralih kepada cara baru.
Dalam pemilihan kepala daerah, misalnya, beberapa waktu lalu kita dengan kompak dan gegap gempita menyatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD/ DPRK sebagai sesuatu yang tidak demokratis. Penuh transaksi dan politik uang.
Lalu cara pilih kepala daerah pun kita ubah. Dari dipilih oleh wakil rakyat di DPRD/DPRK kita geser menjadi dipilih langsung oleh rakyat atau pilkadasung. Harapan kita sebenarnya sangat humanis. Kita berharap kualitas demokrasi semakin baik agar menghasilkan sosok-sosok kepala daerah, bahkan kepala negara yang berpihak pada kedaulatan rakyat.
Sudahkah harapan itu menjadi kenyataan? Kalau boleh jujur menjawab, belum. Masih jauh panggang dari api.
Di samping kepala daerah yang terpilih sebagai produk pilkadasung, sebagian besar jauh dari harapan.
Tanpa sadar kita juga telah memindahkan “kejahatan” dari gedung DPRD/ DPRK yang dilakukan oleh beberapa orang terbatas dan tidak berdampak langsung kepada rusaknya pranata sosial di tengah-tengah masyarakat, menjadi “kejahatan” kolektif di akar rumput masyarakat.
Karenanya, kemudian tanpa sadar yang dilakukan masyarakat kita dalam setiap pilkada tidak hanya terlibat dalam keberpihakan subjektif yang merusak persatuan, tetapi juga secara kasatmata kita juga menemukan praktik transaksi politik yang dulu kita lawan ketika pemilihan pemilihan kepala daerah kita percayakan kapada legislatif.
Kalau ketika pilkada dilakukan DPRD/ DPRK maka daya rusak yang terjadi terbatas kepada orang perorangan yang ada di gedung dewan. Namu ketika pilkadasubg, kerusakan pada pranata dan struktur sosial budaya masyarakat menjadi tidak terhingga.
Peristiwa model pilkada ini sekaligus mengkonfirmasikan kepada kita bahwa demokrasi itu bukan hitam putih. Bukan bulat tapi lonjong.
Tapi tetap saja ada argumentasi pragmatis dan jangka pendek atas nama demokrasi. Kata mereka, ketimbang manfaat dan keuntungan dari transaksi politik pilkada itu hanya menjadi menu lezat segelintir anggota dewan, kan lebih baik bila “nikmat demokrasi” itu disantap oleh rakyat sebagai pemilik saham tunggal demokrasi?
Bila kerangka berpikir seperti ini sepakat kita usung bersama, kemudian kita mempraktikkannya secara kolektif, maka terhadap kepala daerah terpilih kita kehilangan hak untuk protes. Meminjam istilah PLN, bukankah kepada kita (sebagian rakyat) telah dilakukan transaksi prabayar.
Maka sepanjang demokrasi yang kita sepakati dan praktikkan adalah demokrasi prosedural, maka selama itu pula kita lebih banyak mendapat mudarat dari manfaat berdemokrasi.
Dalam bahasa Khalifah Umar bin Khattab dijelaskan bahwa sosok seorang pemimpin adalah representasi yang dipimpin (rakyat yang memilih pemimpin).
Kesalahan atau tepatnya jalan sesat demokrasi yang kita tempuh selama ini sepertinya telah memantik kesadaran sejumlah parpol di Indonesia. Demokrasi langsung ternyata selama ini telah mereduksi atau merusak sejumlah infrastruktur sosial politik sejumlah parpol.
Demokrasi yang selama ini dipraktikkan sejumlah parpol telah menyebabkan sejumlah parpol rusak parah. Hilangnya soliditas partai.
Lenyapnya penghargaan dan apresiasi kepada kader cerdas dan berkeringat yang sejak dini hari bersama partai ikut mendaki bukit. Mereka dengan mudah diganti dengan sosok sosialita populer yang datang kemudian ketika tiba di puncak. Mereka tidak berkeringat.
Dalam sebuah muktamar, munas, atau konferensi parpol dapat saja seketika kader terbaik parpol tidak terpilih karena tidak punya banyak uang. Tapi kader mualaf yang tiba-tiba muncul dengan dukungan pemilik modal tampil memenangkan pertarungan menjadi Ketua Umum Parpol.
Saya yakin kesadaran ini akan menjadi otokritik sekaligus koreksi kita terhadap tata cara kita berdemokrasi.
Akhir-akhir ini sejumlah parpol dalam memilih top leader mereka tidak lagi dengan cara melakukan voting, tetapi dengan musyawarah mufakat. Alasannya sederhana, mekanisme voting dalam pemilihan Ketua Umum Parpol adalah karpet merah bagi pengusaha atau pemilik modal di luar partai untuk melakukan intervensi ke partai.
Memang masih ada yang berteriak, bahwa pemilihan ketua parpol secara musayawarah jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Menurut kelompok ini, demokrasi sejati meniscayakan voting.
Kepada mereka yang berkeyakinan demikian wajar kita ajukan pertanyaan sederhana: Yang Anda inginkan demokrasi prosudural atau demokrasi substantif?
Pseudo demokrasi (demokrasi semu) atau demokrasi yang memberdayakan sebuah komunitas demokrasi?
Konten sebuah demokrasi adalah komitmen dan kesepakatan kita selaku pengusung demokrasi. Bukan memaksa diri dengan flatfom dan konten dari pihak lain. Demokrasi itu lonjong. Bukan bulat!
*) Penulis adalah editor/kolumnis Theacehpost.com