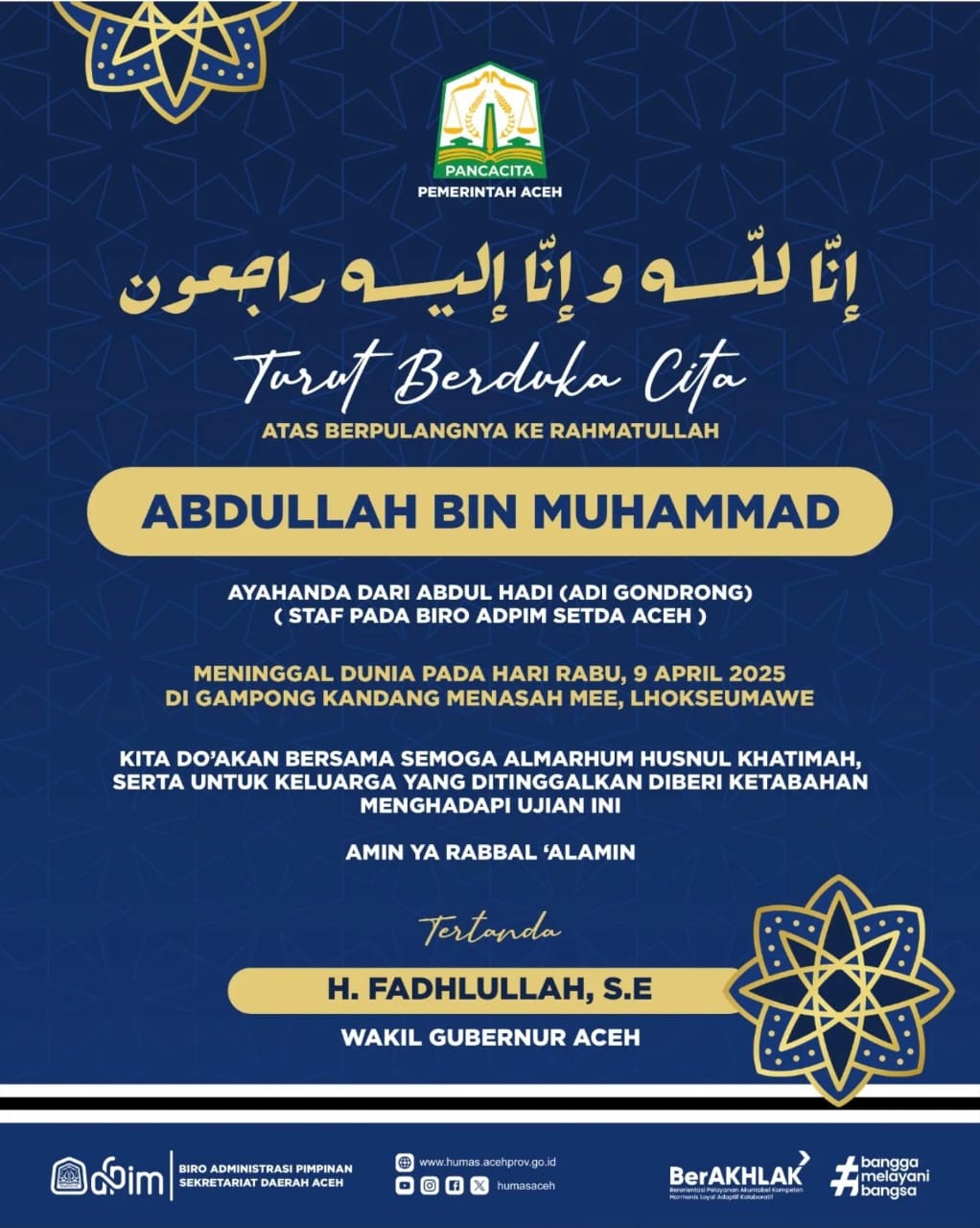Aku Si Anak Emping
Pagi minggu, matahari masih melirik di antara batang rumbia, embun pun seakang enggan meninggalkan dedaunan, burung masih saja benyanyi menyambut pagi yang begitu syahdunya, Usman mulai menumbuk biji melinjo di halaman rumah. Suara lesung dan alu bersahutan dengan suara ayam dan desir angin dari sawah yang mengelilingi desa kecil mereka di Pidie. Di sudut beranda, ibunya duduk bersandar di dinding, tongkat kini selalu menemani kemapun ia pergi. Matanya memerhatikan Usman tanpa suara, hanya senyum lemah yang sesekali muncul di wajahnya.
Usman adalah anak ketiga dari empat bersaudara. kakaknya telah merantau ke kota untuk bekerja serabutan, meninggalkan Usman dan adiknya di rumah tua yang mulai lapuk, menemani ibunya yang kini hanya bisa berbaring karena sakit yang tak kunjung sembuh. Hidup Usman serba kekurangan, namun ia tetap bertahan.
Kehidupan Usman kontras dengan keluarga besar ayahnya. Ayah Usman berasal dari keluarga terpandang di desa. Ia memiliki banyak saudara yang hidup berkecukupan, bahkan beberapa di antaranya bisa dibilang kaya. Paman Usman yang bernama Teuku Hasan, misalnya, dikenal sebagai orang paling berada di desa. Ia memiliki beberapa hektar kebun, truk pengangkut hasil panen, dan rumah besar dengan genteng merah yang mencolok.
Namun kekayaan keluarga besar ayahnya tidak serta-merta mengalir ke Usman. Sejak kecil, Usman hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Ayahnya, Abdurrahman, adalah satu-satunya dari delapan bersaudara yang memilih hidup sederhana, membangun rumah kecil dari kayu, dan bekerja sebagai buruh tani. Ketika ayah Usman meninggal dunia pada tahun 2002 karena serangan jantung mendadak, kehidupan keluarga Usman seolah kehilangan cahaya.
Saat itu Usman baru berusia tujuh tahun. Ia masih ingat hari ketika tubuh ayahnya yang dingin terbujur di atas tikar pandan, dikelilingi pelayat yang ramai, termasuk paman-pamannya yang datang dengan pakaian bagus dan mobil mewah. Tapi setelah hari pemakaman selesai, satu per satu mereka pergi, meninggalkan ibu Usman dengan tiga anak dan beban hidup yang tidak ringan.
***
Ibu Usman, Nurma, kemudian menggantungkan hidup dengan membuat emping melinjo. Ia mengajarkan Usman menumbuk biji melinjo sejak kecil, karena tidak ada lagi yang bisa membantu. Sejak saat itu, Usman tak hanya menjadi anak, tetapi juga tulang punggung keluarga.
Emping bukan hanya sumber penghasilan, melainkan simbol perjuangan. Setiap pagi sebelum berngkat sekolah, Usman menyusuri jalan setapak untuk mengutip melinjo dari pohon-pohon yang tumbuh liar di kebun peninggalan ayahnya. Kemudian ia membawa pulang hasilnya, mengupas, menumbuk, dan mengemasnya untuk dijual ke pasar. Kadang, hasilnya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Kadang tidak.
Usman bukan anak yang suka mengeluh. Ia menerima hidup apa adanya. Teman-temannya di sekolah tahu bahwa Usman adalah anak miskin yang memakai sepatu robek dan membawa bekal nasi garam, tapi mereka juga tahu bahwa Usman anak yang pintar. Ia sering membantu teman-temannya mengerjakan PR, dan gurunya selalu memujinya.
“Usman, kamu punya bakat menulis. Teruskan ya,” kata Bu Nisa, guru Bahasa Indonesia nya, suatu hari setelah membaca karangan Usman tentang kehidupannya.
Karangan itu berjudul “Emping Terakhir untuk Ayah.” Cerita tentang latar belakang kehidupan Ayah Usman. Cerita itu lahir dari hati Usman, dari kehidupan sehari-hari yang ia jalani dengan sabar.
Tanpa sepengetahuan Usman, Bu Nisa mengirimkan karangan itu ke lomba menulis tingkat provinsi. Cerita itu meraih juara dua, dan nama Usman pun disebut-sebut di berbagai media lokal. Bukan hanya karena tulisannya yang menyentuh, tapi juga karena latar hidupnya yang menginspirasi.
Saat menerima penghargaan di Banda Aceh, Usman mengenakan baju pinjaman dari tetangganya. Ia berdiri di panggung dengan gugup, sementara ibunya menonton lewat televisi kecil yang dipinjam dari tetangga sebelah. Wajah Usman yang kaku berubah hangat saat menyampaikan pidatonya.
“Saya menulis karena saya ingin Ibu bahagia. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya cerita. Saya anak emping. Dan saya bangga.”
Penghargaan itu membuka banyak pintu. Beasiswa mulai berdatangan, dan sebuah yayasan sosial mulai membantu biaya pengobatan ibunya. Pamannya, Teuku Hasan, yang selama ini tak banyak bicara, tiba-tiba datang membawa beras dan uang bantuan.
“Maafkan Paman, Usman. Paman tidak tahu keadaanmu seburuk ini,” katanya dengan suara lirih.
Usman hanya mengangguk. Ia tak menyimpan dendam. Ia hanya ingin ibunya sembuh.
***
Kini, Usman sudah dewasa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Banda Aceh dengan bantuan beasiswa. Ia menulis untuk media nasional dan telah menerbitkan buku kumpulan cerpen, salah satunya berjudul “Emping Terakhir untuk Ayah.”
Di desa, ia kembali membangun rumah kecil untuk ibunya yang kini sudah jauh membaik kesehatannya. Ia juga membuka rumah baca untuk anak-anak desa, agar mereka punya harapan dan mimpi yang lebih besar.
Usman tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Bagi dunia, ia mungkin hanya penulis dari desa kecil. Tapi bagi ibunya, ia adalah anak yang membuat emping terakhir, dengan cinta dan harapan yang tak tergantikan.
Dan bagi Usman, emping itu akan selalu menjadi pengingat—bahwa dari kesederhanaan, bisa lahir kekuatan yang luar biasa.