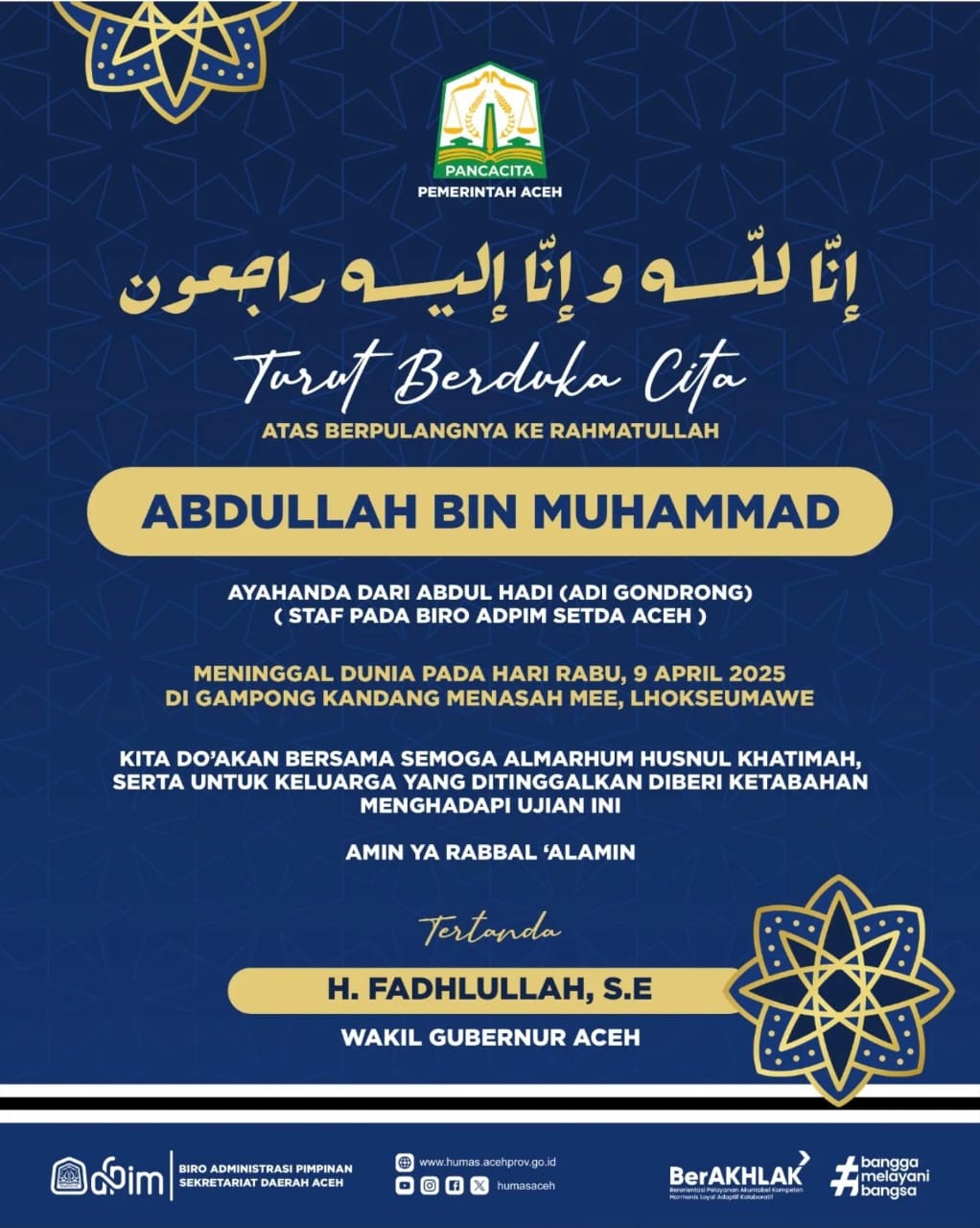Budaya Fee Proyek di Aceh, Ketika Kebiasaan Menantang Akuntabilitas
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Di banyak dinas, sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik permintaan fee proyek seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pelaksanaan pekerjaan pemerintah.
Para pejabat dan pegawai yang seharusnya menjalankan tugas secara profesional justru menjadikan posisi mereka sebagai “pintu masuk” untuk memperkaya diri.
Tak jarang, proyek yang bersumber dari dana publik hanya bisa berjalan jika rekanan bersedia menyerahkan fee antara 5 hingga 15 persen dari total nilai kontrak, bahkan ada juga sebagian yang minta hampir 30 persen dari nilai kontrak, kejam memang tapi inilah fakta yang terjadi di lapangan.
Hal ini sungguh ironis, sebab para ASN dan pejabat tersebut telah digaji oleh negara. Namun dalam praktiknya, seakan gaji itu tak pernah cukup.
Fee proyek menjadi semacam “uang pelicin” yang wajib dibayarkan jika ingin memperoleh pekerjaan. Bahkan, tak sedikit pihak rekanan yang sudah mengantisipasi pungutan ini dalam perhitungan anggaran mereka.
Yang lebih menyedihkan, semua pelaku proyek sebenarnya tahu praktik ini ada. Kontraktor, penyedia jasa, hingga konsultan pengawas pun mafhum: jika mereka tidak “ikut aturan main” dan enggan memberikan jatah fee, maka proses administrasi proyek akan dipersulit.
Berkas bisa tertahan berhari-hari, pencairan dana tertunda tanpa alasan yang jelas, bahkan kesalahan kecil dalam dokumen bisa dibesar-besarkan sebagai alasan untuk menggagalkan proyek.
Dengan kata lain, sistem ini sudah berjalan seperti mesin yang saling mengunci. Kontraktor merasa terpaksa, pegawai merasa berhak, dan publik tetap menjadi korban karena proyek yang seharusnya dibangun dengan baik justru dikompromikan demi “jatah orang dalam”.
Tertangkap Tangan: Konsekuensi Hukum
Jika seseorang tertangkap tangan menerima atau meminta fee proyek, maka dapat dilakukan proses hukum melalui mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian).
Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, seseorang dinyatakan tertangkap tangan bila sedang melakukan, baru saja melakukan, atau ditemukan bersama barang bukti tindak pidana. Dalam konteks fee proyek, bukti transfer atau uang tunai menjadi kunci dalam proses OTT.
Pelaku bisa langsung ditahan dan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Landasan hukum lainnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 12 huruf e:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”
Ancaman pidana: seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Pasal 11:
“Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya…”
Ancaman pidana: penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp250 juta.
Selanjutnya juga tertera dalam KUHP Pasal 418 dan 419 (gratifikasi/penyuapan ringan).
Praktik fee proyek bukanlah hal sepele. Ini adalah bentuk korupsi yang terselubung tetapi sistemik. Semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima, ikut menopang struktur yang merusak pelayanan publik. Maka, perubahan harus dimulai dari kesadaran kolektif dan keberanian untuk berkata “tidak” terhadap pungutan liar ini.
Jika tidak dimulai sekarang, kita hanya akan terus menyaksikan generasi demi generasi hidup dalam sistem yang sama: yang korup, yang takut bicara, dan yang selalu berkompromi. []
Baca berita lainnya di Google News dan saluran WhatsApp