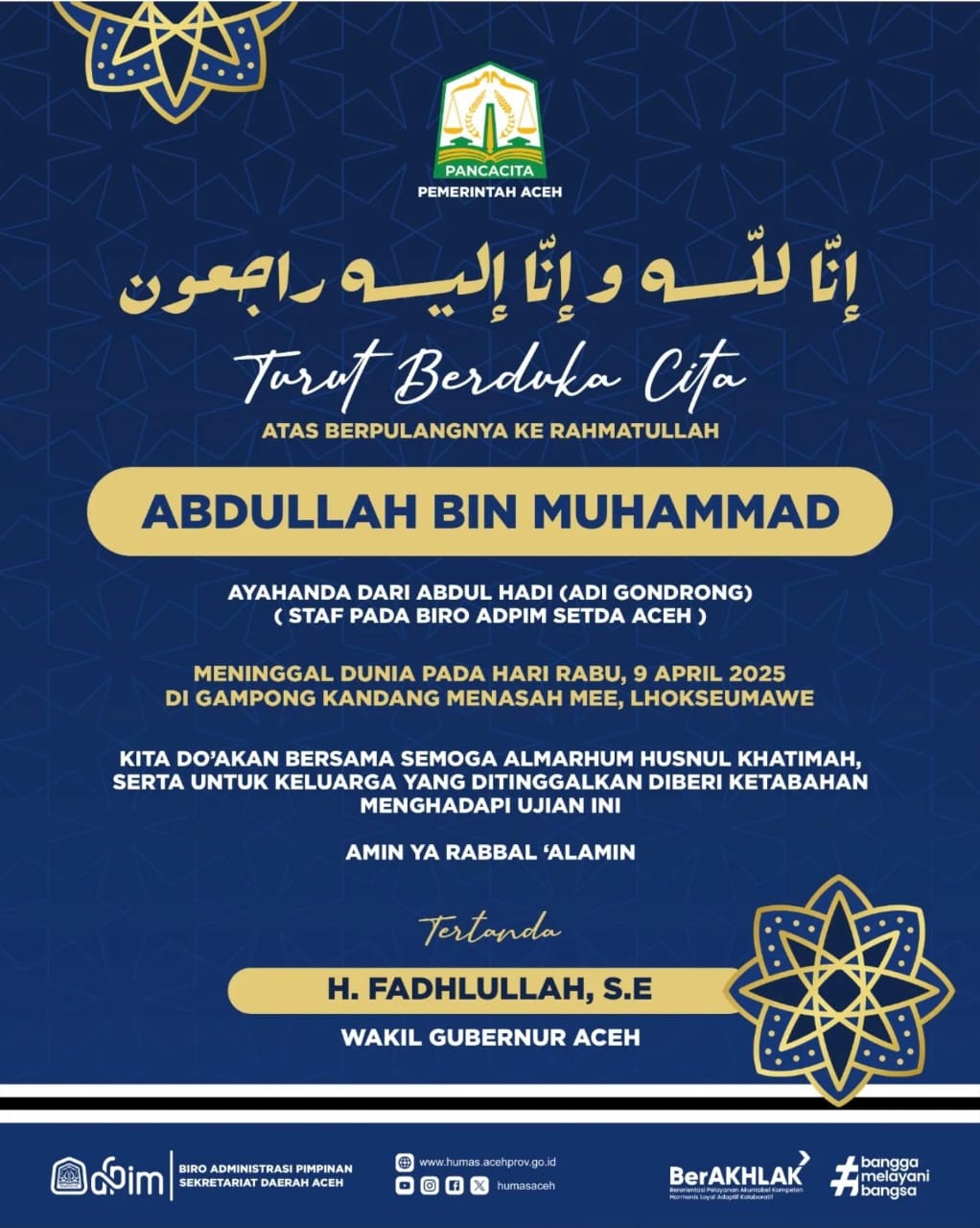Menakar Perhelatan Pemilihan Serentak
THEACEHPOST.COM – Pagelaran pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah usai.
Pasca rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten Kota kemudian dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon (paslon) perolehan suara terbanyak sebagai pemenang pemilihan serentak (Pilkada), tentu saja banyak pihak yang melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya, yang terhangat adalah usulan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya di perayaan ulang tahun Golkar yang ke-60 beliau memberikan sebuah usulan terhadap pilkada agar dikembalikan ke DPRD provinsi dan kabupaten kota.
Jauh sebelum pilkada ini dilaksanakan, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemilihan tidak langsung.
Teknisnya adalah para kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mendaftarkan diri melalui partai politik dan atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
Setelah melewati tahapan pencalonan hingga penetapan paslon, tahapannya terakhirnya adalah pemilihan dilaksanakan melalui voting oleh anggota DPRD. Prosesi ini terakhir dilaksanakan di tahun 2004 kemudian lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Sejak perhelatan pilkada dari tahun 2005 hingga kini, lalu kenapa ini menjadi hangat untuk di perbincangkan? Ada beberapa sudut pandang yang membuat pilkada tetap dilanjutkan atau tidak.
Salah satu hal yang paling disoroti adalah tentang efisiensi anggaran, sebab untuk melaksanakan pilkada berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 pendanaannya dibebankan kepada APBD, dimana biaya pilkada tahun 2024 untuk pengalokasiannya berasal dari Tahun Anggaran 2023 sebesar 40 persen dan untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen.
Anggaran tersebut tentu bukan hanya untuk melaksanakan rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara serta pengadaan logistik saja, termasuk juga pendanaan di setiap tahapan pilkada, mulai dari awal sosialisasi pencalonan sampai ke penyiapan TPS serta honorarium seluruh badan adhoc baik itu PPK, PPS maupun KPPS.
Disamping itu, anggaran ini bukan untuk 1 (satu) lembaga saja melainkan ada 2 (dua) lembaga yakni; KPU dan Bawaslu. Sudah barang tentu jika menilik dari sisi anggaran, pelaksanaan pilkada akan menyerap anggaran daerah yang sangat besar.
Tentu saja ini akan berbanding terbalik apabila dilakukan pemilihan di DPRD. Barangkali dapat diasumsikan anggaran yang dibutuhkannya hanya untuk biaya pelaksanaan persidangan saja. Selanjutnya, kenapa anggaran ini mendapatkan sorotan? Karena pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.
Sudah barang tentu perkara ini mendapat atensi yang cukup besar dari sejumlah kalangan. Sementara di pilkada-pilkada yang lalu dengan besaran anggaran yang sama tidaklah menjadi perhatian karena proses pelaksanaannya tidak serentak, pilkadanya akan dilakukan beberapa bulan sebelum habis masa jabatan masing-masing kepala daerah.
Dalam perspektif ekonomi, pelaksanaan pilkada dapat meningkatkan gairah perekonomian di tengah masyarakat, sebab pilkada benar-benar menjadi pesta rakyat, ketimbang pelaksanaannya melalui pemilihan di DPRD.
Nah, dari sinilah banyak yang berasumsi bahwa cost politik untuk pilkada lebih besar ketimbang pemilihan di DPRD. Namun bila melihat sebarannya, peredaran cost politik itu hanya akan terpusat di gedung DPRD saja, sementara sebaran cost politik pilkada tersebar di tengah-tengah masyarakat. Artinya ada pertumbuhan ekonomi masyarakat selama pilkada dibandingkan dengan pemilihan tidak langsung.
At least but not last, manakah yang lebih ugal-ugalan dan jorok antara pilkada dengan pemilihan di DPRD? Menilik dari sisi buruknya tentu kedua-duanya tidak lepas dari money politik. Praktiknya menjadi sarapan wajib pemilih jelang pencoblosan.
Pun begitu money politik di pemilihan di DPRD, coba kita reka ulang kembali pemilihan kepala daerah di masa lampau, disana juga terjadi jual beli dukungan antara kandidat dengan partai politik, jual beli kursi hingga jual beli suara antara kandidat dengan anggota DPRD demi keterpilihannya sebagai kepala daerah.
Mengembalikan pilkada ke pemilihan di DPRD memang tidak menyerap anggaran yang besar, akan tetapi juga tidak akan menghilangkan money politik sepanjang proses pelaksanaannya.
Lebih jauh lagi, kita dapat menilik dari sisi pengkondisian partai pemenang pemilu menjadi kepala daerah dengan alasan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Perkara ini akan lebih mudah pengaturannya bila dilangsungkan pemilihan di DPRD daripada pilkada.
Alih-alih melakukan pendidikan politik dan demokrasi, pengembalian pilkada ke pemilihan di DPRD justru semakin tidak memberikan ruang berdemokrasi dan menghapus hak pilih masyarakat. Sekalipun ini terjadi di posisi pilkada, partai hanya mampu melakukan pengkondisian pada taraf pencalonan, untuk soal keterpilihan tidak bisa diprediksi.
Maka dari itu, bagaimanapun sistem pemilihan kepala daerah permasalahan yang muncul tetap permasalahan yang sama, alangkah baiknya bila diuraikan dulu permasalahannya lalu perkuat undang-undang dan sistem hukumnya. Bila tidak, praktek membangun dinasti kekuasaan akan tetap bergulir di setiap event pemilihan kepala daerah. Motivasinya hanya ada satu prinsip yang gaungkan “ini adalah pertaruhan kelompok kita selama lima tahun kedepan”.
Bila saja pada akhirnya pilkada tetap dikembalikan ke DPRD maka akan banyak hal yang akan ditempuh, walaupun itu tidaklah sulit dan bila itu berhasil, sedikit tidaknya juga akan mempreteli kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.
Apakah akan menjadi badan Ad Hoc atau tidak lagi menjadi lembaga yang permanen di tingkat kabupaten kota. Bersebab tugas dan wewenangnya dalam pemilihan kepala daerah sudah tidak ada lagi.
Lantas apakah dari satu sisi penganggaran ini saja yang kemudian dapat menakar perhelatan pilkada? Pastinya tidak, mengevaluasi pilkada boleh-boleh saja, akan tidak fair apabila mengembalikan pilkada ke pemilihan di DPRD dengan hanya menggantungkan pada satu issue yakni efisiensi anggaran.
Sementara menghilangkan esensi pemilihan dari kalimat dipilih secara demokratis seperti yang telah diamanatkan UUD 1945.
Dengan demikian makna dipilih secara langsung umum bebas rahasia cukup untuk dikesampingkan saja. Efisiensi anggaran tidak setimpal dengan hak politik masyarakat yang datang memilih kepala daerahnya. Semestinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan tali air dari permasalahan pilkada. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan pilkada yang berkualitas.
Terakhir, marilah kita akhiri saja perdebatan apakah tetap melanjutkan pilkada dan atau mengembalikan ke pemilihan ke DPRD, MK telah menerbitkan putusan Nomor 55/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acapkali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia. Seraya membangun asa akan ada penguatan undang-undang dan sistem hukum untuk penyelenggaraan pilkada sehingga dapat mewujudkan pemilihan pilkada yang bermartabat dan berkualitas.
Penulis: Sepri Kurniadi
Dosen Politeknik Aceh Selatan dan Pemerhati Pemilu
Baca berita dan artikel lainnya di Google News dan saluran WhatsApp