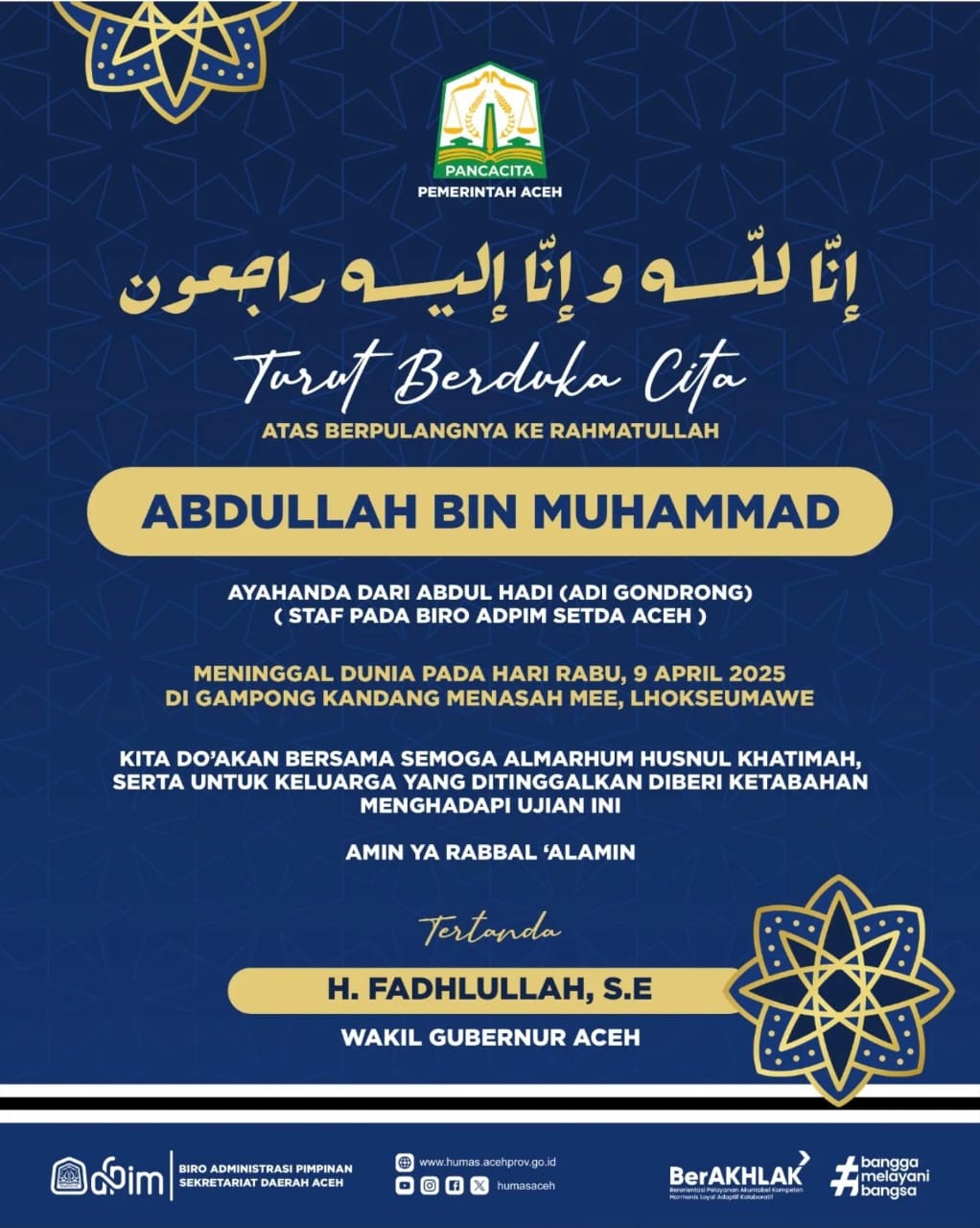Jalan Terang Jurnalisme Koran Kompas
Catatan Darmansyah/Theacehpost.com
SUDAH lama saya tak memelototi koran Kompas. Lama sekali kalau dihitung hari, pekan, bulan, dan tahunnya.
Lama sekali juga kalau saya kembali ke 54 tahun lalu ketika pertama kali menemukannya di sebuah kios kecil di sudut Jalan Merdeka, Tapaktuan.
Kios itu bernama indah, “Flamboyant.” Pemiliknya bernama Abubakar. Lelaki yang sangat senang dipanggil Kelasi.
Si Kelasi bukan pelaut. Bukan anak kapal. Tapi si Kelasi dari gayanya. Bersepatu kets, celana jeans, berkaos oblong dengan tambahan asesori topi pet plus kacamata hitam.
Sempurnalah Abubakar sebagai si “Kelasi” dalam tanda dua petik. Si Kelasi yang yang saya sambangi setiap hari ketika saya masih duduk di bangku sekolah lanjutan pertama. Si Kelasi yang mempersilakan saya membaca koran Kompas secara gratis. Lewat pertukaran timbal balik.
Timbal balik dari pertukaran saya sebagai “loper” part time. Loper yang tidak digaji. Loper yang membuka bundelan Kompas lewat antaran kantor pos untuk kemudian disusun lewat pajangan bergaya eksentrik. Lantas bisa baca sesuka hati.
Kompas di kios Flamboyant kalau dipakai dengan ukuran Jakarta adalah koran kedaluarsa. Terlambat dua hari dari tanggal terbitnya. Tidak lagi up to date. Kompas yang melewati jalan berliku untuk sampai ke pembacanya. Pembaca Negeri di Naca.
Kompas yang dikirim lewat paket pos udara dari Jakarta – Banda Aceh. Diangkut dengan bus ke Tapaktuan. Terlambat dua hari dari hari terbitnya.
Keterlambatan normal.
Kalau musim penghujan hitungan harinya bisa nambah empat lima hari tiba di tangan pembaca.
Walaupun daluwarsa, Kompas si Kelasi tetap menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk artikelnya dan featurenya yang tak lekang oleh waktu.
Sejak hari-hari menjadi loper gratis si Kelasi, saya tak pernah jeda mempelototi Kompas. Mempelototi berita utamanya hingga memamah sampai ke iklan mininya.
Saya hafal luar kepala nama penerbit media itu.
Nama pemimpin umumnya, Petrus Kanisius (PK) Ojong atau Auw Jong Peng-Koen. Pemimpin Redaksinya Jacob Oetama hingga nama Swantoro. Juga tak lekang ingatann saya nama redakatur pelaksana, redaktur, reporter, dan korespondennya.
Hingga kini pun di kepala saya masih terpahat jargon: “amanat hati nurani rakyat” Jargon yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan. Untuk itu saya sering berang kalau ada yang mempelesetkan kepanjangan Kompas– komando pastor.
Pelesetan yang karena ada nama I.J. Kasimo di sana. Anak seangkatan kami tahu siapa Kasimo yang membuat Kompas jadi bulan-bulanan. Padahal “agama” Kompas itu sendiri adalah “kemanusiaan.”
Misi kemanusiaan Kompas nyata. Tak main-main. Kemanusian yang diiwejawantahkannya lewat jurnalisme berskala sepuluh.
Walau pun ia pernah di-ngenyek oleh Rosihan Anwar, tokoh besar pers Indonesia, sebagai jurnalistik “kepiting”.
Istilah ini bukan merujuk kepada sebuah aliran jurnalisme di dunia melainkan hanya sebuah sindiran Kompas pada era akhir tujuhpuluhan.
Mencuatnya gaya jurnalisme ini karena Kompas lebih memilih jurnalisme yang lebih lembut dan dinamis, dibandingkan surat kabar pada masanya yang menganut jurnalisme keras dan sarat kritik tajam terhadap pemerintahan Soeharto.
Jalan jurnalisme yang lebih halus ini diambil setelah Kompas dibredel selama tiga pekan oleh pemerintahan Soeharto di awal tahun 1978.
Saat itu, Jacob Oetama berusaha fokus untuk membangun strategi agar Kompas bisa kembali hadir dan melayani publik.
Sebagai konsekuensinya, Kompas harus menaati sejumlah larangan yang digariskan oleh Orde Baru dalam melakukan tugas jurnalismenya.
Meskipun dikritik oleh tokoh pers dan ditentang oleh sebagian awak redaksinya, strategi inilah yang kemudian membuat Kompas bisa mencapai usia manulanya.
Saya teringat ucapan ST Sularto, salah seorang dari mereka yang berada di barisan puncak keredaksian. Ia dengan kalem menjawab ocehan jurnalisme kepiting itu dengan kalimat santun.
“Itu sebuah jalan budaya. Jalan pencerahan,” kata pria yang akrab dengan sapaan Larto dalam sebuah tayangan dokumenter 50 tahun Kompas.
Lebih lanjut, Larto menjelaskan, jurnalisme kepiting yang dimaksud Rosihan Anwar merujuk kepada cara jalan kepiting.
Ketika kepiting menemui hambatan di depannya, dia akan mundur atau berjalan menyamping lalu mencari jalan lain yang lebih aman. Bila memaksakan diri untuk menabrak halangan di depannya, maka kepiting itu akan mati.
Hal yang sama diibaratkan kepada Kompas. Bila Kompas harus kembali menabrakkan dirinya dengan dinding kekuasaan, yang terjadi selanjutnya, surat kabar tersebut tidak akan pernah ada.
Rikard Bangun, Pemimpin Redaksi Kompas selama lima tahun, kini sudah hijrah ke televisi, menjelaskan, jurnalisme kepiting merujuk kepada pemberitaan redaksi yang selalu memaksimalkan pemberitaan hingga ambang batas.
Ketika mulai ada teguran, kemudian ketajaman pemberitaan diturunkan hingga keadaan pemerintah reda. Begitu seterusnya hingga Orde Baru tumbang dan digantikan reformasi.
Jacob Oetama ketika masih hidup pernah mengatakan Kompas berusaha lebih dinamis usai dibredel. Lebih mandiri.
“Hal yang penting adalah pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada publik dan kekuasaan tak terusik,” tandasnya .
Bahkan Daniel Dhakidae, seorang peneliti minta publik jangan melihat apa yang ditulis di koran. “Read between the line, baca di antara garis.”
“Cara membaca seperti ini susahnya minta ampun. Namun, inilah yang menjaga Kompas tetap aman,” lanjutnya lagi.
Kompas yang amanat itu kini sudah bermetamorfosa. Metamoforsa perpindahan segmentasi. Segmentasi semuanya. Kompas tidak lagi sebagai koran terbesar dengan gelembung oplah bak banjir tsunami.
Tidak ada lagi Kompas di lampu stop atau kios-kios di ujung donya seperti di masa jayanya kios Flamboyant di Tapaktuan.
Koran Kompas hari ini sudah terkulai dari sisi oplah, minat baca dan semuanya.
Untuk itu, ketika saya melewati hari-hari di sebuah rumah di kawasan ……(Saya nggak mau menyebutnya, nanti ke-ge-er-an. Bisa dianggap mbong oleh orang di tanah asoe lhok).
Padahal, hari itu, saya hanya numpang. Numpang karena nggak punya hunian permanen di Jakarta.
Hari itu adalah Sabtu di ujung hari kalender Januari. Saya melangkah ke pintu pagar usai suara derai sebuah motor berlalu melirik ke celah pintu pagar. Langsung menggamit bundel kecil untuk kemudian saya bentang.
Kompas edisi Sabtu.
Gairah saya memuncak menelusuri semua sudut bentangannya. Menghitung jumlah halaman. Jumlah tulisan. Jenis tulisan. Serta berhenti untuk merenung.
Cuma 16 halaman. Cuma empat tulisan tiap halaman. Cuma tulisan reportase dan feature. Sangat sedikit berita politiknya. Sangat sedikit iklannya. Dan banyak lagi yang cuma dan cuma. Juga banyak sedikit-sedikit.
Namun, begitu Kompas saya bentang itu bukanlah koran yang cuma dan cuma. Bukan sedikit dan sedikit. Bukan juga Kompas yang memelas. Kompas yang telah dipinggirkan oleh media online, media sosial. Media berlabel digital.
Entahlah, kata hati saya. Kata hati yang mengajak ke makna jurnalistiknya. Makna ketika pembaca lebih independen. Sejak tingkat kepercayaan pembaca terhadap koran merosot. Sejak media online mengambil ceruk pasar koran
Dan Kompas kembali ke khitahnya. Ada dan tiada dari sisi fisik. Tapi tidak dari sisi jurnalistik. Sebab dari sisi jurnalistik Kompas masih berada di jalan terang.
Jalan terang jurnalistik edisi Sabtunya yang saya bentangkan.
Saya tidak kecewa dengan jurnalistik koran Kompas. Saya tidak mau mencampakkan jargon “journalist never die.”
Saya tidak mau seperti Prof. Drs. Effendi Gazali yang mencampakkan gelar profesornya karena gagal sebagai guru jurnalisme. Gagal ketika menemukan tinggal sedikit wartawan yang baik di negeri ini. Wartawan yang menulis secara benar.
Ia kecewa banyak wartawan yang berkomplot. Berkomplot untuk membunuh jurnalisme. “Dan jurnalisme profesional tinggal menanti ajal,” kata Effendi di sebuah tayangan televisi.
Jurnalisme Kompas masih menuliskan tentang kemanusiaan. Kemanusiaan yang di hari Sabtu itu bicara tentang sagu. Ada enam tulisan panjang yang mereka turunkan.
Dari headline di halaman satu hingga reportase di halaman dua dan ditutup dengan rubrik sosok di halaman enam belas.
Saya puas dengan jurnalisme milik Kompas. Walaupun saya tak bisa membantah analisa Effendi Gazali yang mengatakan, “kini wartawan sungguhan malu menyebut dirinya wartawan”.
“Kalau Anda nggak percaya,” katanya, “datanglah ke sebuah acara. Di sana akan terlihat kantong celana dan baju panitia robek karena wartawan berebut amplop”
Jurnalisme kini bisa dipakai sebagai alat apa saja. Dan jurnalisme kini benar-benar berada di lautan polutan. []