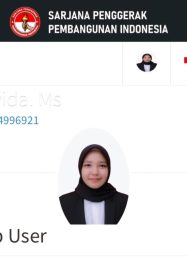Demokrasi Mikrofon
Semua kita punya mulut dan telinga. Semua kita juga menggunakannya sepenuh waktu. Kecuali waktu tidur.
Tapi pernahkah kita berpikir kenapa dua panca indra itu diciptakan dengan jumlah yang berbeda?. Mulut satu telinga dua.
Kita yakin perbedaan jumlah ini di samping pertimbangan teknis dan keindahan sebuah ciptaan, Allah SWT Sang Pencipta menitip iktibar bagi kita di balik perbedaan jumlah dua ciptaan-Nya itu.
Barangkali salah satu iktibar agar sepanjang hidup kita lebih banyak mendengar dari berbicara.
Dengan banyak mendengar maka kita akan lebih banyak mengambil pengetahuan. Sementara orang yang banyak bicara terkadang bukan bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, namun lebih banyak mengundang dosa.
Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitabnya Raudhah Al-‘Uqala wa Nazhah Al-Fudhala menyampaikan, “Orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinga daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga dua buah, sedangkan diberi mulut hanya satu, supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara”.
Dalam kitab tersebut Imam Abu Hatim menjelaskan bahwa sering kali orang menyesal di kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan.
Banyak mendengar bukan berarti tidak boleh berbicara, namun perlu memilah-milah. Kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan mana waktu yang cocok untuk mendengarkan.
Ternyata cara dan frekwensi kita menggunakan mulut dan telinga berhubungan erat dengan kualitas demokrasi di negeri kita.
Budaya kita yang turun temurun lebih cenderung kepada budaya oral atau budaya tutur, mendorong kebanyakan kita sangat telaten berbicara serta kurang sigab mendengar. Bergebu-gebu ingin berbicara dalam setiap momentum, tapi tidak sabar untuk mendengar. Kita seperti sepakat seakan kecakapan berbicara itu simbol kecerdasan. Sedangkan kesabaran dan kearifan mendengar justru dijustifikasikan sikap pasif dan kurang cerdas.
Bahkan kita sangat yakin untuk segera berbicara sekalipun pada saat bersamaan kita belum memahami persoalan yang kita respon cepat dengan mulut itu.
Padahal sejenak saja sabar mendengar, maka dijamin kualitas bicara kita menjadi lebih berkualitas dan tidak memunculkan masalah. Karena dalam interval mendengar ada waktu yang cukup bagi kita untuk berpikir dan bersikap taktis.
Bahkan ketika teknologi informasi menghadirkan mendsos dalam setiap jengkal kehidupan kita, maka seharusnya dominasi peradaban oral kita yang sangat suka berbicara dari mendengar harus kita konversikan menjadi budaya literasi. Budaya suka membaca. Dengan membaca kita mendapatkan ekstrak informasi barulah kemudian kita berbicara. Maka bicara kitapun menjadi lebih subtantif dan berkualitas.
Lihatlah perilaku kita medsos.
Kita dengan mudah melakukan share dan like sebuah berita tanpa terlebih dahulu sedikit susah payah membaca dan memahami konten dan konteks sebuah berita. Dengan bangga kita berlomba meraih prestasi sebagai pihak pertama yang mengshare berita itu, sekalipun berita itu hoax atau lebih besar mudarat dari manfaatnya. Kita juga sangat mudah mencaci maki serta menghina, ketika hanya membaca judul sebuab postingan. Tanpa sedikit bersedia lelah membaca sampai tuntas. Perilaku bermedsos kita seperti ini mewariskan kita dausa jariah.
Begitu juga dengan berbagai berita di media cetak. Kebanyakan kita hanya cukup membaca judulnya saja, lalu dengan menggunakan mulut kita pun berbusa-busa berdiskusi panjang lebar bahkan di luar kontek yang diberitakan itu.
Di panggung demokrasi kita, peradaban kita yang lebih suka dan banyak berbicara dari pada mendengar menyebabkan demokrasi kita menjadi demokrasi mikrofon. Demokrasi yang riuh rendah seperti di tempat pesta Deangan karenanya demokrasi kita pun bermetamorfosis menjadi demokrasi administratif yang jauh dari subtantif.
Di berbagai tempat, termasuk di partai politik dan berbagai varian produk partai politik lainnya, di berbagai momentum yang kita lihat dan dengar adalah perdebatan kering gagasan terkait kepentingan semata. Ruang lingkupnya antara pusat dan dua lutut. Siapa mendapatkan apa.
Sangat jarang kita dengarkan sebuah perdebatan – termasuk di parlemen – yang berbasis gagasan. Gagasan kecil sekalipun. Karena gagasan besar juga bermula dari ide-ide kecil.
Ketika sebuah demokrasi terus menerus tidak dibangun berdasarkan gagasan, maka berbagai output dari proses demokrasi yang berjalan itu akan berdemensi sesaat atau jangka panjang. Padahal ketika negara ini sekapat kita bangun dengan instrumen demokrasi seharusnya yang dihasilkan adalah kemaslahatan visioner yang berjangka panjang.
Dengan pupulasi penduduk Indonesia berada pada urutan pertama se-Asia Tenggara, maka banyak pihak berharap masa depan demokrasi yang berkualitas akan bersemi dari negeri kita.
Lalu kemana arah dermokrasi kita ke derpan. Demokrasi subtantif yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, atau dermokrasi mikrofon?.
Bila kita lebih suka dan banyak menggunakan mulut dari telinga, itu artinya kita masioh nyaman dengan praktik demokrasi mikrofon. []